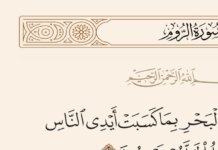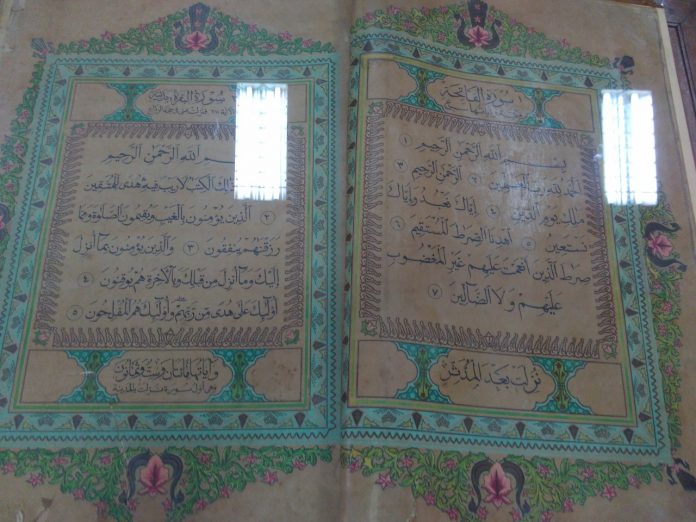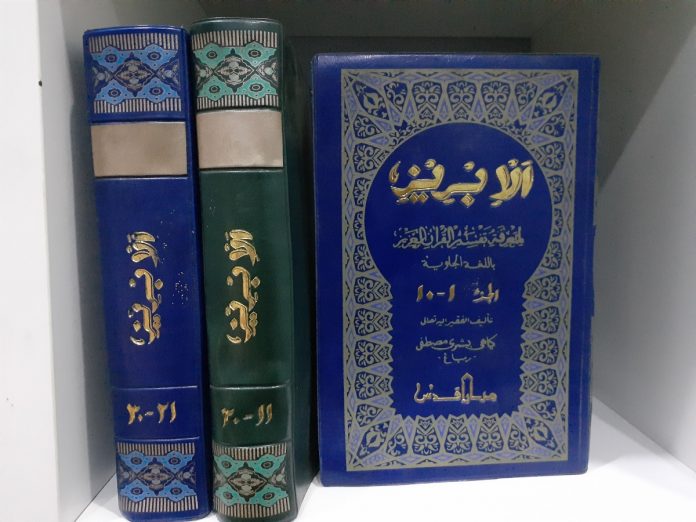Selain kedua putra Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishaq dan Nabi Ismail, juga terdapat utusan Allah yang memiliki kaitan saudara, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Nabi Musa dan Nabi Harun ditugaskan bersama dan kepada kaum yang sama, maka kisah di antara keduanya tak jauh berbeda.
Akan tetapi terdapat riwayat berbeda berkenaan dengan diangkatnya Nabi Harun sebagai nabi. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Harun dan Nabi Musa diangkat sebagai nabi secara bersamaan. Ada juga yang menyebutkan bahwa Nabi Harun diangkat sebagai nabi atas permohonan atau proposal Nabi Musa kepada Allah swt sebagaimana doa Nabi Musa yang terdapat dalam surat Taha [20] ayat 29-35
وَٱجۡعَل لِّی وَزِیرࣰا مِّنۡ أَهۡلِی (٢٩) هَـٰرُونَ أَخِی (٣٠) ٱشۡدُدۡ بِهِۦۤ أَزۡرِی (٣١) وَأَشۡرِكۡهُ فِیۤ أَمۡرِی (٣٢) كَیۡ نُسَبِّحَكَ كَثِیرࣰا (٣٣) وَنَذۡكُرَكَ كَثِیرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِیرࣰا (٣٥)
“…dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (29) yaitu Harun, saudaraku, (30) teguhkanlah kekuatanku dengan (adanya) dia, (31) dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, (32) agar kami banyak bertasbih kepada-Mu, (33) dan banyak mengingat-Mu, (34) sesungguhnya Engkau Maha Melihat (keadaan) kami. (35)” [Q.S. Taha (20): 29-35]
Diangkatnya Harun Sebagai Nabi
Merujuk Tafsir Ibnu Katsir, terdapat dua versi cerita berkenaan dengan permintaan Nabi Musa kepada Allah swt., supaya saudaranya: Nabi Harun, diangkat menjadi nabi. Versi pertama ialah cerita yang bersumber dari Sayyidah Aisyah, tatkala beliau menjumpai sekelompok lelaki di suatu pedesaan yang dilewati ketika berangkat umrah.
Baca juga: Isyarat Pelestarian Alam Dibalik Kisah Nabi Shalih, Unta dan Kaum Tsamud
Ketika Sayyidah Aisyah sedang istirahat dari perjalanannya, beliau mendengar pertanyaan seorang lelaki kepada temannya, “Siapakah orang di dunia yang paling bermanfaat bagi saudaranya?” Teman-teman dari lelaki itu pun kompak menjawab, “Saya tidak tahu.” Menyambung jawaban tersebut, lelaki yang bertanya tadi kemudian bersumpah di hadapan kawan-kawannya, bahwa ia mengetahui siapa lelaki yang paling bermanfaat bagi saudaranya.
Mendengar perkataan yang disertai sumpah, Sayyidah Aisyah pun bergumam, “Menimbang sumpah lelaki itu, yang tak menggunakan kata insyaallah, pasti ia benar-benar mengetahui siapa orang yang dimaksud paling bermanfaat bagi saudaranya.” Tidak lama berselang, lelaki itu melanjutkan perkataannya, “Dia adalah Nabi Musa, ketika memohon kepada Allah Swt., supaya saudaranya diangkat sebagai nabi.”
Seketika Sayyidah Aisyah membenarkan ucapan lelaki itu, dan disertai dengan sumpahnya, “Demi Allah, dia benar!” Berdasarkan riwayat di atas, sehingga kemudian disimpulkan bahwasanya Harun diangkat sebagai nabi atas permohonan Nabi Musa.
Melanjutkan tashdiq-nya, Sayyidah Aisyah menuturkan bahwa, karena permohonan itulah, Allah memuji sikap Nabi Musa, sebagaimana terdapat dalam surat al-Ahzab [33] ayat 69.
وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِیهࣰا
“Dan dia (Musa) seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.” [Q.S. al-Ahzab (33): 69]
Baca juga: Kisah Nabi Hud As dan Kaum ‘Ad Dalam Al-Quran
Selain riwayat Sayyidah Aisyah di atas, pendapat berbeda juga dikemukakan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Harun diangkat Allah swt. sebagai nabi bersamaan dengan diangankatnya Nabi Musa menjadi nabi. Sehingga dapat dimengerti bahwa Harun diangkat menjadi nabi bukan atas permohonan Nabi Musa.
Tafsir Surah Taha Ayat 29-35
Ayat 29-35 dalam surat Taha merupakan lanjutan dari doa Nabi Musa pada ayat sebelumnya, ayat 25-28, yaitu doa “rabbisyrahli shadri, wa yassirli amri, wahlul ‘uqdatan min lisani, yafqahu qauli.” Seutas doa yang sangat masyhur di telingan kaum muslimin. Selanjutnya, Nabi Musa memohon kepada Allah supaya ada seorang dari keluarganya yang membantu beliau. Seseorang dari keluarga yang dimaksud ialah saudara beliau sendiri, yakni Nabi Harun.
Menurut Imam Ahmad ash-Shawi, seperti yang disebutkan dalam Hasyiyah ash-Shawi, permohonan Nabi Musa kepada Allah yang dikaitkan saudaranya, Nabi Harun, ketika diringkas terdapat tiga permohonan. Ketiganya ialah; jadikanlah (ij’al), kuatkanlah (usydud), dan jadikanlah teman (asyrik).
Pertama, dengan redaksi ij’al, Nabi Musa memohon kepada Allah supaya Nabi Harun dijadikan sebagai orang yang membantu (wazir) beliau. Kedua, dengan redaksi usydud, Nabi Musa memohon kepada Allah supaya diteguhkan kekuatan beliau dengan perantara Nabi Harun.
Baca juga: Fashabrun Jamil, Kisah Kebijaksanaan Sang Ayah Saat Ditipu Anak-Anaknya
Penafsiran tersebut juga diungkapkapkan oleh Imam ath-Thabari dalam kitab Jami’ul Bayan fi Tafsiril Qur’an. Ketiga, dengan redaksi asyrik, Nabi Musa memohon kepada Allah supaya Nabi Harun dapat menjadi teman (penafsiran Ibnu Katsir: teman musyawarah) bagi beliau ketika menghadapi berbagai permasalahan yang pelik. Dalam Tafsir Mafatih al-Ghaib atau Tafsir al-Kabir, Syekh Fakhruddin ar-Razi memberikan dua kemungkinan alasan mengapa Nabi Musa memohon supaya diberikan pembantu (wazir).
Pertama, karena Nabi Musa khawatir apabila dirinya tak cukup mampu menyangga perintah Allah yang dibebankan kepada beliau. Kedua, karena beliau meyakini bahwa tolong menolong dalam urusan agama dan memanifestasikan ajaran agama, yang disertai dengan cinta kasih, merupakan suatu keistimewaan yang agung dalam upaya mengajak menuju jalan Allah swt.
Mengakhiri rentetan doanya, Nabi Musa kemudian menyebutkan tujuan beliau yang disandarkan kepada Allah Swt., yaitu supaya senantiasa menyucikan-Nya dan mengingat-Nya. Nabi Musa juga mengungkapkan keyakinan beliau bahwa, Allah melihat keadaan hamba-Nya. Sehingga–menurut Imam Ibnu Katsir–pilihan dan pemberian Allah akan kenabian, serta diutusnya beliau untuk menghadapi Fir’aun, tetaplah memiliki hak atas segala pujian. Wallahu a’lam bish shawab


![Jahiliyah Modern: Membaca Ulang Al-Mā’idah [5]:50 sebagai Kritik Hedonisme, Materialisme dan Kemerosotan Moral](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2025/12/2807131-218x150.jpg)