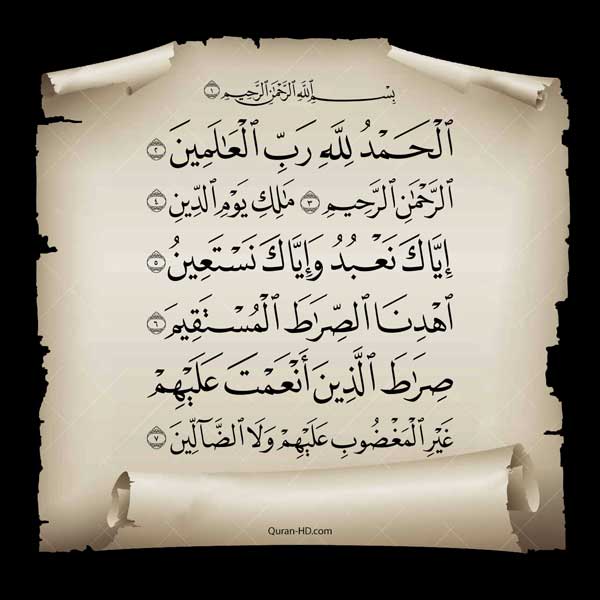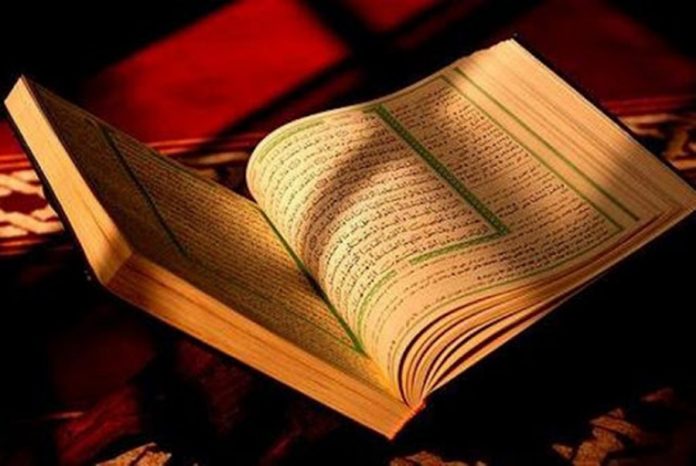Dalam kenyataan sosial, tidak jarang kita menyaksikan orang beragama yang bersikap tidak berdasarkan nilai-nilai agama. Misalnya, sesorang yang mendaku diri sebagai muslim namun malah menjadi tersangka dalam kasus penipuan, korupsi, dan tindakan kejahatan lain. Hal itu sesungguhnya terjadi karena terdapat jarak antara seseorang dengan nilai-nilai agama yang dianutnya.
Baca juga: Cara Menghayati Kebaikan Allah Swt dan Kebesaran-Nya dalam Al-Quran
Ibadah keagamaan yang dilakukannya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tidak ada makna mendalam yang ditemuinya dalam ibadah yang dia lakukan. Amal ibadah tidak memberikan pengaruh pada perubahan serta perbaikan diri. Keadaan semacam itu oleh para sarjana disebut sebagai alienasi atau keterasingan. Berkaitan dengan hal itu, bagaimana pandangan Alquran tentang alienasi dan penyelesaiannya?
Keterasingan dan Penyebabnya
Alienasi atau keterasingan menurut Phillip Stanworth, dalam “Encyclopedia of Religion and Society” adalah keadaan terasing yang dialami oleh individu atau masyarakat terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan bahkan terhadap diri sendiri. Alienasi dalam makna negatif ini -dengan mengutip pendapat Erich Fromm- dalam artikelnya berjudul “Erich Fromm on the Alienation of Modern Man” mengkategorikannya sebagai ketidaksehatan mental. Alquran menyinggung persoalan ini pada QS. Alhasyr [59]: 19.
وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْۗ اُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ
“Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.”
Keterasingan dalam narasi Alquran disebabkan karena lupa kepada Allah. Imam al-Mawardi dalam tafsir al-Nukat wa al-‘Uyun (juz 5, h. 511), menyebut hubungan kausalitas dari melupakan Tuhan. Terdapat lima makna lupa yang menyebabkan seseorang menjadi terasing, yaitu:
- Orang yang melupakan Allah atau meninggalkan perintah Allah, maka dia akan melupakan diri mereka untuk melakukan kebajikan. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Hibban.
- Melupakan hak Allah akan menyebabkan lupa pada hak diri sendiri, sebagaimana pendapat Sufyan.
- Melupakan Allah dengan tidak bersyukur dan mengagungkan kebesaran-Nya akan menyebabkan lupa pada azab yang telah diingatkan oleh sebagian orang. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu ‘Isa.
- Melupakan Allah dengan melakukan perbuatan dosa, akan menyebabkan lupa melakukan taubat, seperti pendapat Sahl.
- Melupakan Allah dalam keadaan berkelimpahan, akan membuat lupa pada Allah saat kesusahan.
Baca juga: Tafsir Surah Al-A’raf Ayat 199: 3 Konsep Kesalehan dalam Harmonisasi Sosial
Dalam diskusi modernisasi yang ditandai dengan kelahiran era digital terdapat unsur kehidupan yang memungkinkan seseorang menjadi lupa kepada Tuhan. Sesuatu yang juga menjadi pangkal alienasi beragama. Haochen Bai dan Kexin Gao, dalam “ The Study of Social Media Alienation in the Digitized World” menyebut dua sebab seseorang menjadi terasing, yaitu: “worship of technology” dan konsumerisme.
“Worship of technology” secara sederhana dimaknai sebagai “penyembahan pada teknologi” dalam arti menjadikan teknologi informasi sebagai preferensi ideologis, sumber kesenangan, pengalaman, dan imajinasi. Teknologi informasi dianggap sebagai kunci yang akan menyelesaikan setiap permasalahan, meskipun sebenarnya tidaklah demikian.
Selain itu, terdapat pula faktor konsumerisme, yaitu perilaku masyarakat dalam aktivitas konsumsi yang berorientasi pada pengakuan orang lain, bukan karena kebutuhan. Tindakan ini biasanya dilakukan secara impulsif atau tiba-tiba. Dalam situasi semacam itu, seseorang kehilangan dirinya melalui ketidakterlibatan pertimbangan akal untuk mengonsumsi dan menggunakan sesuatu. Dirinya dikontrol oleh obsesi-obsesi yang dibentuk oleh pasar dan komunitas tertentu.
Baca juga: Relasi Antara Konsep Sabar dan Gaya Hidup Frugal Living
Nurcholish Madjid dalam “Peranan Agama dalam Kehidupan Modern-Industrial” (h. 150-151) menyebut bahwa kontrol media informasi terhadap manusia atau urusan-urusan yang berkaitan dengan teknologi adalah sebagai bentuk objektivisme yang dengan sendirinya akan bertentangan dengan subjektivisme manusia. Terjebaknya manusia pada teknologi informasi, konsumerisme, dan objektivisme akan membuat manusia kehilangan perasaannya. Kediriannya didominasi oleh media, bukan berdasarkan interaksi nyata dalam kehidupan sosial.
Kehilangan perasaan itu juga berarti pengingkaran terhadap diri (depersonalisasi), yang menyebabkan kehilangan makna dan rasa kemanusiaan (dehumanisasi), yang pada akhirnya mengakibatkan seseorang tidak lagi mengenali hakikat dirinya, makna, dan tujuan hidup. Kehidupan serba digital yang mengalihkan fokus manusia akan mempersempit dan membatasi ruang komunikasi dengan Tuhannya melalui peribadatan yang penuh kekhusyukan dan perenungan. Melalui proses itulah manusia menjadi teralienasi atau terasing dari nilai-nilai tertinggi agama.
Baca juga: Wahyu Al-Quran dan Keteladanan Nabi Muhammad Saw Sebagai Pejuang Kemanusiaan
Dengan perasaan asing terhadap agama dan Tuhan itulah, tidak mengherankan jika seseorang yang meskipun telah menginjak usia dewasa, dia masih mencari-cari makna hidup, kebingungan tentang tujuan hidup, serta bersikap tanpa berdasarkan nilai dan ajaran agama.
Agama tidak berperan sama sekali dalam kehidupan. Gejala-gejala itu sesungguhnya nyata dan terlihat dalam realitas faktual bangsa kita. Perusakan alam, penggelapan dan pencucian uang hasil korupsi, ketidakadilan aparat dan penegak hukum dan lain-lain dilakukan oleh orang-orang yang beragama.
Mereka teralienasi dari agama dan Tuhan. Semua itu terjadi karena tidak melibatkan Tuhan atau secara sengaja melupakan Tuhan dalam melakukan tugas-tugas dan pekerjaan.
Semua penyebab yang telah disebut di atas bermuara pada krisis dalam diri manusia. Menurut Alquran krisis itu berakar pada dua hal, yaitu: hati, akal, penglihatan, dan pendengaran yang tidak berfungsi dalam pengenalan kepada Allah serta sikap emosi yang ambivalen. Dalam QS. Ala’raf [7]: 179, Allah menjelaskan karakteristik orang-orang yang lengah.
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَاۖ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَاۖ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَاۗ اُولٰۤىِٕكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۗ اُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ
“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk (masuk neraka) Jahanam (karena kesesatan mereka). Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat (ayat-ayat Allah), serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.”
Imam al-Qurthubi dalam al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an (juz 7, h. 324), memberi penjelasan tentang akal yang tidak berpikir, yaitu orang-orang yang tidak memanfaatkan akalnya untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, balasan, dan azab Allah.
Pada saat yang sama, telinga mereka tidak mau mendengarkam nasihat-nasihat kebaikan. Imam al-Baydhawi dalam Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil (juz 3, h. 43), menambahkan tentang fungsi hati yang tidak digunakan untuk mengenal Allah Yang Maha Benar. Allah mempertegas hal tersebut pada QS. Annahl [16]: 108.
اُولٰۤىِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ
“Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci hati, pendengaran, dan penglihatannya. Mereka itulah orang-orang yang lalai.”
Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi dalam Khawathir Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi (juz 13, h. 239), menjelaskan makna hati yang dikunci Allah. Ia adalah hati yang dipenuhi dengan keingkaran sehingga iman tidak dapat masuk ke dalamnya. Hati yang menjadi tempat segala informasi yang datang dari berbagai indera, terutama dari penglihatan dan pendengaran yang tidak berfungsi dengan baik. Hal kedua yang menjadi krisis manusia adalah perasaan ambivalensi. Hal itu disebut Alquran pada QS. Annisa [4]: 143.
مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَۖ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَاۤءِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا
“Mereka (orang-orang munafik) dalam keadaan ragu antara yang demikian (iman atau kafir), tidak termasuk golongan (orang beriman) ini dan tidak (pula) golongan (orang kafir) itu. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah (karena tidak mengikuti tuntunan-Nya dan memilih kesesatan), kamu tidak akan menemukan jalan (untuk memberi petunjuk) baginya.”
“Mudzabdzabin” pada ayat ini dimaknai sebagai orang-orang yang ragu. Yaitu sebuah keadaan psikologis seseorang saat diombang-ambingkan oleh setan dan nafsu. Keadaan mereka antara beriman dan kekafiran seperti dijelaskan oleh Imam al-Nasafi dalam tafsir Madarik al-Tanzil wa Haqa’iq al-Ta’wil (juz 1, h. 408).
Segala perwujudan tindakan dan tingkah laku yang menggiring pada keterasingan bersumber pada krisis dalam diri. Hal itu menjadi faktor dominan yang menyebabkan seseorang menjadi terasing dari Tuhan dan dirinya sendiri.
Penyelesaian
Cara terbaik mengatasi alienasi beragama adalah dengan mengenali Tuhan sebagai tujuan utama dan tertinggi. Dengan pengenalan yang baik kepada Tuhan, seseorang akan mengerti tujuan hidupnya. Kesadaran dan pengenalan kepada Tuhan akan menjadi dasar segala kebaikan yang perwujudannya dapat dilihat dari niat, sikap, dan perbuatan yang mengandung nilai-nilai ideal.
Untuk sampai pada pengenalan itu, tidak ada jalan lain kecuali dengan terus menerus belajar, memahami, dan merenungi segala tanda-tanda yang datang dari Tuhan, baik yang tersurat maupun yang tersirat.
Langkah-langkah kehidupan yang berada di bawah bimbingan Tuhan tidak hanya menjadi ruang privat untuk dirinya dan Tuhannya, melainkan juga terwujud dalam berbagai kesalehan sosial. Untuk meraih tujuan itu, manusia harus memberi kesempatan dirinya mendekat kepada Tuhan agar memperoleh makna-makna terdalam tentang kehadirannya di dunia.
Hal tersebut di atas tidak hanya membuat seseorang menjadi terhindar dari perasaan terasing dengan diri dan agamanya, melainkan juga akan menjadikannya sehat secara mental. Seperti dikatakan oleh Matt Karamazov bahwa kesehatan mental ditandai dengan hidup yang produktif, tidak terasing, karena mampu menghubungkan diri kepada dunia dengan kasih sayang.
Ketidakterasingan juga ditandai dengan kemampuan menggunakan akal untuk memahami realitas secara objektif, menjalankan kehidupan dan menilai diri sebagai entitas individu yang unik -yang menyatu dengan sesama- serta tidak tunduk pada otoritas irasional yang mengontrol diri. Selain itu, memiliki kerelaan dan menerima otoritas rasional, yaitu hati, nurani, dan akal budi. Memahami kehidupan sebagai kesempatan berharga yang harus disyukuri.



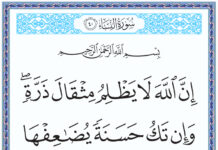

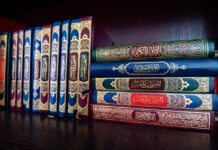







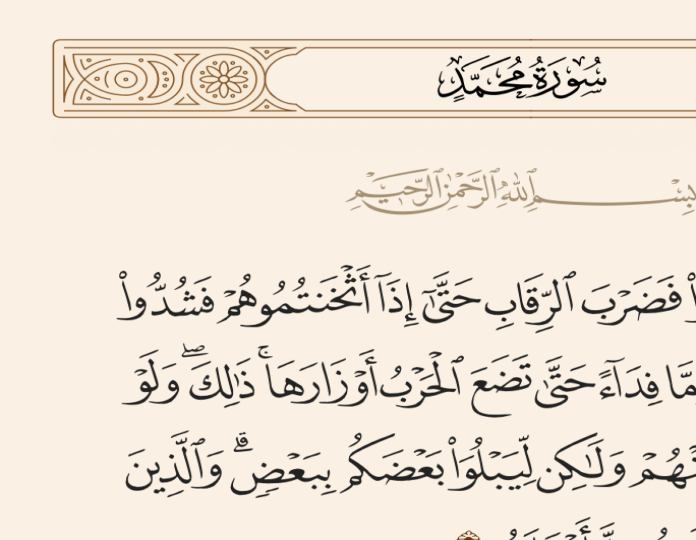
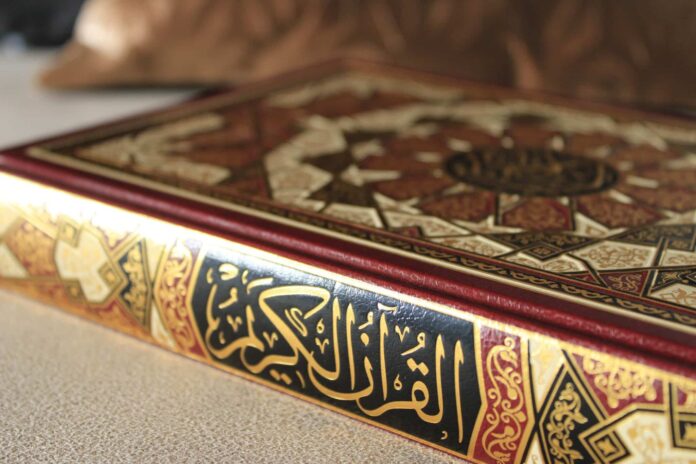
![Al-Futuwwah dan Urgensinya: Refleksi Surah Alkahfi [18]: 13 Al-Futuwwah dan Urgensinya: Refleksi Surah Alkahfi [18]: 13](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2023/10/photo-1598723106443-27f8bd0591b4-696x463.jpg)