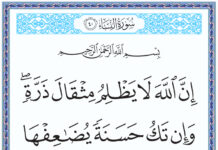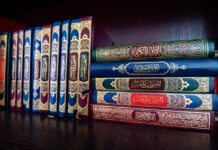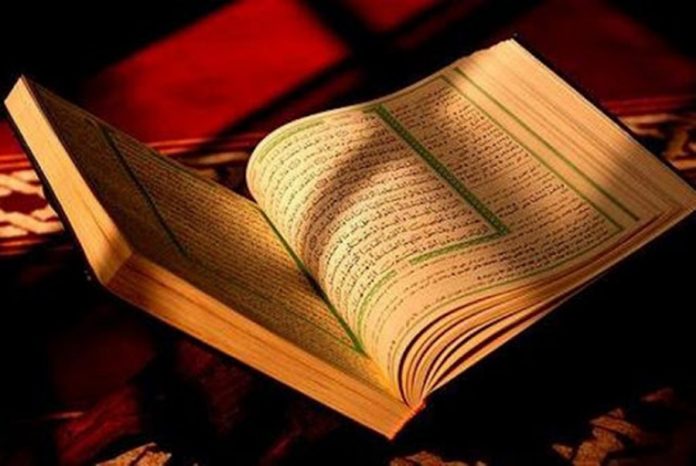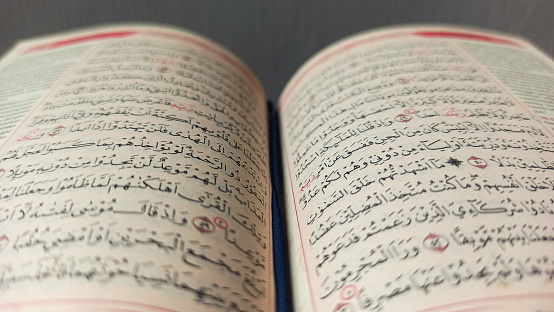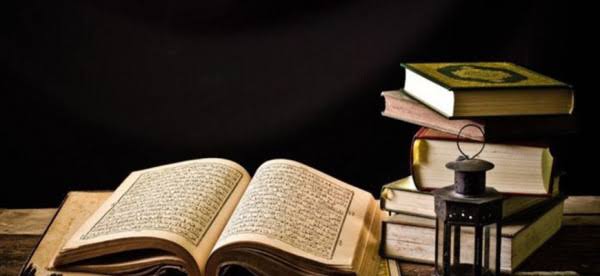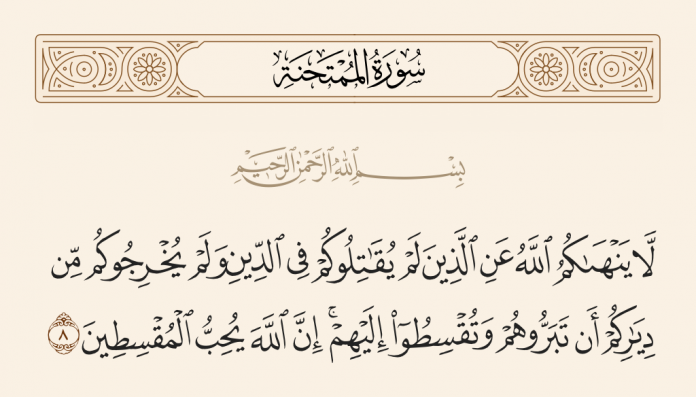Salah satu kepribadian dan kebiasaan yang dimiliki oleh sebagian dari orang-orang Yahudi yang diceritakan oleh Alquran adalah upaya politisasi kitab suci, pemalsuan dan pendistorsian terhadapnya. Di beberapa ayat, Allah swt. menunjukkan kelancangan mereka mengubah dan mendistorsi isi teks-teks suci mereka sesuai dengan hawa nafsu dan hasrat duniawi belaka.
Di antara ayat Alquran yang menyingkap tindakan mereka adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 78,
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران: 78]
“Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan: “Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah”, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui.” Q.S. Ali imran [03]: 78
Baca Juga: Politisasi Ayat dan Hadis dalam Sejarah Islam
Kaum Yahudi dikenal sebagai kelompok yang sering kali menyembunyikan kebenaran. Salah satu misalnya adalah kebenaran tentang ciri-ciri nabi terakhir yang sudah tampak dalam diri Rasulullah saw. meski informasi tentang hal tersebut pernah disampaikan oleh seorang pendeta Yahudi yang amanah kepada paman Nabi, Abu Thalib ketika dalam perjalanan menuju Syam.
Dalam ayat di atas, diterangkan bahwa salah satu kebiasaan yang sering mereka lakukan adalah melakukan distorsi dan pemelesetan kata kemudian mengatakan bahwa apa yang mereka katakan itu adalah kitab suci berasal dari Allah swt. padahal nyatanya bukan. Hal itu mereka lakukan dengan motif-motif tertentu dan niat buruk yang terselubung. [Al-Tafsir al-Wasith, juz 2, hal. 156]
Mengutip dari al-Dahhak yang meriwayatkan dari Sahabat Ibnu Abbas ra., Imam al-Baghawi menjelaskan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan Kaum Yahudi dan Nasrani yang melakukan distorsi dan penyelewengan terhadap kitab taurat dan injil. [Tafsir al-Baghawi, juz 2, hal. 59] sehingga kesucian dan keautentikan dua kitab suci tersebut menjadi ternodai akibat ulah penambahan dan pengurangan di sana-sini. Hal itu mereka lakukan dalam keadaan sadar dan didorong oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi belaka.
Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini ingin mengabarkan prilaku sekelompok orang Yahudi yang kerap kali melakukan pembodohan dan penipuan kepada orang awam tentang isi kitab Allah. mereka melakukan tahrif atau perubahan seperlunya kemudian mengumumkan kepada khalayak bahwa itu berasal dari Allah swt. Padahal itu adalah suatu kedustaan belaka. [Tafsir Ibnu Katsir, juz 2, hal. 65]
Prilaku menyimpang orang Yahudi yang diceritakan dalam Alquran di atas hendaklah menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak bermain-main dengan sakralitas agama demi kepentingan dunia, baik dalam bentuk politisasi kitab suci atau semacamnya.
Baca Juga: Beda Orientasi Politis Penafsiran Sayyid Qutb dan Hamka
Syaikh Ibnu Ajibah menjelaskan bahwa tindakan penyelewengan terhadap al-kitab yang dilakukan oleh orang Yahudi setidaknya memberikan kita warning untuk tidak menjadikan agama sebagai tunggangan dalam memenuhi ambisi pribadi.
Seorang ulama tidak boleh menyampaikan sesuatu yang dilatari oleh kepentingan pribadi. Seorang pemegang kekuasaan juga tidak boleh melakukan tipu daya dan cara kotor untuk mendapatkan dukungan dan kepentingan pribadi lantas mereka berdalih atas nama Alquran untuk menjustifikasi tindakan yang mengandung kepentingan pribadi dan hawa nafsu tersebut. [Al-Bahr al-Madid, juz 1, hal. 373].
Dari ayat ini, dapat diambil pelajaran bahwa sebagai umat Islam, kita jangan sampai mengikuti kebiasaan kaum Yahudi yang gemar melakukan politisasi kitab suci demi kepentingan pribadi. Terlebih menjelang tahun politik ini, kita jangan sampai cawe-cawe untuk menjustifikasi atau mendukung pilihan kita dengan berdalih atas nama agama atau kitab suci. Wallahu a’lam.