Setelah Aksin Wijaya mengulas tentang wacana mufasir dengan nalar normatif dan rasional yang sudah tertulis dalam tulisan sebelumnya Normatif dan Rasionalis: Dua Tipologi Nalar Tafsir Gender. Selanjutnya, dibahas tentang hermeneutika filosofis-dekonstruksi dalam menalar tafsir gender. Hermeneutika yang digunakan Aksin ini merupakan kritik lebih lanjut terhadap kelompok normatif dan rasionalis.
Langkah awal yang dilakukan Aksin adalah memahami kembali konsep wahyu Tuhan. Hal ini, ia lakukan bukan untuk meragukan, apalagi menolak keberadaan wahyu Tuhan, melainkan untuk menggali autentisitas pesan Tuhan. Pemahaman kembali yang ia lakukan terhadap wahyu Tuhan untuk membongkar selubung budaya yang ada dalam mushaf yang kini diterima umat muslim.
Memahami konsep wahyu Tuhan, bagi Aksin adalah memilah definisi term wahyu Tuhan, Alquran, dan mushaf Usmani dengan nalar dekonstruktif Muhammad Arkoun. Dalam terminologi meanstream, antara wahyu Tuhan, Alquran, dan mushaf Utsmani dipahami dengan makna yang saling tumpang tindih. Aksin mencontohkan definisi Alquran menurut Ali al-Shabuni terlebih dahulu. Menurut al-Shabuni, dalam al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an-nya, Alquran adalah kalam Allah yang melemahkan yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad Saw., melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf-mushaf, yang ditransfer kepada umatnya secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, dimulai dari surah Alfatihah dan ditutup dengan surah Alnas.
Baca Juga: Dua Tipologi Nalar Tafsir Gender
Pemilahan dan kategorisasi ini Aksin lakukan untuk mengetahui mana wahyu sebagai kalam Tuhan yang transendental dan tak terbatas, mana wahyu yang bersifat historis yang diturunkan dengan bahasa Arab kepada para Nabi, dan mana wahyu yang diwujudkan dalam bentuk tulisan. Bagi Aksin, wahyu adalah kalam Tuhan tanpa lafaz. Alquran adalah wahyu Tuhan yang terucap menggunakan bahasa Arab, dan mushaf Utsmani adalah korpus resmi tertutup.
Aksin mengatakan, pada masa Utsman bin Affan sepakat bahwa mushaf Utsmani adalah Alquran korpus resmi yang tertutup. Sebagai korpus resmi tertutup, mushaf Utsmani menjadi kitab tertulis dalam Islam yang dianggap otoritatif dan tidak ada perubahan sama sekali hingga kini. Sebagai pesan Tuhan yang ditulis dengan bahasa Arab, maka dia memastikan mushaf Utsmani juga mengandung pesan budaya masyarakat Arab.
Atas pemahaman tersebut, Aksin menilai hermeneutika filosofis-dekosntruktif tepat digunakan untuk melepaskan pesan Tuhan dari selubung budaya Arab klasik. Pembacaan ini juga berguna untuk mengembalikan budaya Arab ke habitat sosialnya sendiri, dan mengembalikan pembaca pada habitat sosialnya sendiri. Dengan hermeneutika ini, antara teks, subjek budaya Arab, dan pembaca saling berdialog mencari solusi produktif di tengah realitas kekinian. Pembacaan ini sebenarnya juga masih bertumpu pada teks, tetapi teks itu dibaca secara filosofis, kritis, dekonstruktif dan dalam konteks pembaca.
Selanjutnya, yang dilakukan oleh Aksin adalah mengomentari pendapat dua nalar tafsir gender dalam lanskap intelektual Islam klasik dan modern, yakni kalangan normatif dan rasional.
Baca Juga: Husein Muhammad dan Pembacaan Al-Quran Berperspektif Gender
Kritikan terhadap kelompok normatif
Menurut Aksin, pembacaan kelompok normatif terhadap surah Alnisa’ [4]: 1 sebenarnya agak rancu dan ambigu. Alasannya, karena dibolehkannya pengalihan makna lafaz dari bentuk mudzakkar ke muannas atau sebaliknya. Dan hal itu biasanya terletak pada kebiasaan masyarakat Arab yakni bersifat sama’i. Padahal, lafaz nafsun wahidah ini terikat dengan dilalah lafdziyah atau secara linguistik lafaz tersebut adalah feminim “perempuan”. Kemudian, kalangan normatif juga mengatakan lafaz zaujun yang dimakna sebagai pasangan laki-laki. Seharusnya, lafaz zaujun terikat dengan dilalah lafdziyah menjadi zaujatun yang artinya perempuan. Dengan demikian, dalam konteks ayat itu menafsiri zaujatun sebagai “Siti Hawa”, layak dipertanyakan.
Kritikan terhadap kelompok rasional
Aksin mengatakan, pola pemikiran kalangan rasional juga terbuka untuk diperdebatkan, khususnya dalam melakukan pembacaan surah Alnisa’ [4]: 1. Karena mereka juga ternyata mengacu pada lafaz nafsun wahidah seperti halnya dengan kelompok normatif. Namun perbedaannya, kelompok rasionalis hanya mengalihkan makna kata. Sehingga, berbeda dengan kalangan normatif, tanpa melihat konteks gramatikal ayat dalam konteks sosio-historisnya. Tepat pada lafaz “ nafsun wahidah” kelompok rasionalis memaknai “jenis yang sama”.
Filosofis-Dekonstruktif dalam menalar surah Alnisa’ [4]: 1
Hal yang perlu dikritisi dari dua pola pembacaan di atas berkisar pada dua aspek. Pertama, mereka terlalu menekankan pemahaman atau pembacaan Alnisa’ [4]: 1, tepatnya pada lafaz “nafsun wahidah” tanpa melihat realitas historisnya. Kedua, mereka telah menggunakan ayat tersebut sebagai sentral yang menentukan posisi kesetaraan atau diskriminasi gender, tanpa melihat konteks gramatikal ayat dan konteks sosial-historisnya. Padahal, menurut Aksin ayat tersebut memiliki kenyataan linguistik dan kenyataan sosio-historisnya.
Baca Juga: Dua Faktor Pemicu Bias Penafsiran Ayat Relasi Gender
Surah Alnisa’ [4]: 1 disebut dalam berbagai pendapat sebagai ayat madaniyah, yakni ayat yang turun pasca hijrah. Namun, pembuka ayat tersebut justru menggunakan ciri-ciri surat makkiyah, yakni ya ayyuhan nas. Bagi Aksin, sebagai bagian dari ayat madaniyah, maka secara realitas historis yang menjadi titik pembahasan seharusnya adalah perintah untuk bertakwa (ittaqullah). Seperti yang maklum diketahui, rata-rata ayat madaniyah menggunakan seruan ya ayyuhal ladzina amanuu (wahai orang-orang yang beriman).
Artinya, ayat tersebut bagi Aksin dengan pembacaan filosofis-dekonstruktif tidak mutlak berbicara mengenai gender. Justru ayat tersebut lebih condong pada penempatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks profesional, moral, khususnya ketakwaan. Siapapun yang memenuhi kriteria tersebut, maka dialah yang mulia di sisi Allah Swt.
Wallahu a’lam.













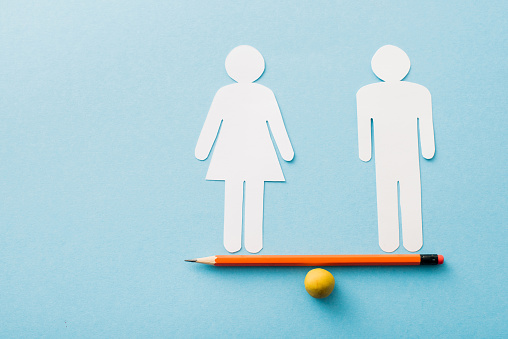



![Tafsir Surah Alnur [24]: 35; Allah Adalah “Cahaya di Atas Cahaya” Tafsir Surah Alnur [24]: 35; Cahaya Sebagai Esensi Ilahi](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2023/04/istockphoto-1163653359-170667a.jpg)



