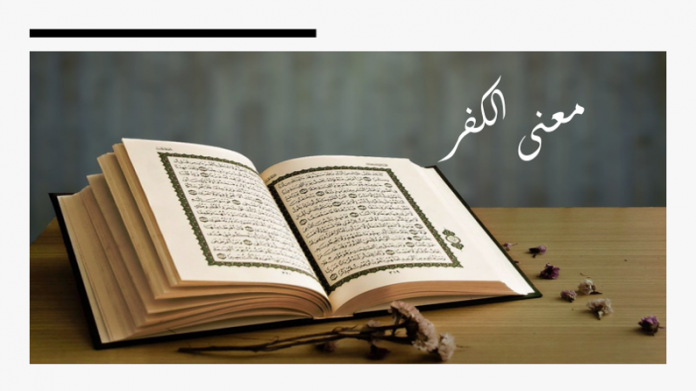Heddy Shri Ahimsa-Putra dalam tulisannya yang berjudul “The Living Al-Qur’an: Beberapa Perspektif Antropologi”—dimuat dalam Jurnal Walisongo Volume 20 Nomor 1 Tahun 2012—mengemukakan bahwa salah satu makna Alquran bagi masyarakat yaitu sebagai kitab suci yang dikeramatkan. Oleh karena posisinya yang keramat tersebut, maka fisik Alquran harus dimuliakan.
Ada banyak cara untuk memuliakan fisik (baca: mushaf) Alquran. Contoh yang paling jelas yaitu bahwa seseorang harus suci dari hadas besar dan kecil untuk dapat menyentuh mushaf Alquran. Menariknya, selain yang berdasarkan ajaran agama, ada juga perilaku memuliakan Alquran yang berdasarkan pada tradisi.
Baca Juga: Living Quran; Melihat Kembali Relasi Al Quran dengan Pembacanya
Contoh tradisi memuliakan mushaf Alquran yaitu penggunaan alat tunjuk ketika belajar atau membaca Alquran. Tradisi itu ada dalam masyarakat Banten, dan mungkin masyarakat lain di nusantara. Di (sebagian) masyarakat Banten, alat tunjuk Alquran itu disebut panuduh atau tutuduh—berasal dari Bahasa Sunda “tuduh”, yang berarti “menunjuk”.
Penggunaan alat tunjuk dalam membaca Alquran yang berupa tongkat kecil seukuran sumpit atau sedotan, selain bertujuan untuk mendapatkan fokus huruf atau ayat yang dibaca, dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap Alquran; karena menunjuk ayat-ayat Alquran dengan jari dianggap tidak hormat.
Kini, panuduh itu telah menjelma dalam nama dan rupa yang baru. Di toko-toko buku, dapat ditemukan kalam atau qolam, alat tunjuk Alquran yang biasanya terbuat dari plastik dengan warna yang terang—meskipun ada juga yang terbuat dari kayu atau bambu, tetapi lebih jarang ditemukan—dengan hiasan tertentu di bagian atasnya.
Pada masa lalu, panuduh terbuat dari lidi kelapa (Cocos nucifera), lidi aren (Arenga pinnata), ranting bambu (Bambusoideae), atau batang daun dadap (Erythrina variegata). Ada maksud yang bermakna doa dalam pemilihan bahan-bahan untuk panuduh itu.
Lidi pohon kelapa dan pohon aren serta ranting bambu dipilih karena ketiga tanaman itu dianggap memiliki banyak manfaat: buah kelapa, buah aren, dan tunas bambu dapat dikonsumsi; daun kelapa dan aren untuk membuat atap; lidi kelapa dan aren—yang didapat dari ruas-ruas daunnya—dapat dijadikan sapu; sementara batang kelapa dan batang bambu merupakan bahan bangunan.
Ada kaidah tersendiri dalam memilih ranting bambu sebagai panuduh; yaitu dengan menghitung ruas ranting bambu berdasarkan urutan kata dari Bahasa Jawa Banten: belet, peteng, calakan, lancar. Belet berarti “bodoh”, peteng berarti “gelap”—simbol dari kebodohan, calakan berarti “cerdas”, sementara lancar memiliki arti yang sama dengan kata lancar dalam Bahasa Indonesia.
Panuduh dari batang daun dadap berupa batang kecil yang menghubungkan daun dengan dahan pohon dadap, yang sudah mengering. Bagian dalam batang daun dadap menyerupai gabus; dapat dipisahkan dari batang dengan cara mendorongnya keluar dengan lidi atau benda lain. Setelah gabusnya keluar, batang daun dadap akan menyerupai sebatang pipa kecil—atau sedotan.
Baca Juga: Relasi Islam, Alquran, dan Budaya
Kesemua bahan panuduh itu merupakan simbolisasi doa. Lidi dari pohon kelapa dan pohon aren serta ranting bambu merupakan simbol dari manfaat. Harapan dari penggunaan panuduh dari bahan-bahan tersebut yaitu bahwa seorang pembelajar atau pembaca Alquran bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri dan masyarakatnya.
Sebuah panuduh dari ranting bambu harus memiliki jumlah ruas yang jika dihitung berdasarkan urutan kata—belet, peteng, calakan, lancar—jatuh pada kata calakan atau lancar; tidak boleh jatuh pada kata belet atau peteng. Itu adalah doa agar seorang pembelajar dan pembaca Alquran diberikan kecerdasan dan kelancaran—serta dijauhkan dari kebodohan—ketika belajar Alquran.
Sementara itu, batang daun dadap yang bolong merupakan lambang dari kelapangan, keluasan, atau kelancaran; yang dimaknai sebagai harapan akan ketiadaan hambatan dalam belajar Alquran serta kelapangan hati dalam menerima ilmu dari Alquran.
Demikanlah gambaran mengenai salah satu tradisi masyarakat Banten dalam memuliakan Alquran yang mewujud dalam panuduh. Lebih jauh lagi, penggunaan alat tunjuk baca Alquran yang tradisional itu, selain dalam rangka memuliakan Alquran, juga sebagai simbolisasi doa bagi para pembelajar dan pembaca Alquran.