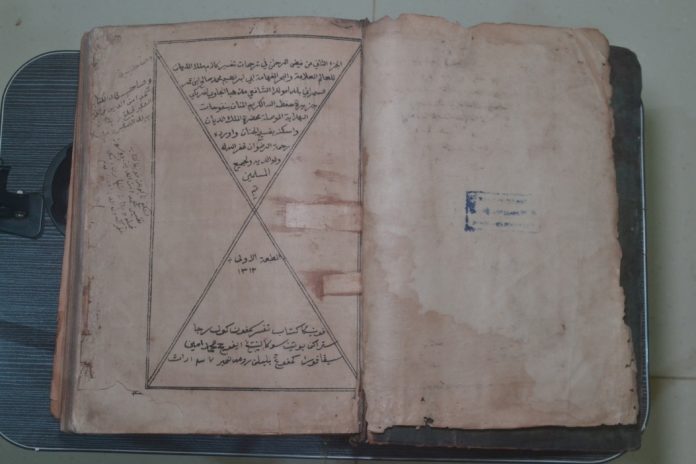Dalam bahtera mulia bernama rumah tangga, anak merupakan salah satu rezeki terbesar yang dianugerahkan Allah Swt. Alquran bahkan menyebutnya sebagai perhiasan (Q.S. 18: 46), kebanggaan (Q.S. 57: 20), dan penyejuk hati (Q.S. 25: 74) bagi manusia. Namun selain itu, Alquran juga menyebutkan bahwa kehadiran seorang anak adalah amanah yang menjadi ujian (fitnah) (Q.S. 8: 28; 64: 15) bagi orang tuanya, bahkan terindikasi juga dapat menjadi musuh (‘aduww) bagi keduanya (Q.S. 64: 14).
Oleh karena itu, orang tua memiliki peranan penting dalam mengasuh dan membimbing anak-anaknya sehingga mengejawantah predikatnya sebagai perhiasan dan kebanggaan, yakni anak-anak yang berbakti dan bermanfaat. Dalam konteks ini, peran keduanya—ayah dan ibu—secara bersama begitu penting. Sebab, beberapa penelitian menyebutkan bahwa kebanyakan anak yang dibesarkan tanpa bimbingan ibu cenderung berkepribadian lemah, sementara anak tanpa ayah cenderung keras.
Dengan demikian, jangan sampai anak dengan orang tua yang lengkap kehilangan bimbingan dari salah satu orang tuanya. Kehadiran sosok ayah dan ibu merupakan modal fundamental bagi tumbuh kembang seorang anak. Adapun dalam konteks ini, ayah menjadi sorotan utama dalam pengasuhan anak. Sebab tidak jarang, seorang anak kehilangan hak pengasuhan dari ayahnya karena terlalu sibuk dengan hal lain. Fenomena ini disebut “fatherless”, yakni kondisi pertumbuhan anak tanpa disertai peran bimbingan dan asuhan dari sang ayah.
Terkait fenomena fatherless, Indonesia menjadi urutan ketiga di dunia sebagai negara tanpa “ayah”. Hal ini menyedihkan, sebab ketidakhadiran peran serta ayah tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan psikis seorang anak. Hal ini juga yang sering didengungkan Alquran, bahwa peran seorang ayah sangat penting dalam sebuah keluarga. Setidaknya ada tiga amanat Alquran yang penting untuk digarisbawahi seorang ayah agar senantiasa mewujudkan perannya dalam pengasuhan anak, yakni:
Baca juga: Peran Ayah dalam Keluarga Menurut Alquran
Memberikan wasiat Islam
Aspek pertama yang harus dipenuhi oleh seorang ayah terhadap anaknya adalah menuntunnya kepada agama Islam. Hal ini sebagaimana amanat Alquran berikut:
﴿ وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُۗ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۗ ١٣٢ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاۤءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْۗ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَاۤىِٕكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًاۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ١٣٣ ﴾
“[132] Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. “Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. [133] Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab, “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami (hanya) berserah diri kepada-Nya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 132-133).
Ayat tersebut menjelaskan wasiat yang diberikan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub (sebagai Ayah) kepada anak-anaknya. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menekankan bahwa pengaruh seorang ayah dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya memberikan beragam pemahaman dan pengalaman kepada mereka. Ayahlah yang sangat bertanggungjawab dalam mengenalkan dan membimbing seorang anak kepada tuntunan agama Islam—agama yang diterima Allah Swt.
Begitu pula menurut Al-Zuhaili, bahwa sosok Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub adalah prototipe kebijaksanaan seorang ayah yang menghendaki kebaikan terhadap anaknya, sehingga keduanya sama-sama berwasiat, “Ikutilah agama [Islam] ini.”
Wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub dalam ayat di atas juga dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan pertama yang penting diperoleh seorang anak dari ayahnya, yakni pendidikan tauhid. Oleh karena itu, pada dasarnya seorang ayah memiliki kewajiban untuk memahami Islam. Jika pun tidak, seorang ayah berkewajiban menemani dan membimbing anaknya agar belajar keislaman kepada guru-guru yang berkompeten.
Baca juga: Belajar Keteguhan Hati Seorang Ayah dari Kisah Nabi Yakub
Memberikan sentuhan kasih sayang
Aspek kedua yang harus dipenuhi oleh seorang ayah terhadap anaknya adalah sentuhan kasih sayang. Hal ini menurut para mufasir terindikasi pada ayat-ayat yang mengggunakan diksi “yâ bunayya”. Misalnya seperti apa yang dicatat Alquran dari kisah Nabi Nuh, yakni:
﴿ وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِۗ وَنَادٰى نُوْحُ ِۨابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ٤٢ ﴾
“Kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Nuh memanggil anaknya, ketika dia (anak itu) berada di tempat yang jauh terpencil, “Wahai anakku! naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.” (Q.S. Hud [11]: 42).
Menurut Al-Zuhaili, ayat tersebut menjelaskan bagaimana ketika itu terjadi badai besar, kemudian Nabi Nuh memanggil semua umatnya untuk menaiki kapal, termasuk anaknya (Kan`an) yang tidak beriman kepadanya. Meskipun akhirnya Kan`an tidak menghiraukan seruan ayahnya. Namun, dalam frasa ayat tersebut, Nabi Nuh tetap memanggilnya dengan lemah lembut dan mesra melalui frasa “ya bunayya”. Artinya, Nabi Nuh tidak pernah bosan mendidik anaknya sampai ajal menjemputnya. Sekalipun Kan`an durhaka, beliau tidak pernah meninggalkannya.
Selain itu ada juga sosok Syeikh Madyan yang diceritakan Alquran. Allah berfirman:
﴿ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖاِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ٢٦ قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَۚ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَۗ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ٢٧ ﴾
“[26] Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. [27] Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja untukku selama delapan tahun. Jika engkau sempurnakan sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (Q.S. Al-Qashash [28]: 26-27).
Menurut para mufasir, ayah dari dua orang perempuan tersebut adalah Nabi Syuaib. Rupanya salah seorang anak perempuannya kagum kepada Nabi Musa karena beliau kuat, ulet, dan bisa dipercaya. Kemudian ia meminta ayahnya untuk mempekerjakan Nabi Musa. Menurut Sayyid Quthub, barangkali Nabi Syuaib merasakan adanya kecenderungan fitrah yang lurus untuk membangun keluarga antara anaknya dan Nabi Musa. Oleh karena itu, beliau mengajukan kepada Nabi Musa agar menikahi salah seorang anak perempuannya dengan mahar berupa jasa menggembalakan ternak.
Secara struktural, dalam ayat ini tidak ada dialog berupa nasihat dari Nabi Syuaib kepada anaknya. Sebaliknya, ada dialog dari anak perempuan kepada ayahnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa Alquran mengisahkan kedekatan seorang ayah dengan anak perempuannya. Artinya, seorang anak perempuan tidak perlu takut atau segan sehingga bersikap tertutup. Demikian pula seorang ayah hendaknya dapat merasakan keinginan hati anaknya. Hal ini mungkin terjadi jika anak perempuan merasakan kasih sayang seorang ayah dan ia tahu bahwa ayahnya memahami dan peduli atas keinginannya.
Baca juga: Fashabrun Jamil, Kisah Kebijaksanaan Sang Ayah saat Ditipu Anak-anaknya
Bertanggung jawab terhadap anak
Ungkapan bahwa anak tidak meminta untuk dilahirkan dalam satu sisi memang dapat dianggap relevan. Hal ini tentu saja memberikan konsekuensi logis bahwa kehadiran anak adalah tanggung jawab orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga. Terkait hal ini, kita juga dapat belajar dari kisah Nabi Syuaib dalam Q.S. Al-Qashash di atas, yakni bagaimana beliau menyiapkan dengan matang masa depan bagi anak perempuannya. Nabi Syuaib merencanakan masa depan yang baik dengan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang memiliki potensi, baik lahir maupun batin.
Dalam melakukan berbagai perannya di atas, para ayah yang diceritakan Alquran adalah ayah yang lemah lembut dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya berikut sikap tanggung jawab atas pendidikan dan masa depannya. Artinya, kehadiran ayah dalam pengasuhan anak sangat dibutuhkan dan berpengaruh terhadap proses perkembangan anak. Sebab, menurut beberapa penelitian, kehadiran seorang ayah secara konsekuen memberikan stimulasi afeksi sehingga memberikan rasa nyaman dan penuh kehangatan. Wallahu a’lam. []
Baca juga: Parenting Demokratis ala Nabi Ibrahim dalam Q.S. As-Saffat: 102