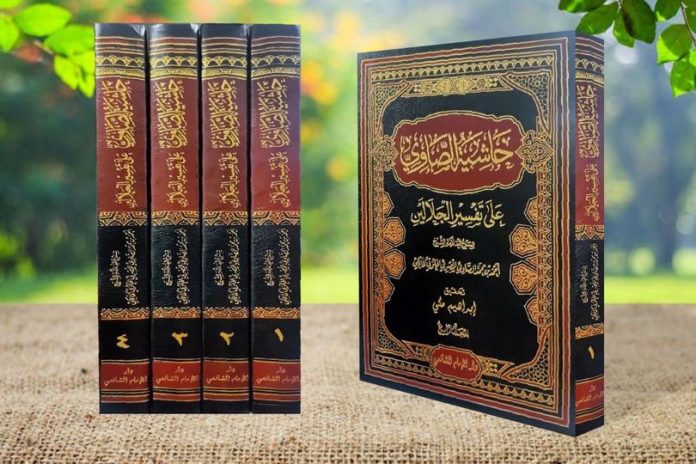Dari Alquran lahir berbagai cabang ilmu seperti ilmu tafsir, nahwu sharaf, balaghah, dan masih banyak lagi. Bahkan uniknya, satu huruf dari Alquran saja memuat makna yang keindahannya tak pernah bisa dijangkau oleh syair terhebat versi manusia. Siapapun tak ada yang dapat membuat sebuah ayat dengan faidah huruf demi huruf yang sempurna, jauh dari kekeliruan. Contohnya saja makna preposisi lam yang akan dibahas pada tulisan ini.
Allah Ta’ala berfirman dalam surah at-Taubah ayat 51:
قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
“Katakanlah: Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.”
Makna preposisi lam
Beberapa ulama mengomentari bahwa ada rahasia di balik penggunaan preposisi lam di surah at-Taubah ayat 51 ini. Menurut mereka, ada alasan kenapa Allah menggunakan kata lanā (لنا) dan bukan ‘alainā (علينا). Ibnu Hajar Rahimahullah berpendapat, Allah menyampaikan ayat ini dengan kata (لنا) dan bukan ( علينا) sebagai peringatan bahwa hendaklah kita memandang setiap apa yang menimpa dan terjadi pada kita sebagai ni’mah (anugerah) dan bukan nikmah (kesengsaraan). [Fathul Bari: 11/626].
Baca Juga: Tafsir Surah Ad-Duha Ayat 11 dan Surah Yusuf Ayat 5
Dalam Tafsir Ibnu Rajab al-Hanbali, Ibnu Jauzi berkata di dalam al-Muqtabas: aku mendengar menteri (Ibnu Hubairah) berkata tentang ayat ini. Allah tidak mengatakan dengan mā kataba ‘alainā (ما كتب علينا) karena menyangkut urusan seorang mukmin. Setiap kali ia ditimpa sesuatu, maka sesungguhnya sesuatu itu adalah tetap baik untuknya. Apabila ditimpa kebaikan, maka itulah kebaikan yang ia peroleh di dunia. Dan apabila ditimpa keburukan, maka kebaikannya adalah nanti berupa pahala di Akhirat.
Untuk lebih memahami perbedaan makna tersebut, mari kita perdalam pada gaya bahasa ath-thibaq dalam surah al-Baqarah ayat 286:
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
Ayat di atas diterjemahkan dengan redaksi: “Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”
Sebagaimana dalam tafsir Jalalain yang menafsirkan لها ما كسبت: berupa kebaikan yakni pahala; sedangakn عليها ماكتسبت: berupa keburukan yakni siksaan.
Maka dapat disimpulkan bahwa ayat ini menggunakan lafadz lanā, sebab preposisi ini dalam bahasa Arab selalu menggambarkan kebaikan, bertolak belakang dengan lafadz ‘alā yang melambangkan hal buruk.
Contoh lain ialah doa untuk pengantin yang Rasulullah ajarkan. Terdapat kata bārakallah laka dan kata bārakallah ‘alaika. Laka di sini adalah mendoakan keberkahan pada hal-hal baik dan manis selama menjalani biduk rumah tangga. Disempurnakan oleh lafadz ‘alaika, sebagai doa agar tetap dalam keberkahan pula selama menjalani masa-masa sulit dan pahit di dalam berumah tangga.
Makna lam dalam ayat
Surah at-Taubah ayat 51 ini diperuntukan untuk orang mukmin sebagai manifestasi lafadz lanā. Karena hanya orang mukmin yang seluruh kehidupannya dikaruniai nikmat. Adapun nikmat yang diberikan kepada orang kafir dalam pandangan Allah adalah hal yang sebaliknya. Mereka mungkin saja diberi nikmat di dunia, tapi mereka tidak akan merasakan nikmat akhirat. Sedangkan orang mukmin, dunia akhiratnya, suka dukanya, lahir batinnya, semuanya bernilai kebaikan.
Baca Juga: Ketika Allah Mengajarkan Nabi Daud tentang Kepemimpinan
Semestinya setiap mukmin berprasangka baik terhadap setiap hal yang menimpa karena semuanya adalah untuk kebaikannya. Apapun yang menimpa hidup seorang mukmin, semuanya adalah ni’mah dan bukan nikmah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam hadis berikut.
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلممَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِى نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ
“Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Ujian selalu bersama dengan orang beriman lelaki dan perempuan, baik di dalam diri, anak dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahanpun.” (H.R. Tirmidzi :2687).
Demikianlah makna huruf dalam Alquran yang selalu memuat rahasia indah, hingga penggunaan preposisi lam saja dapat menjadi bahan telaah para ulama dengan segala rahasia maknanya. Wallah a’lam.