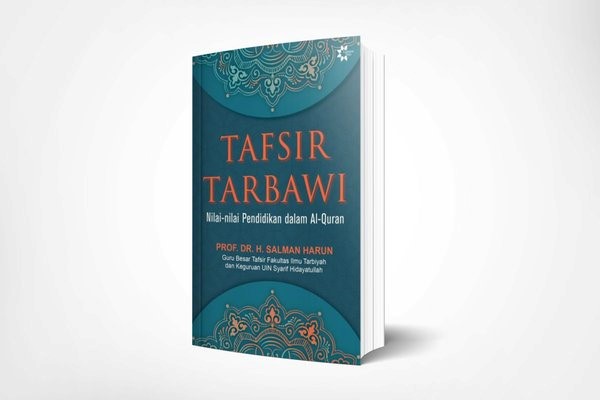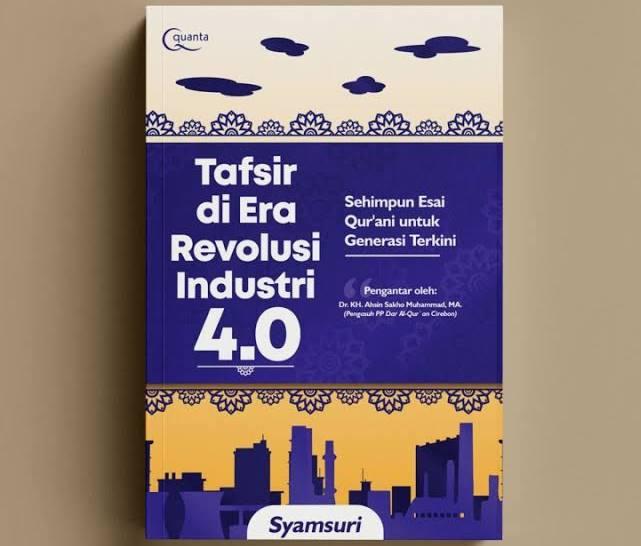Pernikahan merupakan pintu gerbang menuju bangunan kehidupan rumah tangga, ia sakral dan suci bagi pasangan suami istri. Sebagai ikatan yang sakral (mitsaqan ghalidzha), sebuah pernikahan bertujuan membangun hubungan suami istri yang sakinah dengan landasan mawaddah dan rahmah (Q.S. 30: 21). Oleh karena itu, keutuhan rumah tangga sangat ditentukan oleh hubungan suami istri sebagai unsur utama.
Keberhasilan sebuah pernikahan tidak akan tercapai kecuali jika kedua insan tersebut saling memperhatikan kewajiban dan haknya masing-masing. Hal ini berarti bahwa kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian yang diidamkan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh pola interaksi antara keduanya. Dengan kata lain, relasi yang terjalin dalam sebuah pernikahan perlu dibangun secara bijaksana di atas asas kebersamaan, keadilan, dan kesalingan.
Dalam Islam, ikatan pernikahan tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Lebih dari itu, pernikahan adalah fitrah dan ladang ibadah bagi manusia. Ibarat bahtera, rumah tangga yang dijalin terbangun dari berbagai aspek yang saling menyempurnakan untuk tetap berlayar di samudera kehidupan yang luas. Oleh karena itu, Al-Qur`an sebagai pedoman bagi umat Islam banyak memberikan tuntunan bagaimana mahligai pernikahan seharusnya dijalankan.
Silih Asah
Aspek pertama dalam asas kebersamaan yang harus dibangun dalam relasi suami istri adalah silih asah atau saling menajamkan pengetahuan, tukar pendapat, dan saling berbagi pengalaman. Aspek silih asah ini penting mengingat rumah tangga dalam pandangan Islam tidak sebatas jalinan asmara saja, namun juga berperan dalam pembangunan peradaban manusia.
Baca Juga: Marak e-commerce, Antara Kemudahan dan Keborosan: Refleksi Surah Al-Furqan Ayat 67
Peradaban dalam konteks ini tentu saja menyangkut setidaknya dua hal, yakni peradaban intelektual dan peradaban spiritual. Sepasang suami istri memiliki tanggung jawab yang sama untuk saling berbagi pengetahuannya, khususnya perihal pemahaman keislaman. Sebab tanpa pengetahuan, agama dan ritual ibadah di dalamnya hanya akan tertolak (mardudatun) dan sia-sia belaka. Oleh karena itu, sepasang suami istri memiliki tanggung jawab untuk sama-sama menjaga dan membimbing rumah tangganya agar berhasil. Allah berfirman:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا….. ٦
“Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu beserta keluargamu supaya terhindar dari api neraka,….” (Q.S. Al-Tahrim [66]: 6)
Ayat tersebut menunjukan kewajiban dalam membangun rumah tangga (keluarga) takwa, karena lafadz “qu” di sana menurut Tafsir Al-Jalalain merupakan fi’l al-‘amr yang mengindikasikan perintah wajib. Upaya pembangunan keluarga takwa tersebut menurut Al-Tabari dan Ibnu Katsir adalah dengan saling mengingatkan dalam ketaatan dan mewujudkan pendidikan yang baik dan terarah.
Begitu juga menurut Al-Zuhaili, pada urgensi frase ayat ini sangat nampak pentingnya penanaman pendidikan dalam sebuah keluarga. Pendidikan tersebut bersifat mutualisme, artinya keseluruhan anggota keluarga memiliki tanggung jawab kemitraan untuk mewujudkan keluarga yang terdidik. Hal ini sebagaimana diungkapkan Quraish Shihab bahwa perintah dalam redaksi “qu” tersebut tidak hanya ditujukan untuk laki-laki (suami), namun juga kepada perempuan (istri). Syahdan, keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk saling berbagi pengetahuan, pun mendidik anak-anaknya.
Silih Asih
Aspek kedua dalam asas kebersamaan yang harus dibangun adalah “silih asih” yang berarti saling memberi kasih, menebar cinta, dan berbagi sayang. Aspek ini menjadi penting mengingat bahwa cinta seringkali menjadi alasan utama sebuah pernikahan, bahkan ia menjadi tujuan dari pernikahan itu sendiri (QS. 30: 21). Karena cinta tidak sesederhana sebab kecantikan dan ketampanan, wangi tubuh, dan senyuman, lebih dari itu cinta menjelma sebagai dzat esoterik yang mendalam. Maka kedalaman tersebut senantiasa harus dijaga dalam hubungan suami istri.
Cinta atau kasih sayang dalam rumah tangga juga berarti interaksi dan pergaulan yang “baik” antara keduanya. Saling bersikap santun, bertutur kata lembut, dan memanjakan dengan halus. Oleh karena itu, cinta tidak mungkin dimaknai kebalikan dari semua hal itu, maka relasi rumah tangga yang cenderung mengarah pada “toxic relationship” tidak pantas dilabeli cinta. Berkenaan dengan hal ini, Allah berfirman:
وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)
Ayat tersebut secara eksplisit menjelaskan mengenai konsepsi sebuah pernikahan. Menurut Ibnu Katsir, pernikahan bertujuan untuk membangun ketentraman hidup bagi seorang suami karena hadirnya seorang istri, begitupun sebaliknya. Sehingga keduanya dapat membangun rumah tangga yang serasi, saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti, dan saling membangun kesejahteraan bersama.
Hal senada juga diungkapkan Al-Zuhaili, menurutnya ayat tersebut bermakna bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia dari jenisnya sendiri (manusia) dengan tujuan untuk menciptakan keserasian dan menjauhkan dari perasaang asing atau tidak dekat. Dengan kata lain, perasaan serasi dan dekat tersebut lah yang kemudian akan menumbuhkan kenyamanan (sakinah) dengan muara rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sehingga dengan perasaan tersebut akan terbangun keluarga yang indah.
Silih Asuh
Aspek ketiga dalam asas kebersamaan yang harus dibangun adalah “silih asuh” yang berarti saling berbagi bantuan, memberi perhatian dan pengertian, juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Aspek ini dianggap penting mengingat rumah tangga merupakan bahtera yang mengarungi samudera kehidupan dengan berbagai cobaan dan rintangan. Artinya, sepasang suami istri seyogianya saling melengkapi dan menuntun rumah tangga tersebut menuju kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram.
Sikap silih asuh tersebut tercipta juga manakala interaksi dan pergaulan antara sepasang suami istri terjalin secara harmonis dan integratif. Hal ini sebagai firman Allah yang menyatakan, “bergaullah kalian dengan istri-istirmu dengan baik (ma’ruf)” (QS. 4: 19). Tentu saja pergaulan tersebut sifatnya sangat fleksibel dan kompleks, artinya tidak hanya sebatas pada ranah hubungan intim saja, namun juga dalam relasi interaksi antara keduanya yang harus dilandasi perasaan saling melengkapi. Dalam ayat lain Allah berfirman:
اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاۤىِٕكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ…. ١٨٧
“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 187)
Baca Juga: Tiga Fungsi Pohon dan Eksistensinya Menurut Al-Qur’an
Ayat tersebut menurut Al-Zuhaili memang secara umum menjelaskan mengenai kebolehan berhubungan intim pada “laylatu al-siyam”. Namun frasa “hunna libasun lakum, wa antum libasun lahun” menurut Quraish Shihab secara implisit menggambarkan bagaimana Al-Qur`an membimbing sepasang suami istri untuk senantiasa saling menjaga dan melengkapi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Imam Al-Jalalain bahwa ayat tersebut menggambarkan konsep relasi suami istri yang setidaknya terjalin atas tiga hal, yakni 1) kedekatan secara psikis dan psikologis; 2) saling mengayomi; dan 3) perasaan saling membutuhkan.
Ibarat pakaian—sebagaimana redaksi Al-Qur`an—sepasang suami istri harus mampu melindungi satu sama lain, dan saling menjaga dan menuntun dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, pesan Al-Qur`an dalam ayat tersebut sangat dekat dengan makna “silih asuh” yang memang berarti demikian.
Syahdan, konsep “silih asah asih asuh” ini harus dimaknai secara mendalam bagi setiap insan yang mengharapkan relasi cinta dalam rumah tangga yang baik dan berhasil. Tiga aspek tersebut menjadi dasar dan fondasi serta menara rumah tangga yang dapat memancarkan kesejahteraan bagi setiap pasangan, bahkan bagi tetangga, hingga banyak masyarakat di sekitarnya. Wallahu a’lam.