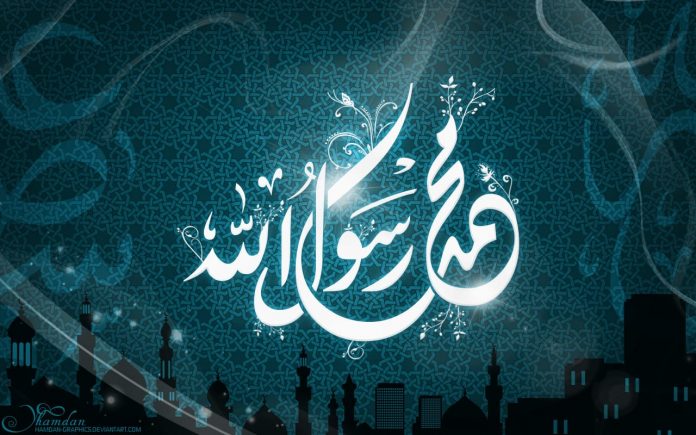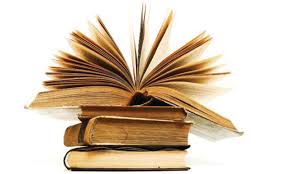Bagaimana hukum makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas atau perak murni? Mungkin ini adalah salah satu pertanyaan yang terbersit di benak pembaca, tatkala mempelajari kebiasaan raja-raja terdahulu atau membayangkan memiliki kekayaan sehingga bisa makan dari piring emas. Menggunakan wadah dari emas dan perak adalah salah satu tema yang disinggung dalam kitab tafsir. Hal ini berkaitan dengan nikmat kelak di surga yang dapat minum dari gelas emas. Lebih lengkapnya, simak penjelasan para pakar tafsir dan fikih berikut ini:
Baca Juga: Hidangan Manna dan Salwa dalam Al-Qur’an Beserta Manfaatnya
Emas dan Perak Adalah Nikmat Di Akhirat
Hukum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak murni disinggung oleh para ahli tafsir salah satunya tatkala menguraikan firman Allah yang berbunyi:
اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًاۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ٢٣
Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalamnya mereka diberi perhiasan berupa gelang emas dan mutiara. Pakaian mereka di dalamnya adalah sutra (QS. Al-Hajj [22] :23).
Imam Ibn Katsir memberi penjelasan tatkala mengomentari ayat di atas, dikarenakan hal-hal seperti sutra dan emas merupakan nikmat yang diberikan tatkala di akhirat, maka diharamkan di dunia dan kemudian diperbolehkan di akhirat. Ibn Katsir kemudian mengutip sebuah hadis yang dijadikan dasar ulama’ fikih mengharamkan pemakaian wadah emas atau perak. Sahabat Khudzaifah meriwayatkan (Tafsir Ibn Katsir/6/551):
لاَ تَشْرَبُوا فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِى صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الآخِرَةِ
Janganlah kalian minum dari wadah emas dan perak, juga jangan makan dari piring yang terbuat dari keduanya. Sesungguhnya kesemuanya milik mereka di dunia dan milik kita di akhirat (HR. Imam Bukhari).
Senada dengan Ibn Katsir, Imam Al-Qurthubi mencantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah dan berbunyi (Tafsir Al-Qurthubi/12/29):
ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الآخرة
Barangsiapa minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka ia tidak akan minum dari wadah seperti itu di akhirat (HR. An-Nasa’i).
Hadis yang disebutkan Imam Al-Qurthubi di atas juga disebutkan oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir-nya. Syaikh Wahbah menyatakan, memanfaatkan wadah dari emas dan perak untuk tujuan seperti makan dan minum, diharamkan secara mutlak bagi laki-laki dan perempuan (Tafsir Munir/17/187).
Imam An-Nawawi; salah seorang pakar perbandingan mazhab menyatakan, menurut pendapat yang sahih, masyhur dan diyakini mayoritas ulama’, hukumnya haram menggunakan wadah dari emas dan perak untuk tujuan makan, minum dan selainnya. Imam An-Nawawi juga membantah riwayat bahwa Imam Asy-Syafi’i dalam qaul qadimnya menyatakan hukum menggunkan emas dan perak hanya sekedar makruh (Al-Majmu’/1/248).
Kitab Mausu’atul Ijma’ mendokumentasikan, memang benar ada pernyataan bahwa ulama’ telah sepakat mengharamkan pemakaian kedua wadah tersebut untuk makan dan minum. Diantaranya dinyatakan oleh Ibn Mundzir dan Ibn Abdil Bar. Namun itu hanya klaim belaka. Kenyataannya sebenarnya ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Perbedaan itu diriwayatkan dari Mu’awiyah ibn Qurrah yang membolehkan minum dari wadah perak, dari Mazhab Dawud yang menyatakan keharaman hanya terbatas pada minum saja, dan dari qaul qadim Imam Syafi’i yang menyatakan sekedar hukum makruh saja, tidak sampai haram (Mausu’atul Ijma’/1/137).
Dari berbagai uraian di atas kita dapat mengambil kesimpulan, mayoritas ulama’ menyatakan haramnya makan dan minum dari wadah emas dan perak. Perlulah diingat, hukum ini terbatas pada pemakaian wadah yang murni terbuat dari emas atau perak. Sebab untuk sekedar menyimpan wadah dan bukan memakai, serta untuk wadah yang sekedar dihiasi emas serta tidak murni terbuat darinya, para ulama’ memiliki pembahasan hukum yang tersendiri. Wallahu a’lam bish showab.