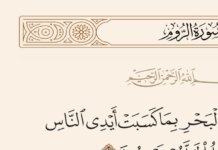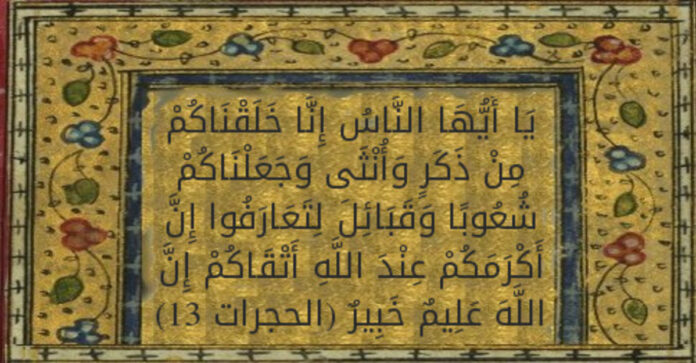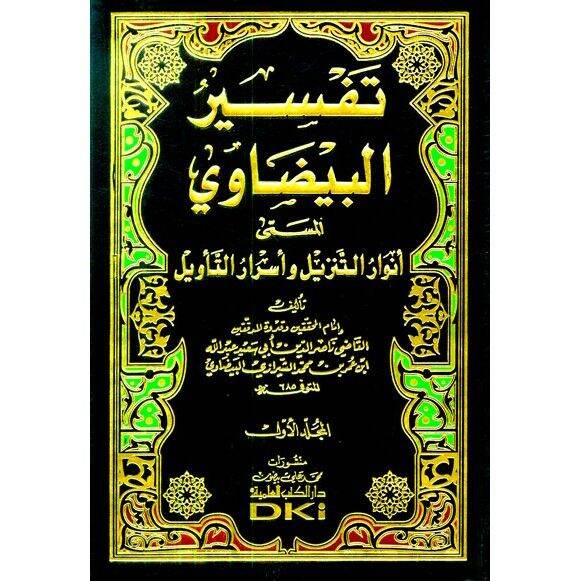Air adalah sumber kehidupan, anugerah ilahi yang menopang seluruh makhluk hidup di bumi. Dalam Alquran, air disebutkan lebih dari 60 kali, menggambarkan peran vitalnya dalam kehidupan manusia, ekosistem, dan spiritualitas. Bahkan semua lini kehidupan berawal dan butuh dengan air. Semua bangunan, butuh dan berbahan dasar air, tumbuhan butuh air, bahkan kita sendiri berasal dari air.
Namun, di tengah krisis lingkungan yang semakin akut, khususnya di Indonesia, bagaimana kita membaca pesan Alquran mengenai air? Apakah nilai-nilai ekologis dalam wahyu ini mampu menjadi solusi untuk tantangan besar seperti kekeringan, banjir, dan pencemaran air?
Baca Juga: Air: Anugerah Ilahi dan Etika Manusia Terhadapnya
Air dalam Perspektif Alquran
Alquran menegaskan bahwa air adalah inti dari kehidupan. Firman Allah:
………وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۤءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّۗ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ٣٠ ( الانبياۤء/21: 30)
… dan Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman? (Al-Anbiya’/21:30)
Ayat ini menegaskan bahwa air adalah fondasi kehidupan, esensi yang memungkinkan tumbuhan, hewan, dan manusia untuk ada. Dalam ayat lain, air digambarkan sebagai tanda kekuasaan Allah yang menghidupkan bumi melalui hujan:
“Dialah yang menurunkan hujan dari langit untukmu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan…” (Surah An-Nahl [16]: 10).
Namun, Alquran tidak hanya membahas air dari aspek material, tetapi juga spiritual. Air digunakan dalam wudu sebagai simbol penyucian, menunjukkan bagaimana elemen ini mempererat hubungan manusia dengan Allah. Tafsir klasik seperti Al-Qurthubi mengingatkan bahwa penyebutan air dalam Alquran juga menuntut tanggung jawab untuk menjaga sumber daya tersebut.
Dalam menafsirkan ayat ini, tafsir-tafsir klasik sperti Tafsir Al-Qurthubi, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Mafatih al-Ghaib serta tafsir kontemporer seperti Tafsir Al-Munir karya Syeikh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa air dalam berbagai konteks dalam Alquran bukan hanya sesuatu yang ditunjukkan sebagai karunia Allah, tetapi juga sebagai tanggung jawab manusia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam terbesar ini.
Baca Juga: Q.S Almu’minun Ayat 18: Konsep Bumi Sebagai Reservoir Air
Krisis Air di Indonesia: Paradoks Negeri Air
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan curah hujan rata-rata mencapai 2.700 mm per tahun, dikenal sebagai salah satu negara dengan sumber daya air melimpah. Namun, potret realitas justru menunjukkan paradoks. Banyak wilayah mengalami krisis air bersih akibat distribusi yang tidak merata, pengelolaan yang buruk, serta pencemaran.
Kekeringan dan kelangkaan air bersih di Indonesia, sekitar 33 juta penduduk masih kekurangan akses air bersih (BPS, 2022). Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah contohnya, di mana musim kemarau panjang kerap menyebabkan kekeringan ekstrem. Fenomena ini diperburuk oleh degradasi hutan yang mengurangi kapasitas daerah tangkapan air.
Banjir dan Intrusi Air Laut. Di sisi lain, banjir menjadi masalah berulang di kota-kota besar seperti Jakarta dan Semarang. Tingginya tingkat urbanisasi, pengelolaan drainase yang buruk, serta kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim memperburuk situasi. Intrusi air laut juga menjadi ancaman di pesisir, mengubah air tanah menjadi asin dan tidak layak dikonsumsi.
Pencemaran Air Sungai Citarum, salah satu sungai terpanjang di Jawa Barat, menjadi simbol pencemaran air di Indonesia. Sebuah studi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa lebih dari 50% sungai di Indonesia tercemar berat akibat limbah domestik, industri, dan pertanian. Sungai-sungai di Pulau Jawa memikul beban pencemaran tertinggi, mengancam ketersediaan air bersih bagi penduduk di wilayah padat penduduk.
Baca Juga: Maurice Bucaille dan Tafsir Ilmi tentang Siklus Air
Mengintegrasikan Pesan Alquran untuk Mengatasi Krisis Air
Dalam Islam, perusakan lingkungan, termasuk eksploitasi air secara berlebihan, dianggap sebagai tindakan melampaui batas (israf), dan hal itu jelas dilarang. dalam surah al-A’raf ayat 56 disampaikan tentang larangan untuk berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.
Pesan ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Berikut adalah langkah-langkah konkret berdasarkan nilai-nilai Alquran yang relevan dengan kondisi Indonesia:
Pertama, Efisiensi dan Pengelolaan Air. Nabi Muhammad SAW mencontohkan penggunaan air secara hemat. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda: “Janganlah kamu boros dalam menggunakan air, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir.” (HR. Ahmad).
Di Indonesia, pola hidup hemat air dapat diterapkan dalam sektor rumah tangga dan pertanian. Penerapan irigasi tetes, misalnya, dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air di lahan pertanian yang kerap boros.
Kedua, Restorasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai-sungai yang tercemar, seperti Citarum, membutuhkan langkah konkret berupa rehabilitasi ekosistem. Reboisasi hutan di hulu sungai, pengelolaan limbah industri yang ketat, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pencemaran dapat mengembalikan fungsi DAS sebagai penyuplai air bersih.
Ketiga, Pendidikan dan Kesadaran Publik. Pendidikan berbasis ekologi Islam, dengan pendekatan nilai Al-Qur’an, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga air. Sebagai contoh, madrasah dapat mengintegrasikan pelajaran tentang konservasi air dalam kurikulum pendidikan agama.
Keempat, Inovasi Teknologi Hijau. Penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti instalasi pengolahan air limbah di masjid dan sekolah, dapat mengurangi dampak pencemaran. Inisiatif seperti masjid ramah lingkungan di Jakarta, yang memanfaatkan teknologi penampungan air hujan untuk keperluan wudhu, bisa menjadi model yang ditiru di tempat lain.
Menyinergikan Ilmu Pengetahuan dan Spiritualitas
Pendekatan ilmiah saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan besar ini. Kesadaran spiritual diperlukan untuk mendorong perubahan perilaku. Dalam Islam, air tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan fisik, tetapi juga amanah dari Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin mengingatkan bahwa semua nikmat yang kita gunakan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa konservasi air mampu meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Di Indonesia, pelibatan masyarakat berbasis spiritualitas dapat memperkuat program pemerintah seperti Gerakan Citarum Harum, yang bertujuan membersihkan sungai dari pencemaran.
Harapan untuk Masa Depan Air di Indonesia
Mengatasi krisis air di Indonesia membutuhkan kerja sama lintas sektor, melibatkan pemerintah, komunitas agama, dan masyarakat luas. Dengan mayoritas Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan nilai-nilai Al-Qur’an sebagai landasan etis dalam pengelolaan air.
Dengan pendekatan berbasis wahyu, ilmu pengetahuan, dan aksi nyata, kita dapat mengubah krisis air menjadi peluang untuk membangun negeri yang lebih berkelanjutan. Air adalah tanda cinta Allah kepada makhluk-Nya. Menjaganya adalah wujud nyata rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Wallah a’lam


![Jahiliyah Modern: Membaca Ulang Al-Mā’idah [5]:50 sebagai Kritik Hedonisme, Materialisme dan Kemerosotan Moral](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2025/12/2807131-218x150.jpg)