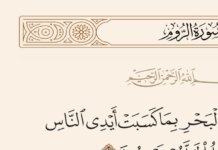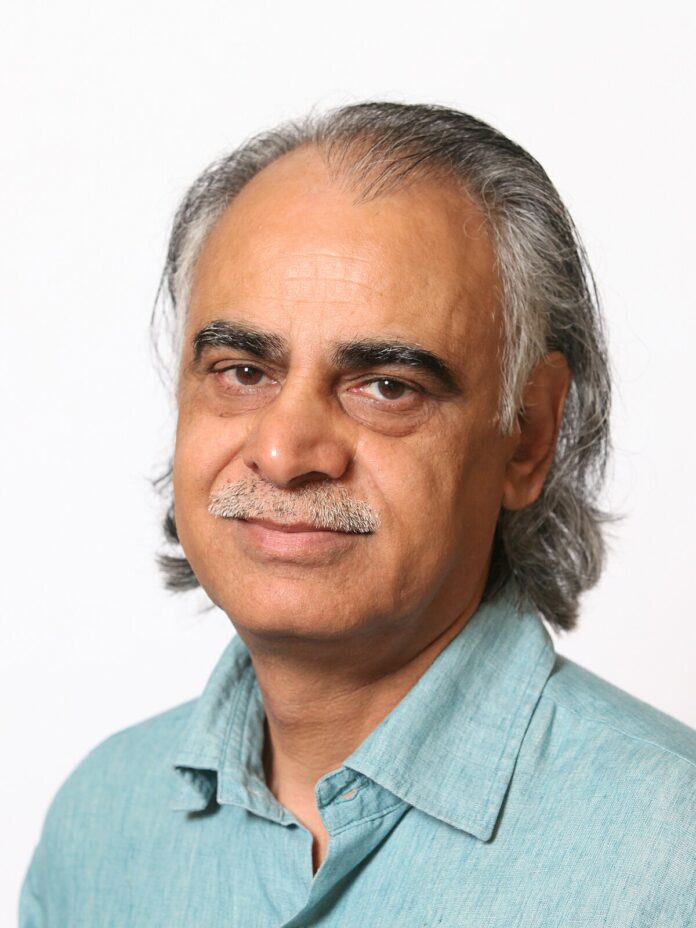Rasm Alquran adalah penulisan lafaz-lafaz Alquran. Sebagai sebuah cabang kajian ilmu Alquran, fokus bidang ini adalah tentang penulisan Alquran mulai dari masa Rasulullah saw. hingga berbentuk mushaf utuh seperti sekarang. Bidang ilmu ini merupakan salah satu upaya penjagaan Alquran dari kesalahan dan perubahan lafaz Alquran. Dalam Sejarah penjagaan Alquran, rasm merupakan upaya penjagaan Alquran dalam bentuk tulisan.
Upaya penjagaan Alquran melalui tulisan terbagi menjadi tiga masa, yakni masa Rasulullah SAW, masa khalifah Abu Bakar, dan masa khalifah Utsman bin Affan. Dari ketiga masa ini, kemudian timbul pertanyaan, apakah rasm Alquran sebagaimana terlihat pada mushaf Alquran yang kita ketahui sekarang dan beredar di seluruh dunia ini tauqifi atau ijtihadi?
Tauqifi dimaksudkan sebagai istilah untuk menamai bahwa penulisan lafaz Alquran itu berasal dari ketetapan Rasulullah yang berdasarkan wahyu dari Allah, sedangkan ijtihadi adalah bersifat hasil dari ijtihad para sahabat.
Dalam Kitab Al-Mukhtashar Al-Lathif Fii ‘Ilm Rasm Al-Mushaf Al-Syarif (hal 29-34) karya Ahmad Samir Ahmad Abdul Ghaniy, tepatnya pada pembahasan mengenai persoalan penting yang terkait dengan rasm, dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai sifat rasm Alquran, tauqifi atau ijtihadi.
Baca Juga: Mengenal Rasm Alquran sebagai Bentuk Resepsi Alquran dan Hadis
Ulama muta’akhirin (setelah abad ketiga hijriyah) mengatakan bahwa mayoritas ulama memahami bahwa rasm Alquran sebagai sesuatu yang bersifat tauqifi dan tidak diperbolehkan menyelisihinya. Oleh karena itu, muncul konsensus berikutnya yaitu dengan mengikuti rasm Alquran ini, baik dalam tulisan maupun bacaan dianggap sebagai kewajiban.
Hal tersebut senada dengan keterangan Az-Zarqani dalam Manahil al-Irfan (hal. 310) bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa rasm Alquran itu tauqifi dan tidak diperbolehkan menyelisihinya, sehingga konsekuensi yang ditimbulkan adalah rasm mushaf usmani yang sampai pada kita sekarang juga bersifat tauqifi karena merupakan ketetapan Rasulullah saw.
Namun, berdasarkan kesepakatan para ulama pula, kewajiban ittiba’ (pengikutan) terhadap rasm tidak berarti menyatakan rasm bersifat tauqifi. Hal ini karena persoalan tauqifi dan ittiba’ merupakan dua persoalan yang berbeda.
Sedangkan ulama mutaqaddimin (masa awal hingga abad ketiga hijriyah) tidak mengatakan rasm itu bersifat tauqifi. Mereka hanya mengatakan bahwa ittiba’ terhadap rasm adalah sebuah kewajiban dan tidak boleh menyelisihinya baik dalam tulisan maupun bacaan. Ulama masa ini lebih mengunggulkan pendapat yang mengatakan bahwa rasm Alquran adalah ijtihadi.
Komentar Syaikh Samir terhadap dua pendapat para pendahulunya, terutama untuk ulama yang memahami bahwa rasm Alquran adalah tauqifi bisa jadi karena bertujuan untuk menakut-nakuti orang-orang yang menganggap mudah persoalan rasm, agar tidak terjadi penggantian rasm usmani yang ditulis dan disepakati oleh para sahabat dengan rasm qiyasi yang memiliki kaidah kesesuaian tulisan dengan lafaznya.
Pendapat yang mengompromikan kedua pendapat di atas, menyatakan bahwa rasm Alquran adalah tauqifi pada masa Rasulullah saw. dan khalifah Abu Bakar. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi ijtihad dalam penyalinan mushaf.
Baca Juga: Membedah Takrif Rasm Mushaf Alquran Standar Indonesia
Rasm Alquran pada masa Rasulullah Saw
Alquran pada masa ini ditulis di bawah arahan dan pantauan Rasulullah. Sebagaimana riwayat yang disebutkan dari Zaid bin Tsabit:
كُنْتُ أَكْتُبُ الْوَحْي عِنْدَ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُمْلِي عَلَيَّ فَإذَا فَرَغْتُ قَالَ صلى الله عليه وسلم اقْرَأْ فَأَقْرَؤُهُ فَإِذا كَانَ فِيْهِ سَقْطٌ أَقَامَهُ ثُمَّ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى النَّاسِ
Rasulullah mendiktekan suatu ayat kepada Zaid bin Tsabit untuk ditulis. Ketika selesai, Rasul meminta Zaid membaca ulang tulisan tersebut dan Zaid melakukannya. Apabila ada yang terlewat, Rasul membenarkannya. Kemudian Zaid keluar menuju orang-orang untuk menyampaikan ayat tersebut. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan sahabat penulis wahyu untuk meletakkan ayat ini dalam surat ini dan seterusnya hingga seluruh ayat Alquran berhasil ditulis meskipun tidak terkumpul dalam satu mushaf.
Rasm Alquran pada masa Khalifah Abu Bakar
Pada masa ini, terjadi peperangan melawan kelompok yang mengaku-ngaku sebagai nabi yang disebut dengan Perang Yamamah dan berakibat gugurnya para sahabat penghafal Alquran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada Umar bin Khattab akan habisnya qurra’. Atas dasar inilah, Khalifah Abu Bakar menyetujui adanya penjagaan Alquran melalui tulisan.
Abu Bakar memerintahkan tugas ini kepada para sahabat yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan dan menyalin serta mengurutkan tulisan Alquran yang telah ada pada zaman Rasulullah saw. ke dalam suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran.
Ketentuan yang berlaku pada masa ini adalah tulisan yang telah ditetapkan oleh sahabat penghafal Alquran dan disaksikan oleh dua orang saksi serta tulisan tersebut adalah yang pernah ditulis dihadapan Rasulullah saw. Inilah yang menjadikan alasan rasm Alquran pada masa khalifah Abu Bakar masih bersifat tauqifi.
Baca Juga: Rasm Alquran dalam Penulisan Rajah
Rasm Alquran pada masa Khalifah Usman bin Affan
Pada masa ini, terjadi perselisihan di internal umat Islam mengenai bacaan Alquran yang disebabkan beragamnya qiraat yang muncul dari berbagai kalangan dan menimbulkan kebingungan umat Islam akan qiraat mana yang sahih dan mana yang tidak sahih.
Berdasar situasi tersebut, khalifah Usman bin Affan memerintahkan sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Tsabit untuk menyalin tulisan Alquran yang sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar dengan menggunakan satu rasm. Apabila ditemukan beberapa macam qiraat pada suatu lafaz yang tidak memungkinkan ditulis dalam satu rasm, maka para sahabat berijtihad untuk memilih rasm mana yang paling sesuai.
Penyalinan rasm Alquran pada masa ini tetap berpedoman pada aturan rasm Alquran sebelumnya. Adapun hal yang membedakan adalah pesan Usman bin Affan kepada para penyalin bahwa jika terdapat perbedaan antara bacaan mereka (para penyalin) dengan bacaan Zaid bin Tsabit (selaku penulis wahyu senior) dalam proses penyalinan Alquran ini, maka tulis atau salinlah dengan berdasar pada lisan (dialek bacaan) Arab, karena sesungguhnya Alquran itu diturunkan berdasarkan lisan mereka.
Rasm Alquran pada masa Usman tersebut dikenal dengan rasm usmani dan seakan menjadi rasm Alquran yang baku, jadi pedoman penulisan Alquran setelahnya.
Selain rasm usmani, penulisan Alquran juga menggunakan rasm qiyasi. Pada rasm qiyasi, kaidah penulisan Alquran lebih variatif, membuka peluang terjadinya perubahan dan penggantian (cara penulisannya). Oleh karena itu, setelah masa khalifah Usman bin Affan tidak diperbolehkan berijtihad terhadap rasm Alquran dan tidak diperbolehkan menulis Alquran dengan rasm selain rasm usmani. Hal ini juga berimplikasi terhadap syarat qiraat yang diterima, dimana salah satunya adalah sesuai dengan rasm mushaf usmani. Wallahu a’lam


![Jahiliyah Modern: Membaca Ulang Al-Mā’idah [5]:50 sebagai Kritik Hedonisme, Materialisme dan Kemerosotan Moral](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2025/12/2807131-218x150.jpg)