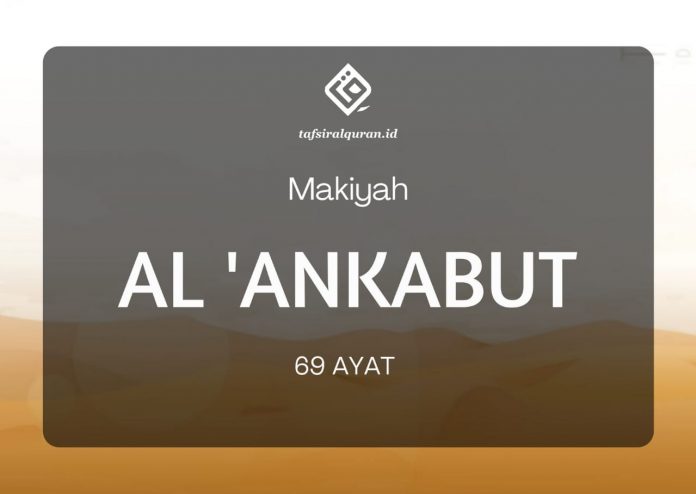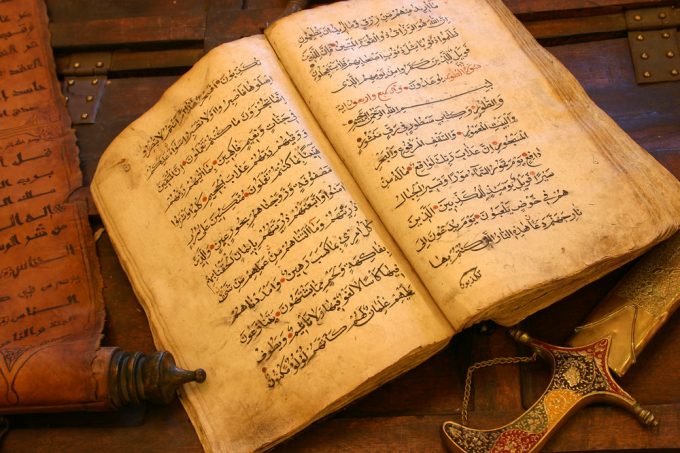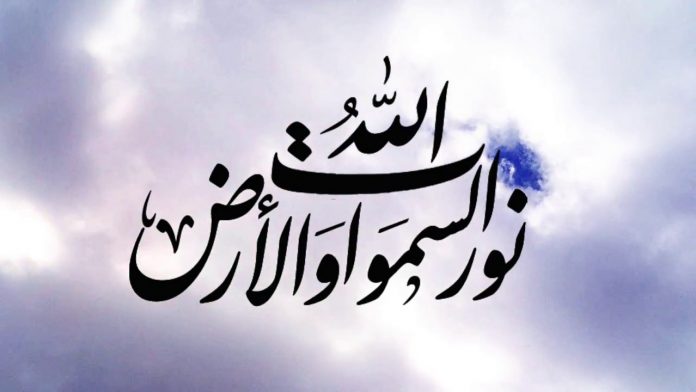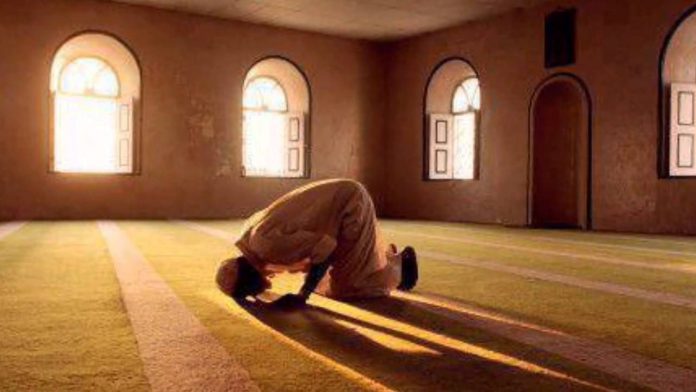Tafsir Surah Al-‘Ankabut ayat 12-15 diturunkan untuk peringatan kepada orang kafir Quraisy yang senantiasa membujuk kaumnya yang beriman agar kembali ke jalan nenek moyangnya. Selain itu Tafsir Surah Al-‘Ankabut ayat 12-15 ini menjadi pembuka kisah Nabi yang diawali dari Nabi Nuh.
Baca Sebelumnya: Tafsir Surah Al-‘Ankabut ayat 9-11
Ayat 12
Tafsir Surah Al-‘Ankabut ayat 12-15 khususnya pada ayat 12 ini Menurut Mujahid, ayat ini diturunkan untuk mengungkapkan usaha-usaha orang Quraisy membujuk kaumnya yang telah beriman dengan mengatakan, “Kami dan kamu tidak akan dibangkitkan kembali. Oleh karena itu, ikutilah langkah-langkah kami. Andaikata kamu berdosa lantaran pekerjaan ini, kamilah yang memikul dosa itu.”
Berkaitan dengan hal ini, Allah memperingatkan orang-orang beriman bahwa orang-orang kafir itu berdusta. Sebab pada hari Kiamat, tidak ada seorang pun diperkenankan memikul dosa orang lain. Allah menegaskan:
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗوَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۗ
Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. (Fathir/35: 18)
Dan firman Allah:
يُبَصَّرُوْنَهُمْۗ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِىِٕذٍۢ بِبَنِيْهِۙ
Sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab dengan anak-anaknya. (al-Ma‘arij/70: 11)
Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan kembali bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bohong. Imam az-Zamakhsyari menafsirkan bahwa di antara mereka yang mengajak rekan-rekannya berbuat dosa itu terdapat juga orang-orang yang mengaku beragama Islam. Mereka menjanjikan untuk menanggung siksaannya sehingga orang-orang bodoh dan lemah imannya tergoda dengan bujukan dan rayuan halus itu.
Ayat 13
Terhadap ajakan dan bujukan orang-orang kafir itu, Allah menegaskan bahwa tidak ada gunanya bagi diri mereka rayuan-rayuan tersebut. Bujukan tersebut disampaikan dalam usaha mengajak orang lain kepada kekafiran dan kesesatan yang harus mereka tanggung dosanya dan orang yang melakukan karena bujukannya.
Namun orang yang melakukannya sendiri tidak akan berkurang dosanya sekalipun yang mengajaknya lebih dahulu dilipatgandakan siksaannya. Pada ayat ini ditegaskan kembali:
لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙوَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اَلَا سَاۤءَ مَا يَزِرُوْنَ ࣖ ;
(Ucapan mereka) menyebabkan mereka pada hari Kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, alangkah buruknya (dosa) yang mereka pikul itu. (an-Nahl/16: 25)
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:
مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنِ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا (رواه مسلم عن ابى هريرة)
Siapa yang mengajak seseorang kepada petunjuk (Tuhan), ia akan memperoleh pahala sebanyak yang diperoleh oleh orang yang mengamalkan petunjuk itu tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya (sampai Kiamat), dan siapa yang mendorong seseorang kepada kesesatan, baginya dosa sebanyak dosa orang yang mengikuti kesesatan itu (sampai hari Kiamat) tanpa dikurangi sedikit pun dosanya. (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah).
Pada akhir ayat ini, Allah menegaskan bahwa di hari kemudian kelak mereka akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kebohongan yang mereka perbuat di dunia. Kepadanya ditanyakan pertanyaan-pertanyaan dengan nada menghina tentang orang-orang yang telah mereka tipu dengan kebohongannya, sehingga mereka menjadi tersesat.
Baca Juga: Kisah Nabi Nuh As dan Keingkaran Kaumnya Dalam Al-Quran
Ayat 14
Kisah para nabi itu dimulai dengan menceritakan riwayat perjuangan Nabi Nuh. Beliau adalah bapak para nabi. Ia berdakwah menyeru kaumnya supaya beriman kepada Allah Yang Maha Esa dan mempercayai kerasulannya selama sembilan ratus lima puluh tahun. Namun demikian, ia tidak pernah merasa bosan mengajak mereka, baik siang maupun malam.
Kadang-kadang dengan suara yang lemah lembut, tetapi sering juga dengan suara keras menyampaikan ancaman Allah terhadap kekafiran mereka. Akan tetapi usaha beliau tidak kunjung berhasil. Hanya segelintir saja di antara mereka yang mau beriman. Selebihnya menolak dan mendustakan beliau.
Oleh karena itu, Allah menyiksa mereka. Dikirimlah siksaan yang disebut “Topan Nabi Nuh”, yakni berupa banjir yang menenggelamkan mereka semua. Tidak seorang pun yang selamat dari siksaan Allah itu kecuali orang yang beriman yang ikut dalam bahtera Nuh.
Al-Hakim meriwayatkan:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ اللهُ نُوْحًا َوهُوَ ابْنُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَبِثَ فِى قَوْمِهِ اَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا يَدْعُوهُمْ اِلَى اللهِ وَعَاشَ بَعْدَ الطَّوْفَانِ سِتِّيْنَ سَنَةً حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ وَفَشَوْا (رواه الحاكم)
Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas bahwa ia berkata, “Allah mengutus Nabi Nuh ketika usia 40 tahun dan berdakwah pada kaumnya selama 950 tahun menyeru mereka untuk mengikuti agama Allah dan Nabi Nuh hidup setelah banjir (topan) selama 60 tahun, sehingga jumlah manusia menjadi banyak dan tersebar. (Riwayat al-Hakim);
Ayat 15
Allah menyelamatkan Nuh dan para pengikutnya dengan sebuah perahu yang telah dibuatnya. Adanya bahtera Nabi Nuh menjadi contoh dan pengajaran bagi orang sesudahnya, karena ia terdampar masih dalam keadaan utuh di sebuah bukit yang bernama Bukit Judi.
Perahu Nabi Nuh sampai beberapa lama masih dapat disaksikan oleh orang yang berkunjung ke sana dalam keadaan utuh. Hal ini menyadarkan orang kepada nikmat Allah yang diturunkan-Nya kepada orang beriman dengan menyelamatkan mereka dari bahaya banjir. Hal demikian dinyatakan dalam ayat lain yang berbunyi:
اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاۤءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِۙ ١١ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ١٢
Sesungguhnya ketika air naik (sampai ke gunung), Kami membawa (nenek moyang) kamu ke dalam kapal. Agar Kami jadikan (peristiwa itu) sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. (al-Haqqah/69: 11-12)
Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah di atas ialah bahwa para rasul sesudah Nuh tidak perlu merasa sedih karena keingkaran kaumnya menerima kebenaran wahyu yang dibawanya. Siksaan dan halangan dari kaum kafir dan musyrik yang tidak senang kepada Islam merupakan peringatan bagi orang yang beriman bahwa sekalipun orang-orang musyrik itu menyiksa dan menyakiti mereka di dunia, namun pada akhirnya semuanya akan kembali juga kepada Tuhan.
Orang-orang musyrik itu kembali dengan menemui malapetaka dan kesengsaraan dalam neraka yang menyala-nyala, sedang orang beriman dan sabar dalam menghadapi penderitaan itu kembali ke tempat yang mulia dengan penuh pertolongan Allah.
Demikianlah pelajaran dari kisah Nabi Nuh. Orang kafir yang selama ini menyakiti Nuh dan kaumnya pada akhirnya ditenggelamkan Tuhan dengan banjir, tetapi orang beriman bersama Nuh selamat, berlayar di atas kapal.
Kesabaran Nuh berdakwah dalam masa yang lama itu hendaknya dijadikan pelajaran bagi setiap juru dakwah. Bahkan, seharusnya kita yang lebih besar memiliki rasa kesabaran dari Nuh, sebab umur dan usia kita berdakwah tidaklah sepanjang usia Nabi Nuh.
(Tafsir Kemenag)
Baca Setelahnya: Tafsir Surah Al-‘Ankabut ayat 16-20