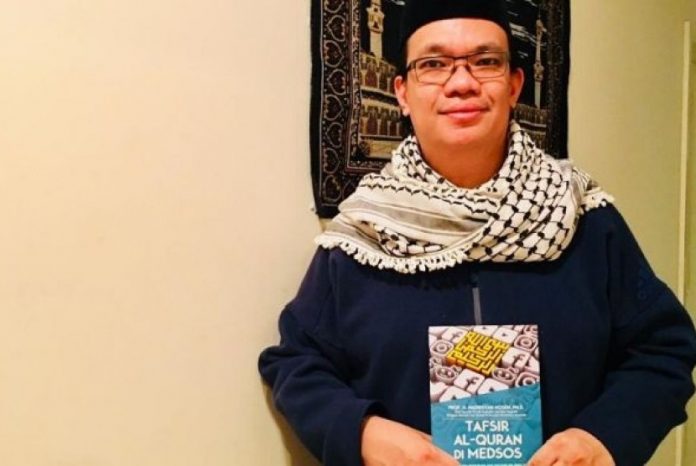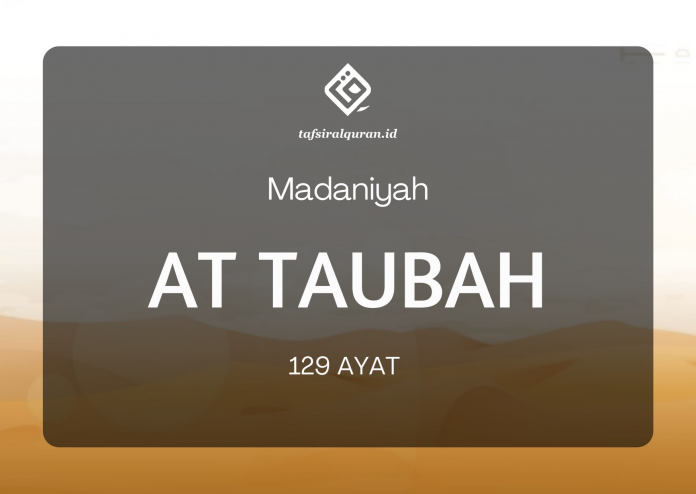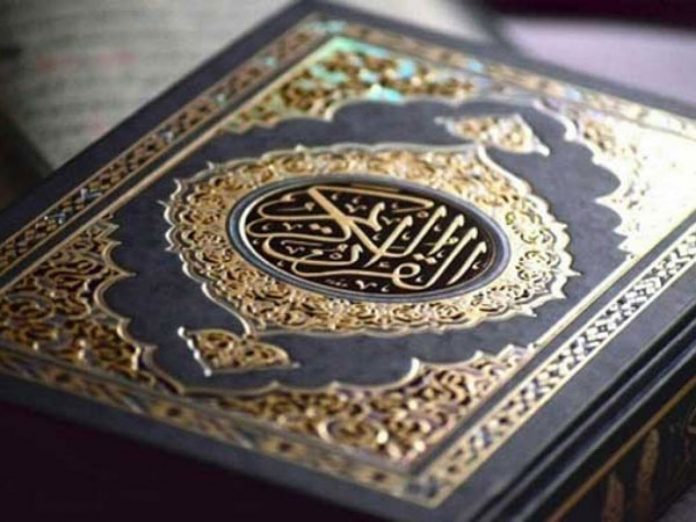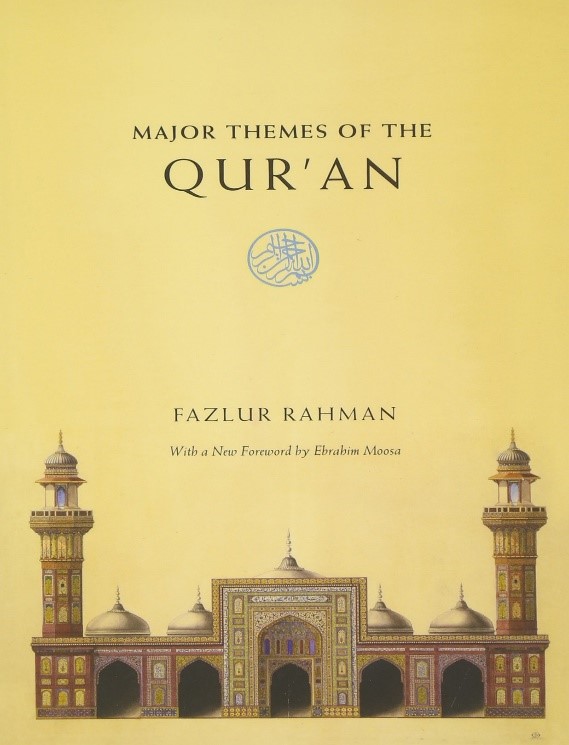Tidak dapat dihindari bahwa kehadiran media sosial telah menjadi arena tersendiri atas terjadinya fenomena penafsiran Al-Qur’an. Salah satu sarjana kontemporer yang aktif melakukan tafsir di media sosial adalah Nadirsyah Hosen. Media sosial yang ia gunakan di antaranya Facebook, Twitter, Instagram, yang kemudian penafsirannya tersebut dibukukan dengan judul Tafsir Al-Qur’an Medsos (2017).
Buku tersebut mengundang diskusi yang mendalam terkait fenomena penafsiran Al-Qur’an dan kehadiran media sosial. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana media sosial memberi nuansa, kekhasan dan karakter tersendiri bagi aktifitas penafsiran Al-Qur’an?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan memanfaatkan penafsiran Nadirsyah Hosen, terutama karena ia telah membukukan penafsirannya yang semula berada di media sosial. Ini penting, karena perpindahan arena penafsiran berimplikasi pada perubahan kekhasan sebuah penafsiran.
Nadirsyah Hosen dan Buku Tafsir Media Sosialnya
Prof. Dr. H. Nadirsyah Hosen, L.L.M., M.A. (Hons), Ph.D., lahir 08 Desember 1973 dan biasa disapa Gus Nadir, merupakan seorang Kyai Nahdlatul Ulama sekaligus sarjana Islam kontemporer yang aktif mengamati perkembangan dan dinamika Islam di media sosial. Ia termasuk sarjana yang produktif menghasilkan karya tulisan, baik berbasis nasional maupun internasional.
Baca Juga: Jajang A Rohmana: Penguak Ekspresi Lokalitas Tafsir Al-Quran di Sunda
Menariknya, banyak karyanya yang terbilang (berupaya) menjangkau model trend masa kini, terutama dengan gaya bahasa yang ringan, tetapi isi yang sangat mendalam. Di antara karya-karya Nadirsyah Hosen adalah Saring sebelum Sharing (2019), Dari Hukum Makanan tanpa Label Halal hingga Memilih Mazhab yang Cocok (2015), dan Tafsir Al-Qur’an di Media Sosial: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial, dan lainnya.
Dengan berfokus kepada buku Tafsir Al-Qur’an di Media Sosial, saya dapat membagi berbagai paparan dalam buku tersebut menjadi dua bagian: (1) penjelasan secara teoritis seputar penafsiran Al-Qur’an, dan (2) pengaplikasian penafsiran Al-Qur’an dengan berdasar pada isu-isu yang hangat dan sensitif di kalangan umat beragama Indonesia.
Yang termasuk bagian pertama adalah bab satu dari buku tersebut: Rahasia menghayati kitab suci Al-Qur’an, dengan sub bab di antaranya (1) bagaimana memahami Al-Qur’an?; (2) metode tafsir dalam Islam; (3) Logika, diplomasi dan berdebat dalam Al-Qur’an; (4) semua orang bisa memahami Al-Qur’an dan Hadis? (5) Tafsir yang terserak dari suara yang berbeda; dan seterusnya.
Adapun yang termasuk bagian kedua adalah mulai bab satu sampai bab akhir (lima) buku tersebut: Tafsir ayat-ayat politik, Menebar benih damai bersama Al-Qur’an, Al-Qur’an bergelimang makna, dan Benderang dalam cahaya Al-Qur’an, dengan berbagai sub bab yang termuat dalam setiap bab-bab tersebut.
Berbagai isi dari buku Nadirsyah Hosen di atas dapat dikatakan bahwa hanya ada dua pemahaman yang dapat diperoleh: (1) pemahaman tentang tafsir Al-Qur’an itu sendiri, dan (2) pemahaman tentang isu-isu kontemporer di Indonesia yang terangkat dalam penafsiran Nadirsyah Hosen. Artinya, buku ini sebenarnya tidak mewakili aktifitas penafsiran Nadirsyah Husen sebelumnya, yaitu tafsir di media sosial.
Tafsir di Media Sosial yang Memiliki Diskusi Tersendiri
Keberadaan tafsir Al-Qur’an di media sosial dalam bentuk buku menjadikan karakter media sosial penafsran Nadirsyah Hosen menjadi tidak jelas –jika enggang mengatakan hilang. Mengapa? Jelas jawabannya karena aspek-aspek media sosial tidak lagi muncul dalam buku tersebut. Ini bukan karena Nadirsyah Hosen sengaja menghilangkan aspek-aspek tersebut, tetapi aspek-aspek tersebut hilang dengan sendirinya.
Aspek-aspek media sosial yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menjadi fitur media sosial seperti unggah foto, komentar, like/dislike, emoticon, bagikan, laporkan, simpang, dan seterusnya. Semua yang menjadi kekhasan media sosial tersebut kemudian berimplikasi pada penafsiran Al-Qur’an.
Lebih jauh, penafsiran yang dilakukan oleh pemilik akun seperti Nadirsyah Hosen akan dengan cepat mendapat tanggapan dari pembacanya (netizen). Dalam konteks ini, penulis tafsir dan pembaca tafsir berinteraksi langsung dengan saling menanggapi melalui, misalnya, ruang komentar –pada media sosial apapun. Menariknya lagi, hal ini menjadi interaksi langsung tetapi dilakukan secara tertulis.
Walter J. Ong dalam bukunya Orality and Literacy (2002) mengatakan bahwa tulisan mengalami bebas konteks, yang berimplikasi pada keterbukaan untuk dipahami secara beragam. Penulis dan pembaca tidak sedang dalam konteks yang sama. Bagaimanapun berusahanya, keduanya sebenarnya tetap berada dalam konteksnya masing-masing. Sehingga, penulis hanya menempatkan pembacanya berdasarkan kemampuan imajinasinya, demikian juga pembaca ke penulis. Inilah yang terjadi dalam interaksi penafsir dan pembaca di kolom komentar.
Saat yang sama, persoalan ‘keterbukaan dan keberagaman pemahaman’ dalam penafsiran Nadirsyah Hosen akan diuji ketika fitur komentar menjadi jalan menutup (baca: menyelesaikan) dan menjadi satu pemahaman yang disepakati oleh penafsir dan pembacanya. Di sinilah satu poin untuk kekhasan tafsir Al-Qur’an di media sosial, yang tidak dimiliki oleh buku tafsir Al-Qur’an di media sosial di atas. Dalam artian, tafsir di media sosial mengundang diskusi penafsiran, interaksi penafsir dan pembaca, dan media sosial itu sendiri.
Tidak hanya itu, interaksi penafsir dan pembaca akan lebih menarik jika disadari adanya peran konteks dan wacana yang terjadi sebelum dan setelah penafsir memosting tafsirannya. Konteks dan wacana ini akan menambah kekhasan tafsir Al-Qur’an di media sosial. Ini karena wacana mempengaruhi munculnya sebuah penafsiran. Misalnya, tahun 2016-2018 tersebar perdebatan di mana-mana tentang QS. Al-Maidah: 51 dan kepimpinan Ahok. Konteks dan wacana seperti ini mempengaruhi penafsiran Nadirsyah Hosen yang kemudian ditanggapi oleh para pembacanya.
Baca Juga: Tafsir Pop Gus Baha’: Fenomena Pengajian Tafsir Al-Quran di New Media
Pengaruh konteks dan wacana ini cukup besar, ia dapat membentuk pro-kontra dalam sebuah penafsiran di media sosial. Dari sini, memahami pro-kontra tersebut akan mengantarkan pada pemahaman identitas, kepentingan, bahkan ideologi penafsir dan pembacanya. Tentu, ini memerlukan penelusuran yang tidak sederhana. Tetapi, hal ini akan menambah nuansa tafsir Al-Qur’an di media sosial lebih khas dan berkarakter.
Sampai di sini, perpindahan penafsiran Al-Qur’an Nadirsyah Hosen dari di media sosial ke bentuk buku cenderung menghilangkan diskusi penafsiran di media sosial itu sendiri. Sekalipun isi penafsiran Nadirsyah Hosen sama, tetapi yang demikian membawa diskusi yang berbeda karena berbeda arenanya. Aktifitas penafsiran Al-Qur’an di media sosial memiliki diskusi tersendiri, minimal, karena melibatkan fitur-fitur media sosial, konteks dan wacana penafsir beserta pembacanya. [] Wallahu A’lam.