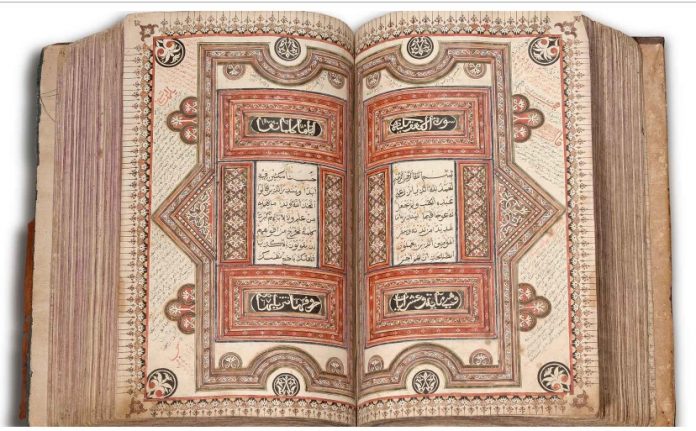Setelah usainya masa Kekhalifahan ‘Ali ibn Abi Thalib, pertikaian antar umat Islam tidak hanya bersinggungan dengan tentang siapa yang seharusnya menjadi khalifah menggantikan Nabi Muhammad. Namun juga tentang keabsahan kitab suci Al-Qur’an sebagai wahyu yang diturunkan serta dikumpulkan oleh para sahabat, tanpa mengalami pengurangan dan penambahan. Hal ini bisa disebut bahwa al-Qur’an sebagai warisan Nabi yang tidak mengalami perubahan.
Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari kemudian mencantumkan satu bab khusus yang menguatkan keabsahan Al-Qur’an sebagai wahyu yang terjaga dari segala pengurangan, penambahan serta perubahan. Di dalam bab tersebut dicantumkan bahwa Nabi Muhammad tidaklah meninggalkan satu warisanpun selain Al-Qur’an yang saat itu ada. Hal ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur’an yang saat itu ada tidak mengalami perubahan sejak zaman Nabi.
Nabi Tidak Mewariskan Apapun
Salah satu bab yang dicantumkan Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya adalah bab
باب مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ
Bab orang yang mengatakan Nabi –salallahualaihi wasallam tidak mewariskan sesuatupun kecuali yang ada di antara dua sampul (Sahih Bukhari/4/1916)
Di dalam bab tersebut, Imam Al-Bukhari hanya mencantumkan satu hadis saja yang berbunyi
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ أَتَرَكَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – مِنْ شَىْءٍ قَالَ مَا تَرَكَ إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ .
قَالَ وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ
Diriwayatkan dari Abdul ‘Aziz ibn Rufi’ bahwa ia berkata: “Aku beserta Syadad ibn Ma’qil datang ke Ibn ‘Abbas. Lalu Syadad ibn Ma’qil bertanya padanya: ‘Apakah Nabi Muhammad salallahualaihi wasallam meninggalkan sesuatu?’ Ibn ‘Abbas menjawab: ‘Nabi tidak meninggalkan sesuatupun kecuali yang ada sekarang di antara dua sampul’.”
‘Abdul ‘Aziz berkata: “Kami mendatangi Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Lalu kami menanyainya. Lalu ia menjawab: ‘Nabi tidak meninggalkan sesuatupun kecuali yang ada sekarang di antara dua sampul’.” (HR. Imam Al-Bukhari)
Baca juga: Sejarah Kodifikasi Al-Quran dalam Al-Tibyan fi Ulum al-Quran
Ibn Katsir berkata, makna dari kata “meninggalkan” adalah mewariskan harta serta selainnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan hadis yang menyatakan bahwa nabi Muhammad tidak meninggalkan dirham serta dinar, dan juga budak lelaki atau perempuan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para nabi tidaklah mewariskan dirham serta dinar, melainkan mewariskan ilmu. Sedangkan yang dimaksud dari “yang ada sekarang di antara dua sampul”, adalah Al-Qur’an serta hadis sebagai penafsir, penjelas, pengurai makna, serta mengikut terhadap Al-Qur’an (Fadhailul Qur’an/1/107).
Menyangkal Adanya Pengurangan Di Dalam Al-Qur’an
Ibn Hajar Al-‘Asqalani dan Badruddin Al-‘Aini menyatakan, lewat judul bab serta hadis di atas, Imam Al-Bukhari ingin menolak anggapan bahwa sebagian besar bagian dari Al-Qur’an telah hilang, hal ini disebabkan banyak penghafalnya yang telah mati syahid. Tuduhan ini adalah tuduhan yang dilancarkan oleh sebagian kaum syiah.
Lewat tuduhan tersebut, kaum syiah ingin mencari jalan pembenaran terhadap klaim mereka bahwa sebenarnya ada keterangan di dalam Al-Qur’an tentang kepemimpinan sahabat Ali, bahwa ia adalah khalifah yang seharusnya diangkat setelah Nabi Muhammad. Hanya saja keterangan itu disembunyikan oleh para sahabat-sahabat nabi.
Imam Al-Bukhari menolak tuduhan tersebut lewat hadis yang diriwayatkan dari Muhammad ibn Al-Hanafiyah; salah satu putra sahabat ‘Ali ibn Abi Thalib dan sosok yang dianggap salah satu dari 12 imam yang diakui oleh kalangan syiah. Imam Al-Bukhari secara tidak langsung ingin menyatakan, bukankah seharusnya kalau benar terjadi semacam pemalsuan sejarah terkait sahabat ‘Ali di dalam Al-Qur’an, yang paling mengetahui adalah anaknya sendiri?
Baca juga: Al-Baqarah Ayat 286: Allah Swt Tidak Akan Membebani Seseorang Melebihi Kemampuannya
Namun mengapa justru Muhammad ibn Al-Hanafiyah dalam hadis di atas seakan menyatakan, bahwa Al-Qur’an yang kini adalah Al-Qur’an yang sebagaimana diterima oleh Rasulullah dari malaikat Jibril. Dan ia sama sekali tidak menyinggung bahwa ada bagian dari Al-Qur’an yang hilang, atau semacam ungkapan “Al-Qur’an yang sekarang adalah sebagian dari warisan Nabi Muhammad. Dan ada bagian lain yang hilang atau disembunyikan”.
Ibn ‘Abbas dalam hadis di atas juga menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Padahal Ibn ‘Abbas adalah keponakan sahabat ‘ali Serta orang yang paling dekat serta mengetahui segala keadaaan Sahabat ‘Ali (Fathul Bari/9/65).