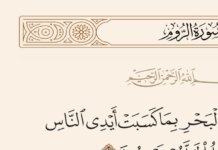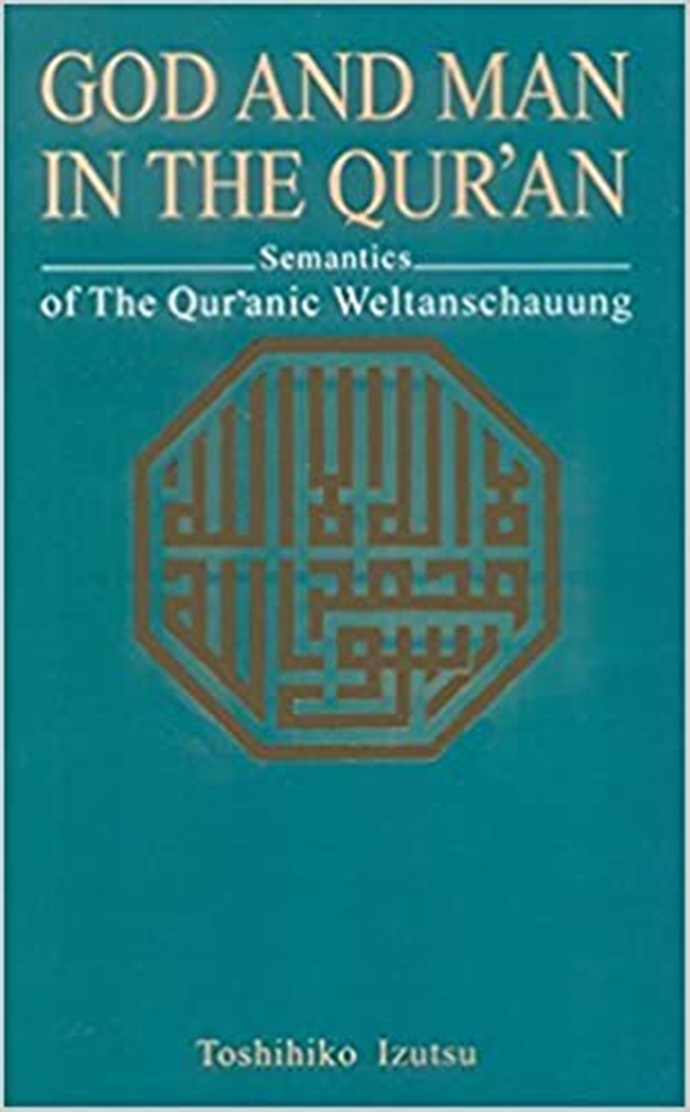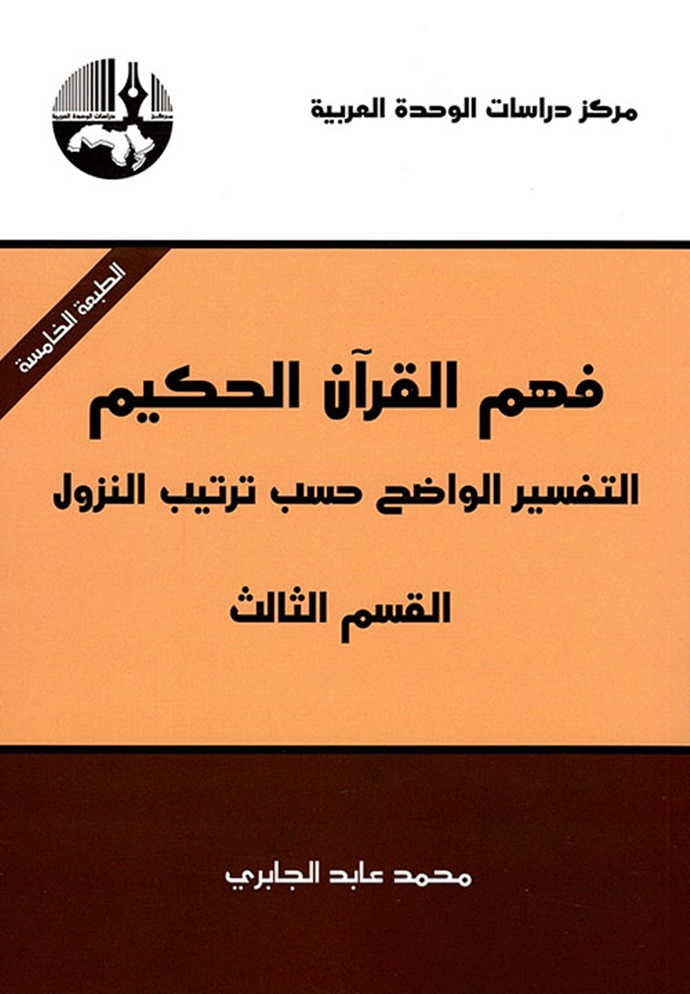Toshihiko Izutsu merupakan seorang poliglot asal Jepang yang menjadi pakar di bidang semantik Al-Quran. Gagasannya terkait kajian semantik Al-Quran memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam perkembangan kajian studi Al-Quran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya akademisi yang mengadopsi teori semantik Izutsu sebagai pendekatan baru dalam kajian akademik. Oleh karena itu, mari kita mengenal lebih jauh tentang teori semantik Al-Quran Toshihiko Izutsu.
Teori Semantik Al-Quran Toshihiko Izutsu
Toshihiko Izutsu membagi wahyu (Al-Quran) menjadi dua bagian utama, yaitu Tuhan dan firman. Dilihat dari segi Tuhan, wahyu dipandang sebagai suatu misteri yang mustahil dijangkau oleh manusia, karena ia bersifat teosentris. Sedangkan apabila dilihat dari sisi firman, wahyu tersebut memuat dua hal, yaitu parole dan langue. (Aksin Wijaya, Menalar Autentisitas Wahyu Tuhan)
Parole adalah komunikasi linguistik yang terjadi dalam situasi konkret antara dua orang, dimana salah satunya memainkan peran aktif, sedangkan lainya bersifat pasif. Sedangkan Langue dimaknai sebagai suatu sistem isyarat verbal yang telah dikenal sebagai alat komunikasi berdasarkan kesepakatan bersama.
Baca Juga: Mengenal Toshihiko Izutsu, Poliglot Asal Jepang, Pengkaji Semantik Al-Quran
Firman Tuhan (Al-Quran) memiliki dimensi parole, karena ia diutarakan oleh Tuhan secara personal. Namun, karena ia berhubungan dengan alam manusia, maka bahasa firman tersebut harus disesuaikan dengan bahasa manusia, khususnya masyarakat Arab.
Oleh karena itu, dipilihlah bahasa Arab sebagai bahasa perantara (langue) dalam penyampaian firman Tuhan, supaya terjadi komunikasi linguistik yang efektif dan dapat dipahami.
Dalam kajian semantik, analitis kebahasaan merupakan hal yang sangat penting. Toshihiko Izutsu mendefinisikan gagasan semantiknya sebagai kajian analitis terhadap kumpulan istilah kunci bahasa yang kemudian menghasilkan pada pemahaman konseptual Weltanschauung (pandangan dunia) dari masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut.
Tujuan dari analisis semantik tersebut adalah memunculkan tipe ontologi hidup yang dinamis dari Al-Quran dengan penelaahan secara analitis dan metodologi terhadap konsep-konsep pokok, yaitu konsep-konsep yang tampaknya memainkan peran menentukan dalam pembentukan visi Qur’ani tentang alam semesta. (Ahmad Sahidah, God, Man, and Nature)
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori semantik Toshihiko Izutsu ini tidak hanya sebagai alat untuk memahami makna harfiah sebuah kata, tetapi lebih jauh untuk mengungkapkan pengalaman kebudayaan yang terkandung di dalam kata tersebut. Sehingga pada akhirnya, akan mencapai suatu rekonstruksi tingkat analitis struktur keseluruhan budaya sebagai konsepsi masyarakat yang sungguh-sungguh ada. Inilah yang disebut oleh Izutsu sebagai weltanschauung semantik budaya.
Baca Juga: Kajian Semantik: Makna Kata Jannah dalam Al-Qur’an
Metode Semantik Al-Quran Toshihiko Izutsu
Toshihiko Izutsu menjelaskan bahwa terdapat empat hal penting yang perlu dipahami terdahulu sebelum menerapkan semantik terhadap teks Al-Quran. Keempat hal tersebut adalah memahami keterpaduan konsep-konsep individual, kosakata, makna “dasar” dan makna “relasional”, serta pandangan dunia (weltanschauung).
Secara prosedural, Toshihiko Izutsu memberikan beberapa tahapan dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penerapan teori semantik Al-Quran tersebut, yaitu Pertama, menentukan terlebih dahulu terkait topik atau tema kajian tertentu yang akan dijadikan fokus penelitian dan objek analisis teori semantik Al-Quran.
Kedua, setelah menentukan tema, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan semua kosakata yang berkaitan dengan tema pembahasan tersebut. Setelah terkumpul semua, dilakukan proses pemilahan dari berbagai kosakata tersebut untuk mencari satu kosakata kunci yang akan dikaji secara mendalam.
Ketiga, menelusuri makna dasar dari kosakata tersebut. Makna dasar yang dimaksud adalah kandungan kontekstual dari kosa kata yang akan tetap melekat pada kata tersebut, meski kata tersebut dipisahkan dari konteks pembicaraan kalimat.
Keempat, menguraikan makna relasional sebuah kosakata, yang dalam penerapanya sangat bergantung kepada konteks, sekaligus relasi antar kosakata dalam satu kalimat. Untuk mengetahui makna relasional tersebut, diperlukan dua metode analisis linguistik, yaitu analisis sintagmatik dan paradigmatik.
Analisis sintagmatik adalah suatu analisa yang berusaha mencari makna dalam suatu kata dengan melihat kata yang di depan maupun di belakang kata tersebut. Sedangkan analisis paradigmatik adalah mencari makna dengan cara membandingkan kata atau konsep dengan kata yang senada ataupun yang bertolak belakang.
Baca Juga: Kajian Semantik Pasangan dalam Al-Quran: Perbedaan Al-Ba‘l dan Al-Zauj
Kelima, mulai memasuki wilayah medan semantik. Semantik diakronik adalah pandangan terhadap bahasa yang menitikberatkan pada unsur waktu. Sedangkan semantik sinkronik adalah pandangan suatu kata yang melintasi garis historis, yang muncul pada suatu sistem kata yang statis.
Untuk mengungkap historisitas makna sebuah kata, Toshihiko Izutsu mengisolasikan tiga fase permukaan semantik yang berbeda, yaitu: (1) pra-Qur’an (masa Jahiliyah), yaitu masa pra-Islam yang berpusat pada tiga sistem kata yang berbeda, yaitu sistem kata baduwi murni, pedagang, dan koskata yang digunakan oleh Yahudi-Kristen; (2) Qur’an (masa turunya Al-Quran); dan (3) pasca-Qur’an, terutama pada masa Dinasti Abbasiyah.
Keenam, proses yang paling utama dari teori semantik Al-Quran Toshihiko Izutsu yaitu menemukan weltanschauung atau dalam istilah lain disebut worldview (pandangan dunia) dari kata yang dikaji tersebut. Kemudian, langka yang terakhir, ketujuh, yaitu menjelaskan terkait pesan yang terkandung dalam sebuah kata yang telah mengalami proses analisis tersebut.
Untuk lebih memudahkan dalam memahami aplikasi teori semantik Al-Quran Toshihiko Izutsu tersebut, Ahmad Sahidah memberikan bagan proses dan tahap-tahapan dalam penerapan teori semantik tersebut, sebagaimana berikut:
Baca Juga: Introducing English Semantics: Teori Semantika Al-Quran Ala Charles W. Kreidler
Kontribusi Teori Semantik Al-Quran Toshihiko Izutsu
Para ulama pengkaji Al-Quran baik klasik maupu kontemporer sepakat bahwa metode penafsiran Al-Quran yang terbaik adalah penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainya (tafsir Al-Quran bi Al-Quran). Hal ini dikarenakan anggapan yang menyatakan bahwa makna sejati dari teks ialah apa yang diketengahkan oleh teks itu sendiri.
Teori semantik Al-Quran yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu ini merupakan sebuah pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian secara mendalam terhadap teks berupa ayat Al-Quran, dengan mempertimbangkan relasi (munasabah) dari teks-teks Al-Quran lainya.
Kemudian, penggunaan sumber-sumber pra-Qur’an berupa syair-syair jahiliyah sebagaimana yang digunakan oleh Ibnu Abbas juga diterapkan dalam teori semantik Al-Quran Izutsu ini. Sehingga diharapkan dengan pendekatan ini mampu memberikan pandangan objektif terhadap apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Hal ini dikarenakan teori semantik tersebut berusaha mengungkapkan makna yang di dalam ayat, bukan di luar ayat.
Keberadaan teori semantik Al-Quran Toshihiko Izutsu ini dapat dijadikan sebagai pendekatan baru dalam memahami ayat Al-Quran tanpa meninggalkan pendekatan tafsir Al-Quran konvensional yang sudah berkembang. Sehingga, dengan munculnya pendekatan baru tersebut menjadikan kajian Al-Quran semakin berkembang dengan berbagai perspektif dan sudut pandang. Wallahu A’lam