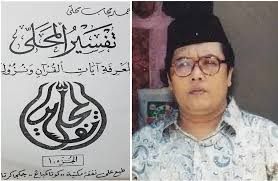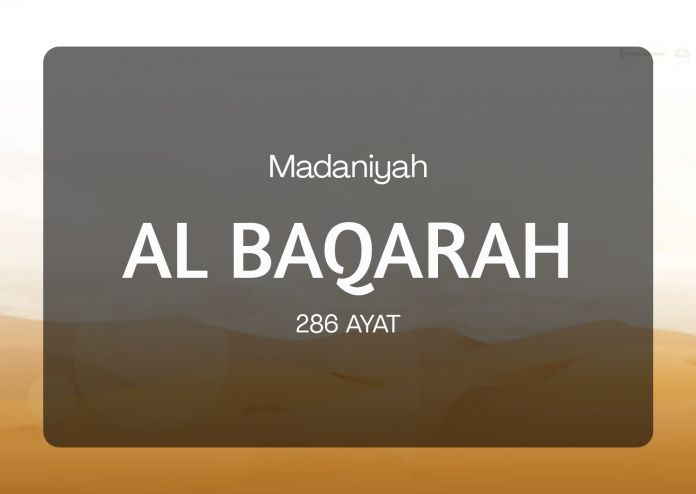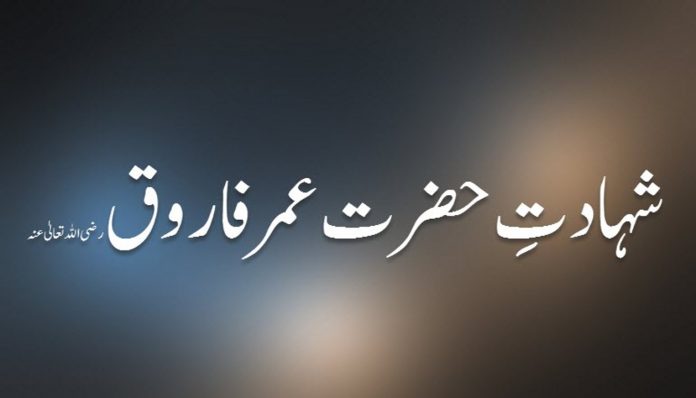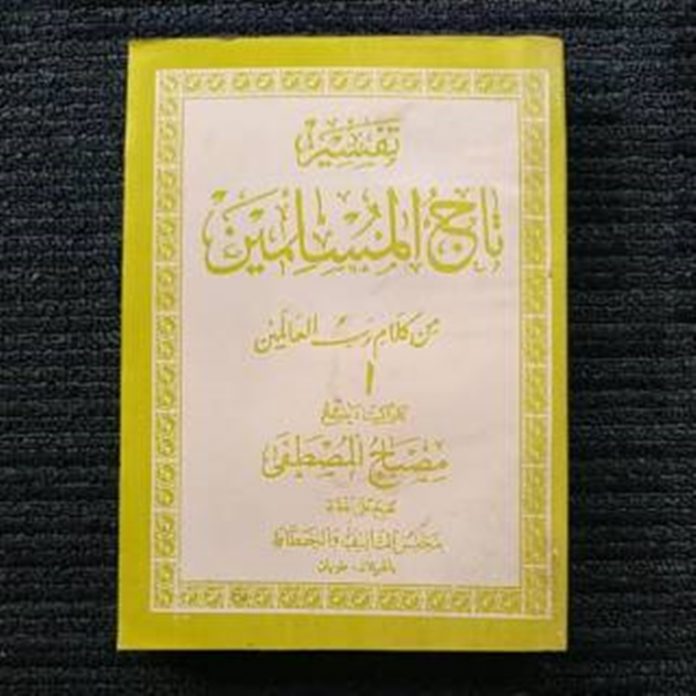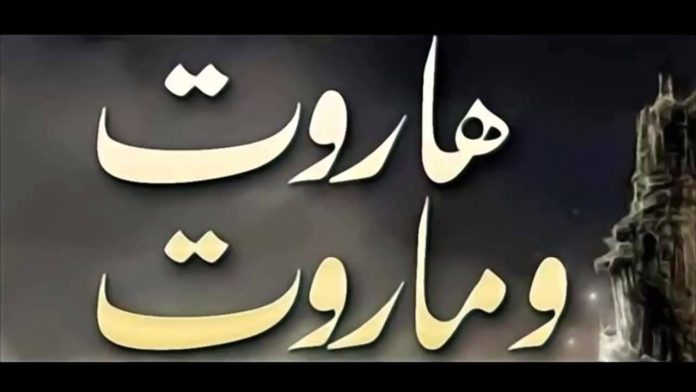Setelah Amin Al-Khulli, lahirlah banyak tokoh yang mencoba memahami Al-Quran dengan menggunakan pendekatan sastra. Salah satunya yaitu Mustansir Mir. Sama dengan Amin Al Khulli, seorang tokoh mufasir yang berpendapat bahwa Al-Quran merupakan kitab bahasa Arab paling besar dan paling agung, yang oleh karenanya dia mencoba memahami Al-Quran dengan sastra bukan lagi dengan pendekatan teologis seperti para mufasir sebelumnya, Mustansir Mir juga demikian.
Muntansir Mir adalah Profesor Islamic Studies pada Youngstown State University, Ohio, US. Dia menyelesaikan sarjana dan magisternya di Punjab University, Lahore, Pakistan. Dia menyelesaikan magister keduanya dan mendapatlan gelar Ph.D dari University of Michigan, Ann Arbor dalam bidang Islamic Studies. Dia mengajar di Universitas Lahore, University of Michigan, University of Virginia, University of Oxford, Youngstown University dan International Islamic University di Malaysia.
Banyak karya yang ditulis oleh Mustansir Mir yang mana ia mengkhususkan kajiannya terhadap pendekatan sastra. Seperti Verbal Idioms of the Quran, The Quran as Literature dan lain sebagainya. Mir menggunakan pendekatan sastra untuk menjelaskan kisah Yusuf dalam Al-Quran.
Mustansir Mir menerapkan kritik sastra kepada Al-Quran dengan menganalisis struktur cerita. Menurutnya, Al-Quran adalah salah satu karya sastra besar seperti Alkitab. Namun demikian, penyajian kesusastraan Al-Quran tidak bervariasi sebanyak yang Alkitab lakukan. Dalam Alkitab, ada lagu-lagu rakyat, puisi-puisi yang berisi duka cita dan ratapan, kegairahan para nabi, puisi yang menggambarkan keindahan alam dan sebagainya.
Pesan dalam Al-Quran disajikan oleh perangkat dan teknik sastra, seperti cerita, perumpamaan, dan sketsa karakter, menggunakan kiasan dan sejenisnya. Beberapa mufasir sebelumnya juga telah menggunakan pendekatan sastra untuk menafsirkan Al-Quran, salah satunya Amin Al-Khulli.
Al-Khulli mengedepankan dua prinsip metodologis yang merupakan metode ideal untuk mengkaji teks sastra. Dua metode tersebut yaitu; pertama, kajian terhadap segala sesuatu yang berada di sekitar Al-Quran (dirasah ma haula Al-Quran) dan kedua, kajian terhadap Al-Quran itu sendiri (dirasah fi Quran nafsihi).
Baca Juga: Amin Al-Khuli: Mufasir Modern Yang Mengusung Tafsir Sastrawi
Kajian seputar Al-Quran terfokus pada pentingnya aspek historis, sosial, kutural dan antropologis wahyu bersamaan dengan masyarakat Arab abad ke 7 Hijriah sebagai objek langsung ketika Al-Quran diturunkan. Secara teknis kajian ini lebih dikenal dengan Ulumul Quran.
Kajian selanjutnya yaitu kajian Al-Quran terhadap dirinya sendiri (dirasah ma fil Quran nafsihi). Kajian ini dimulai dengan meneliti kosa kata Al-Quran dengan mencari bentuk tunggalnya (mufrad) agar dapat dipahami secara total. Setelah mengkaji makna kata dari segi bahasa dan perkembangannya dilanjutkan pada kajian terhadap makna berdasarkan pada pemakaiannya dalam Al-Quran.
Tidak hanya berhenti dalam kajian asal kata, Al-Khulli juga mengamati preferensi penggunaan kata atau struktur bahasa, mengidentifikasi sintaksis (tipe struktur kalimat), leksikal (diksi, penggunaan kata tertentu), deviasi (penyimpangan dari kaidah umum tata bahasa).
Usaha Al-Khuli mengembangkan metode sastra dalam tafsir ini merupakan langkah untuk menjauhkan penafsiran dari subyektifitas mufasir. Sama halnya dengan Al-Khulli, Mir juga berkeinginan untuk merubah pola penafsiran yang subjektif menjadi objektif, setidaknya melalui pendekatan sastra yang telah Mir rumuskan.
Pendekatan Sastra yang digunakan oleh Mir agak sedikit berbeda dengan Al-Khulli. Mir lebih banyak menambahkan hal-hal yang belum tersentuh pada metode sastra Al-Khulli.
Baca Juga: Bint ِِAs-Syathi: Mufasir Perempuan dari Bumi Kinanah
Unsur-unsur sastra Al-Quran
Unsur-unsur sastra Al-Quran menurut Mustansir Mir antara lain; Pertama yaitu word choice. Al-Quran memilih kata-katanya dengan cara yang sangat rinci dan rumit, sehingga maknanya hanya dapat dipahami setelah pembacaan yang teliti. Misalnya Surat Al-Ahzab [33]: 13.
Kedua, gambaran atau kiasan. Al-Quran menggunakan bahasa yang indah. Ekspresi alegoris dan perumpamaan sering digunakan di dalamnya. Keindahannya diakui dari caranya menggambarkan fenomena alam dan situasi orang Arab abad ke-7. Misalnya dalam QS Al-Qamar [54]: 19-20.
Ketiga, humor, sindiran dan ironi. Dalam Al-Quran tidak terlalu banyak ayat yang mengandung humor. Seperti dalam surat Al-Kahfi [18]:62-64. Keempat, permainan kata dan ambiguitas. Salah satu contoh permainan kata dalam Al-Quran yaitu terkandung dalam QS al-Baqarah[2]:61.
Kelima, narasi. Al-Quran biasanya tidak menceritakan keseluruhan cerita tetapi menceritakan bagian-bagiannya saja dan dalam bab yang berbeda. Ini bertujuan untuk menekankan tujuan mengapa sebuah kisah diceritakan dalam sebuah bab. Sebagai contoh, kisah Ibrahim termuat dalam surat-surat berikut: Al-An’am [6], Al-Anbiya [21], Al-Dhariyat [51] dan Al-Mumtaḥanah [60].
Baca Juga: Mengenal Makna Majaz dalam Al-Quran
Keenam, dialog dramatis. Dialog dalam Al-Quran biasanya diberikan dalam teks sederhana yang berisi pemahaman mendalam tentang pikiran dan perilaku manusia. Dialog biasanya ditemukan dalam narasi cerita-cerita dalam Al-Quran, seperti dialog antara Musa dan Khidr (Surah Al-Kahfi [18]: 65-83), Musa dengan Firaun (Surah Al-Syu’ara [26]: 16- 37) dan lainnya.
Ketujuh, karakter. Karakter Dari aspek teologis, karakter-karakter yang disebutkan dalam Al-Quran muncul dari manifestasi sifat atau karakteristik tokoh yang diriwayatkan. Dibandingkan dengan yang lain, karakter para nabi, seperti Ibrahim, Musa, Yusuf, dan lainnya, kebanyakan disebutkan di dalamnya. Inilah unsur-unsur sastra dalam Al-Quran menurut Mustansir Mir.