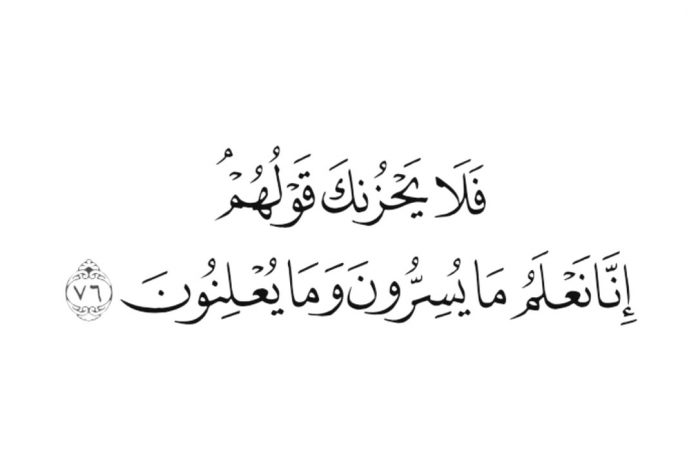Pembakaran Alquran menjadi topik yang mencuat di berbagai pemberitaan media daring (website dan media sosial) akhir-akhir ini. Hal ini terkait dengan aksi membakar Alquran oleh salah satu politisi sayap kanan, hard line Denmark di depan kantor kedutaan Turki, Swedia.
Peristiwa ini pada akhirnya menyisakan problem etis di kalangan umat beragama, terutama umat Islam. Walaupun tindakan tersebut memiliki landasan politik yang diartikan sebagai “kebebasan berekspresi”, pada kenyataannya malah menampilkan sikap seorang politisi dengan logika dan nalar politik yang sempit.
Terlepas dari kitab suci agama manapun, setiap umat beragama memiliki hubungan mendalam dengan ajaran-ajaran kitab sucinya di kehidupan sehari-hari (Filsafat Agama, 3-4).
Musyawarah
Setiap kitab suci agama-agama boleh jadi memuat ajaran moral spiritual individu terhadap Tuhan dan sosial hingga urusan politik. Dalam konteks ini terdapat ayat Alquran yang menjelaskan pandangan berpolitik Islam, yaitu Q.S. Ali Imran (3): 159.
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.
Baca juga: Viral Aksi Meludahi Alquran, Ini Cara Pilih Sikap menurut Alquran!
Di dalam Tafsir Al-Kasysyaf (Juz 4, 202) dijelaskan keutamaan musyawarah dalam memutuskan suatu perkara yang tidak ada wahyu terkait turun guna menyelesaikan masalah tersebut. Dalam konteks ini penjelasan ayat di atas dapat dikaitkan dengan watak elegan seorang politisi dalam berpolitik. Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi nilai utama apabila dilakukan dalam forum yang bertanggung jawab, bukan secara sporadis dan egois.
Menghormati kitab suci
Realitas di dunia ini begitu kompleks. Itulah mengapa Indonesia memiliki slogan khusus yang merepresentasikan pluralitas kebudayaan masyarakatnya, yaitu “Bhineka Tungal Ika”. Dari slogan tersebut dapat ditarik hikmah penting bahwa menyikapi perbedaan yang ada membutuhkan pandangan yang melahirkan persatuan, serta menghormati pihak yang berbeda dan sesuatu yang dianggap penting oleh kelompok tertentu.
Salah satu ayat Alquran yang menjadi landasan utama dalam menghormati lian yaitu Q.S. Al-An’am (6): 108.
وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
“Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setip umat menganggap baik perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang dulu mereka kerjakan.”
Al-Qurtubi (Tafsir Al-Qurtubi, juz 4, 491) menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang beriman memaki berhala orang-orang musyrik dikarenakan apabila berhala tersebut menjadi objek makian orang beriman, malah justru akan menambah kekufuran dalam diri mereka.
Baca juga: Ayat-Ayat Konflik yang Dipahami Keliru dan Kemunculan Kafirphobia di Kalangan Umat
Lebih lanjut dijelaskan bahwa larangan ini bersifat abadi dalam segala situasi dan kondisi umat Islam. Makna sembahan dalam tafsir ini mencakup salib (simbol), ajaran agama, dan gereja (tempat ibadah) umat agama lain.
Sementara itu diterangkan dalam Tafsir Al-Azhar (jilid 3, 2134-2136) bahwa perbuatan memaki, menghina, dan mencerca unsur-unsur agama lain termasuk dalam kategori dosa besar. Kandungan ayat di atas memuat larangan keras yang apabila dilakukan oleh umat beragama terhadap umat lain akan melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak kunjung usai. Hamka menengarai sebaiknya dakwah Islam dilakukan dengan menunjukkan keburukan menyembah berhala dengan alasan yang masuk akal.
Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (vol. 4, 242) juga menjelaskan perincian maksud khusus yang terkandung dalam ayat ini. Menurutnya, perbuatan mencaci tuhan-tuhan orang-orang musyrik dikhususkan kepada pengikut Nabi Muhammad. Dengan demikian, redaksi ayat ini menyatakan kemuliaan akhlak Nabi sebagai rahmat, bukan pemaki dan pencerca. Tugas utamanya tidak lain adalah menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia, bukan memaksa hingga memaki keyakinan yang berbeda dengan risalah yang diserukannya.
Penutup
Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa agama Islam melalui kitab suci Alquran menghendaki manusia, terutama umat Islam berpolitik dengan baik; bijak dan bertanggung jawab. Kebebasan berekspresi dalam bentuk apapun lebih utama diutarakan dalam musyawarah dengan saling menghormati satu sama lain.
Dalam konteks menghormati kitab suci agama-agama, Alquran secara eksplisit melarang seorang muslim mencaci agama lain. Hal ini juga dijelaskan oleh beberapa ulama tafsir ketika menjelaskan Q.S. Al-An’am (6): 108.
Baca juga: Muhammad Nabi Cinta; Nabi Muhammad di Mata Seorang Penganut Katolik
Aksi kontroversial pembakaran Alquran dalam hal ini terkategori dalam perbuatan mencaci salah satu unsur fundamental agama Islam. Namun demikian, upaya alternatif umat Islam supaya tidak terjerembab dalam emosi adalah dengan mendalami keterangan-keterangan para ulama dari masa ke masa, sehingga umat Islam dapat mendalami tuntunan Alquran secara mendalam dan mengkhidmati pesan kenabian sebagai teladan utama sepanjang hayat.