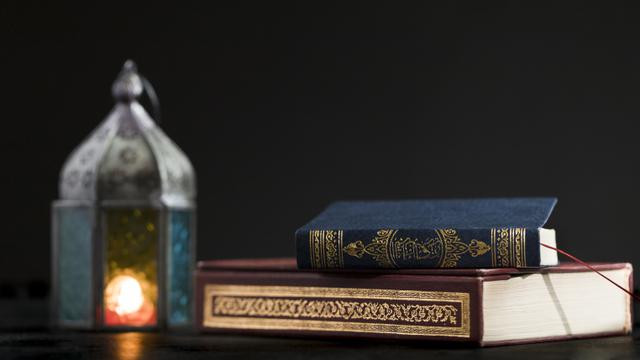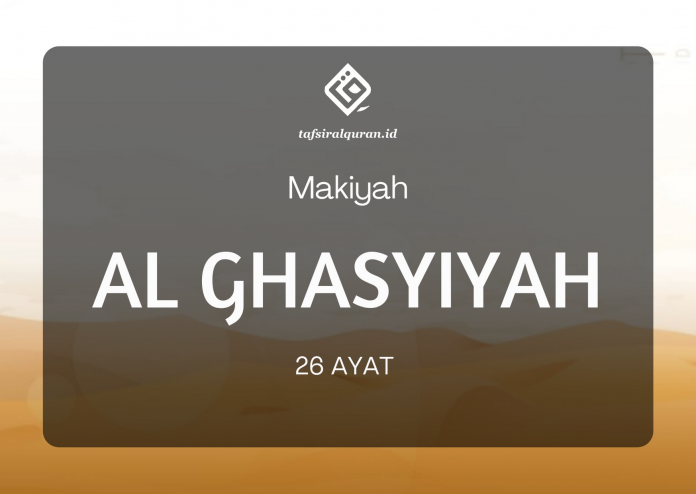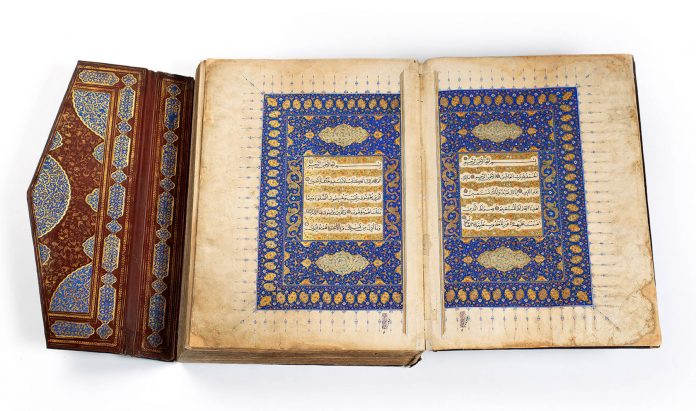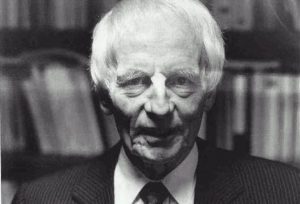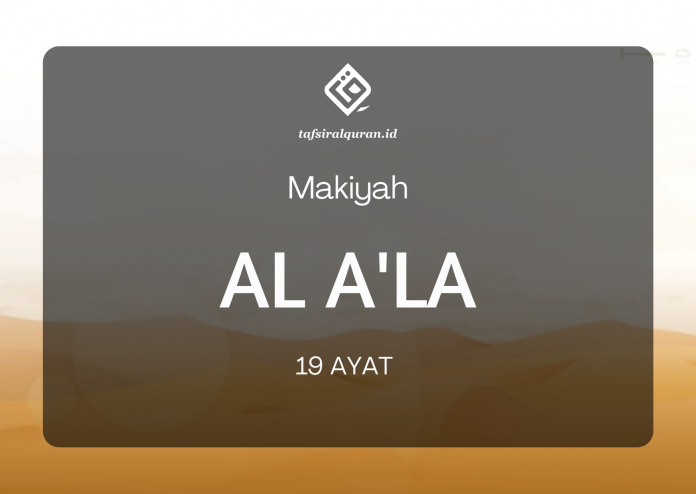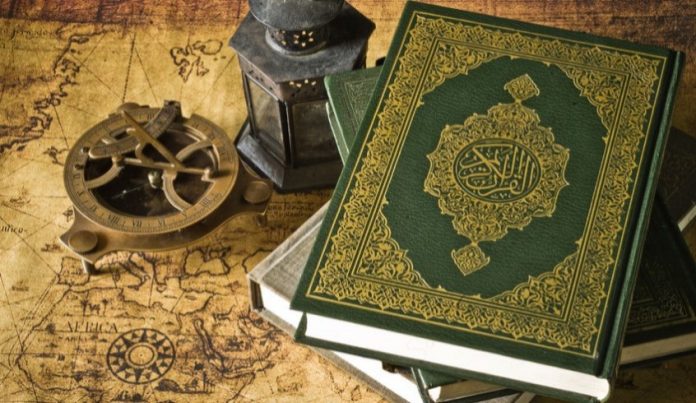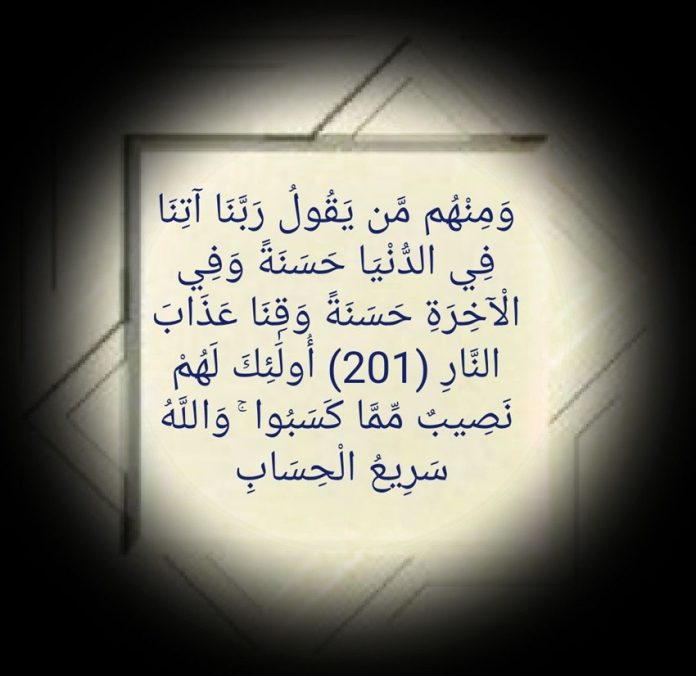Anjuran Al-Quran tentang musyawarah ditemukan tersebar dalam banyak ayat Al-Quran. Melalui ayat-ayat ini, Al-Quran sangat memperhatikan musyawarah di setiap ini kehidupan. Di antara ayat itu adalah surah Ali Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38.
Ar- Raghib al Isfahani dalam kitab al-Mufradat mengutarakan bahwa musyawarah berasal dari bahasa Arab musyawarah yang berasal dari bentuk isim masdar dari kata kerja syawara, yusyawiru. Kata ini terambil dari akar kata syin, wau, dan ra yang bermakna pokok mengambil sesuatu , menampakkan, dan menawarkan sesuatu.
Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kata tersebut semulanya bermakna dasar mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Kata ini pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas.
Baca Juga: Inilah Metode Dakwah Ideal Menurut Al-Quran, Tafsir Surat An-Nahl Ayat 125
Anjuran Al-Quran tentang musyawarah
Anjuran Al-Quran tentang musyawarah disampaikan dengan berbagai bentuk kata. Syawara dengan segala derivasinya terulang sebanyak empat kali diantaranya ‘asyarat, syawir, syura dan tasyawur. Sebagaimana firman Allah (QS. Ali ‘Imran [3]: 159)
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
Sayyid Qutub dalam kitab fi Zilal Al-Quran mengutarakan bahwa dalam ayat ini disebut tiga sifat dan sikap secara berurutan yang diperintahkan kepada Nabi untuk dilaksanakan sebelum musyawarah. Ketiga sifat tersebut adalah berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras.
Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud di mana umat Islam mengalami kekalahan yang serius, namun esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan setiap kaum muslim yang hendak mengadakan musyawarah, apalagi seorang pemimpin. Kalau dia berlaku kasar dan keras hati, niscaya peserta musyawarah akan meninggalkannya.
Berdasar pada ayat itu juga, Ibnu Faris dalam kitab Mu’jam berpendapat bahwa dalam musyawarah, sikap yang harus diambil oleh Nabi saw dan juga orang yang bermusyawarah adalah memberi maaf, yang pada ayat ini diungkapkan dengan kalimat fa’fu ‘anhum. Kata maaf berasal dari kata al-‘afwuw yang terambil dari akar kata yang terdiri huruf-huruf ‘ain, fa’ dan wau. Makna dasarnya berkisar pada dua hal, yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini lahir kata ‘afwu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan)
Petunjuk terakhir dari ayat tersebut dalam konteks musyawarah adalah فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ “Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah”. Ayat tersebut mengisyaratkan apabila tekad sudah bulat untuk melaksanakan hasil kesepakatan dalam musyawarah, maka pada saat yang harus sama harus diikuti denagan sifat tawakkal kepada Allah swt.
Baca Juga: Inilah 4 Karakter Kepemimpinan Transformatif Menurut Al Quran
Ayat kedua yang juga menjelaskan anjuran Al-Quran tentang musyawarah adalah surah Asy-Syura [42]: 38
وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ – ٣٨
dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,
Ayat ini termasuk dalam kelompok ayat Makkiyyah. Ini berarti bahwa umat Islam telah mengenal tradisi musyawarah sebelum mereka hijrah ke Madinah. Bahkan, sebelum Islam datang masyarakat telah juga mengenal tradisi musyawarah, sehingga wajar Mustafa al-Maragi berpendapat dalam Tafsir al-Maraghi, bahwasanya musyawarah sebenarnya merupakan fitrah manusia. Pandangan Al-Maraghi ini disampaikan ketika menafsirkan ayat 30 Surah Al-Baqarah tentang “keberatan” malaikat atas pengangkatan Adam sebagai khalifah di bumi.
Pandangan yang hampir sama diberikan oleh Fazlur Rahman dalam tulisannya “Implementation of The Islamic Concept of State in The Pakistani Milieu” yang menyatakan bahwa musyawarah bukanlah suatu yang berasal dari tuntunan Al-Quran untuk pertama kali, melainkan suatu tuntunan abadi dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Lebih jauh, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa musyawarah kemudian diperluas oleh Al-Quran dengan mengubahnya dari institusi kesukuan menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman.
Baca Juga: Surat As-Syura Ayat 38, Dalil Demokrasi dalam Al Quran
Sementara itu, di dunia politik, musyawarah diidentikkan dengan demokrasi meski tidak sepenuhnya identik. Yusuf Al-Qaradhawi, dalam kitabnya Min Fiqh ad-Daulah Fil-Islam berpendapat bahwasanya musyawarah dan demokrasi memiliki titik persamaan. Di antaranya adalah bahwa substansi demokrasi adalah memberikan bentuk dan beberapa sistem yang praktis. Seperti pemilu untuk meminta pendapat rakyat, kebebasan berpendapat, dan lain-lain. Hal-hal tersebut jelas adalah bagian terpenting dari musyawarah yang di ajarkan Islam.
Dari pemaparan ayat-ayat tentang musyawarah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah adalah salah satu perintah agama yang harus ditegakkan, bahkan Al-Qurtubi dalam Jami’ul-Ahkam berpandangan lebih jauh dengan mengatakan bahwa seorang yang menjabat kepala Negara, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan ahli agama haruslah dipecat.
Pendapat ini memang mengaitkan kedudukan musyawarah dalam sistem politik. Namun seperti yang telah dijelaskan di awal, musyawarah tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam hal lainnya. Dalam musyawarah yang terpenting adalah bukan siapa yang menyampaikan pendapat, dari kelompok mayoritas atau minoritas, tetapi bagaimana kualitas pendapat tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan umat.