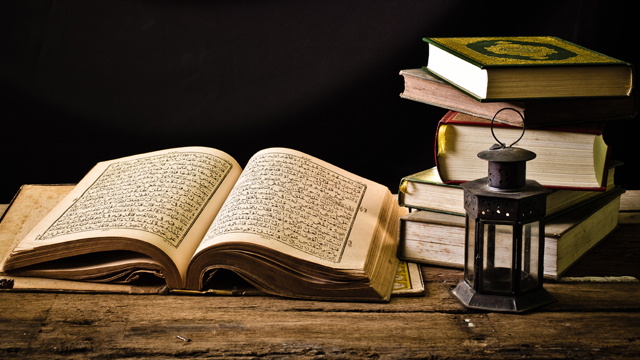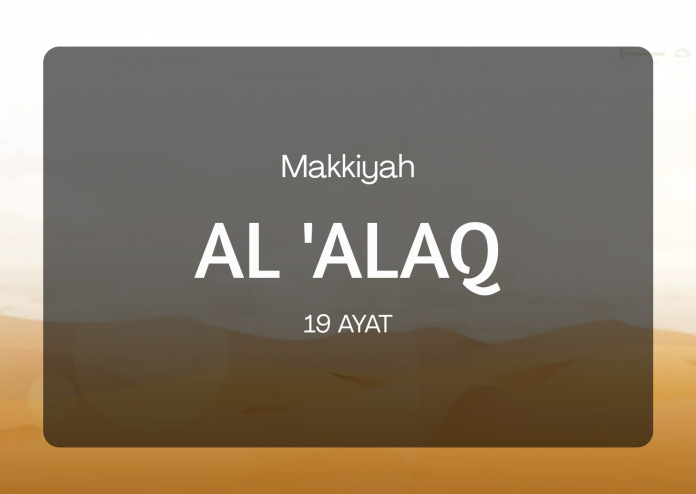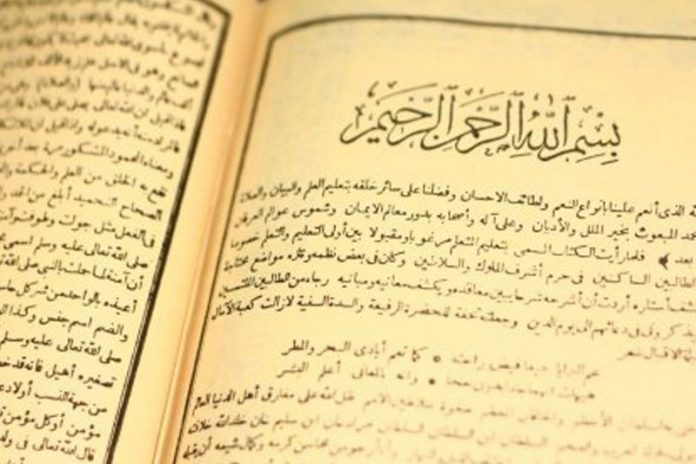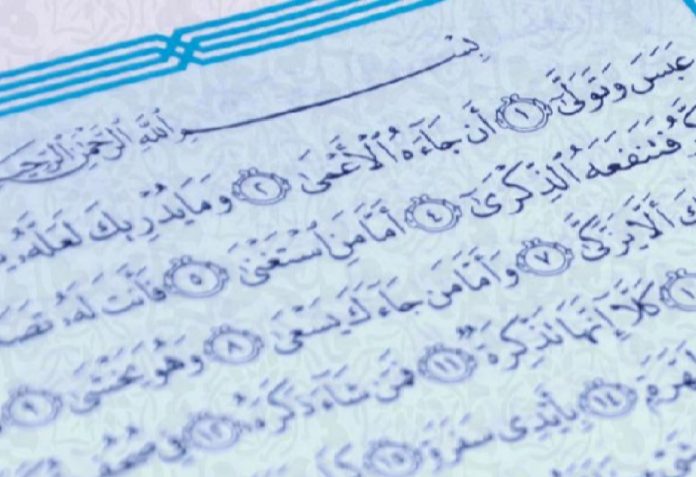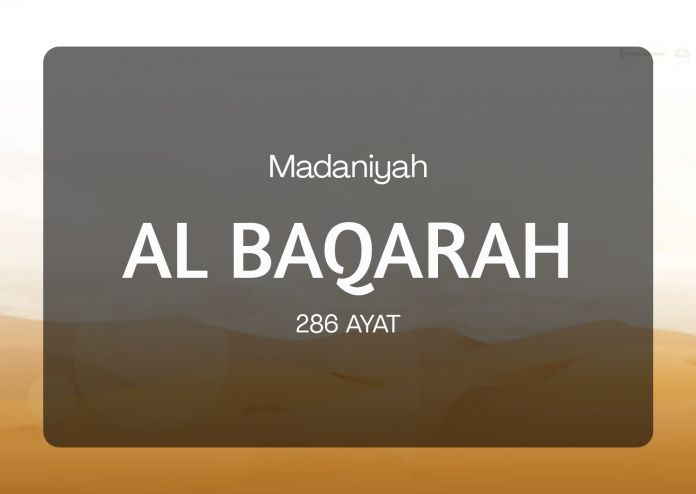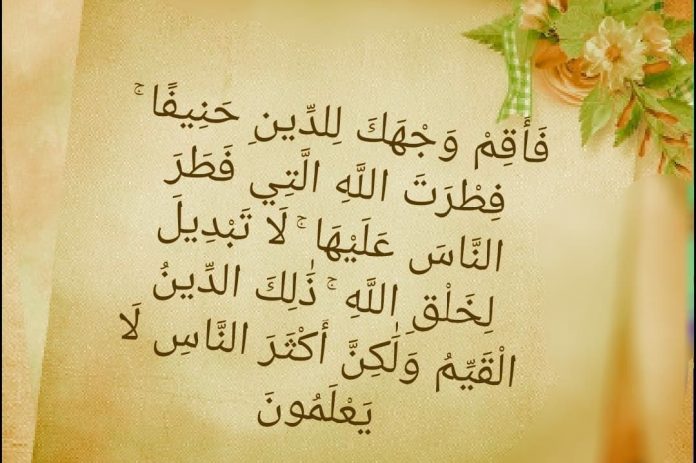Jamak kita temui kitab-kitab yang berisi empat puluh hadis atau lazim disebut kitab arba’in (al-arba’iniyyat) dan dikarang oleh para ulama dengan metode tematik. Misalnya adalah kitab Arba’in An-Nawawi karya Abu Zakaria Muhy al-Din bin Syaraf al-Nawawi al-Damasyqi yang menghimpun 42 hadits tentang ushulud din, pondasi agama.
Sudah menjadi suatu tradisi bagi para ulama untuk menghimpun permasalahan dalam agama dalam sebuah rangkuman. Arba’in An-Nawawi bukanlah satu-satunya kitab dengan metode rangkuman tersebut. Bahkan saking jamaknya kitab-kitab al-arba’iniyyat, tidak diketahui siapa ulama yang pertama kali mengarang kitab dengan metode ini.
Namun berdasarkan beberapa catatan dalam berbagai mukadimah kitab al-arba’iniyyat, seperti dalam mukadimah anotasi Arba’in An-Nawawi karya Imam Nawawi Banten, ulama pertama yang menulis karya kitab arba’in ialah Imam Abdullah bin al-Mubarak yang hidup pada 118 -181 H.
Setelah Ibn al-Mubarak beberapa ulama mengikuti metode penulisan tersebut seperti Muhammad bin Aslam al-Thusi, al-Hasan bin Sufyan al-Nasa’i, Abu Bakar al-Ajri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Ashfahani, al-Daruquthni, al-Hakim, Abu Nu’aim, dan lain sebagainya.
Motif Penulisan
Penulisan kitab arba’in oleh para ulama tersebut tidak serta merta berdasarkan kreatifitas belaka. Akan tetapi, adalah sebuah harapan mereka demi masuk pada golongan yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah dalam sabdanya;
من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء و العلماء
“Barangsiapa di antara umatku, yang hafal empat puluh hadis mengenai urusan agamanya, maka kelak pada hari kiamat, Allah akan membangkitkannya termasuk ke dalam golongan ahli fikih dan ahli ilmu.”
Baca juga: Inilah Keutamaan Shalat Menurut Al-Quran: Tafsir QS. Al-Ankabut [29] Ayat 45
Akan tetapi dalam mukadimahnya, Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis tersebut dinilai hadis dhaif oleh para ahli hadis meski banyak perawi yang meriwayatkannya dengan redaksi yang berbeda. Kendati, para ahli hadis juga bersepakat bolehnya mengamalkan hadis dhaif sebatas dalam perkara fadhail al-a’mal (keutaman-keutamaan suatu amal).
Arbain tentang Keutamaan Al-Quran
Barangkali di antara kitab al-arba’iniyyat yang paling masyhur adalah kitab arbain karya Imam Nawawi al-Damasyqi yang diberi anotasi (syarh) banyak sekali oleh para ulama. Sebut saja sebagai contoh kitab al-Majalis al-Sainiyyah karya Syaikh Ahmad al-Fasyani yang dikaji di berbagai pesantren tradisional. Lalu Imam Nawawi Banten juga memberi anotasi pada kitab ulama Damaskus tersebut.
Kepopuleran kitab Arbain Nawawi tersebut tidak bisa terlepas dari isinya yang membabarkan hadits-hadits ushul al-din, pondasi agama, yang menjadi bekal utama setiap muslim. Dengan demikian, kitab tersebut sangat penting diajarkan pertama kali sebelum umat islam mempelajari anasir-anasir ilmu agama lainnya.
Saya kira, kitab al-arba’iniyyat yang tak kalah pentingnya adalah kitab Arba’una Haditsan fi Fadhail Al-Quran al-Adzim (2005) karya Sayyid Abd al-Rahman bin Abdullah Balfaqih, Hadramaut, Yaman. Kitab ini memuat 40 (bab) hadis mengenai keutamaan-keutaman Al-Quran. Bisa disepakati kitab arba’in yang memuat tema istimewa ini sangat jarang. Kitab arba’in sebelumnya yang memuat tema Al-Quran ini adalah karangan Mulla Ali al-Qari al-Makki (1014 H) yang berjudul Faidh al-Mu’in ‘ala Jam’ al-Arba’in fi Fadhl al-Qur’an al-Mubin (1987 M).
Sayyid Abd al-Rahman Balfaqih lahir pada 1089 H di Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau merupakan seorang putra dari pasangan Sayyid Abdullah bin Ahmad, seorang pemuka Alawiyyin pada masanya dan Sayyidah Maryam, cucu Sayyid Abdurrahman al-Idrus. Mulanya, beliau belajar kepada ayahnya hingga usia sepuluh tahun, kemudian kepada kakeknya dari jalur ibu, Sayyid Muhammad al-Idrus. Setelah kepada kakeknya, beliau belajar kepada pamannya, al-Habib Abdurrahman al-Idrus.
Selain belajar kepada ayah, kakek dan pamannya, Sayyid Abdurrahman juga belajar kepada Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad (1044-1132 H) serta kepada ulama-ulama masyhur lainnya dari berbagai wilayah, seperti Yaman, Haramain(Makkah-Madinah) dan Syam. Tercatat puluhan lebih ulama yang menjadi guru beliau di berbagai negara. Di antara karya beliau adalah Risalah al-Murid, al-Shu’ud fi Tadzkirah al-Ukhuwah, Fath Bashair al-Mustarsyidin dan lain sebagainya.
Baca juga: Memahami Makna Kata Jaza dalam Al-Quran dan Penggunaannya
Sistematika Penyusunan
Kitab Arbauna Haditsan fi Fadhail Al-Quran ini disusun dengan sistematika sederhana sesuai penomoran dari satu hingga empat puluh. Setiap nomor dinukilkan satu atau beberapa hadis yang terkait. Biasanya adalah hadits yang memiliki makna sama namun dengan redaksi yang berbeda. Model ini dibuat untuk memudahkan pembaca mengeksplorasi kandungan makna yang berkenaan dengan suatu keutamaan Al-Quran pada tiap redaksi hadis.
Dengan demikian, meski penomoran pada kitab ini hanya empat puluh, akan tetapi hadits yang dicantumkan dalam kitab ini mencapai 132 hadits. Sayyid Abdurrahman dalam mukadimahnya telah mengutarakan bahwa dalam kitabnya tersebut tidak ada satu hadits pun yang cacat atau bahkan maudhu’. Namun setelah ditelusuri di berbagai kitab hadits babon, pen-tahqiq kitab ini menemukan beberapa hadits yang dinilai oleh para muhaddits sebagai hadis yang dhaif seperti pada hadits nomor 63, 65, 79.
Muhammad Bazib, sang pen-tahqiq kitab ini, mengatakan alasan kenapa hadits dhaif juga dikutip dalam kitab ini adalah sederhana, yakni penyandaran Sayyid Abdurrahman dalam menukil hadis dhaif tersebut kepada guru-gurunya dahulu, terutama pada kitab Kanz al-‘Ummal, anggitan Ali al-Muttaqi al-Hindi dan juga merujuk pada al-Jami’ al-Shaghir karya Jalaluddin al-Suyuthi. Biarpun, beliau telah berusaha menukil hadits-hadits dengan mengklasifikasinya dahulu sebelum dimasukkan ke dalam susunan kitabnya dan sebagian besar hadis dalam kitab beliau dapat digunakan sebagai hujjah.
Sisi lain yang menarik dari kitab ini adalah dilengkapi dengan anotasi atau catatan pada mufradat-mufradat yang sulit dan jarang digunakan (gharib) dan satuan kalimat yang rumit dipahami. Dengan begitu sidang pembaca dapat mudah memahami makna suatu hadis tanpa membuka kamus atau kitab pendukung lainnya. Wallahu A’lam.