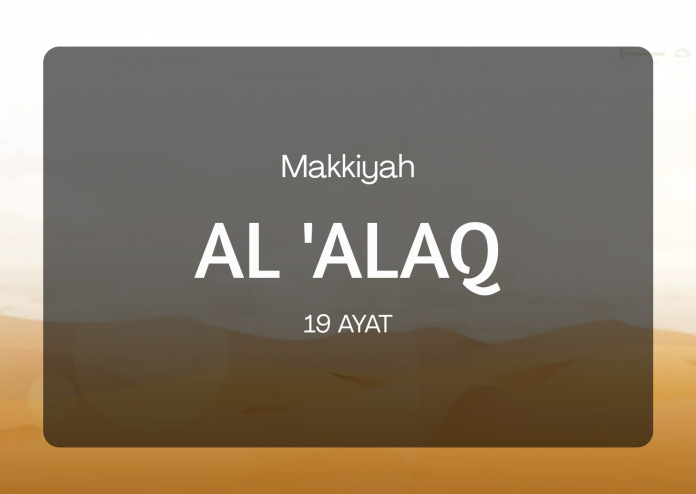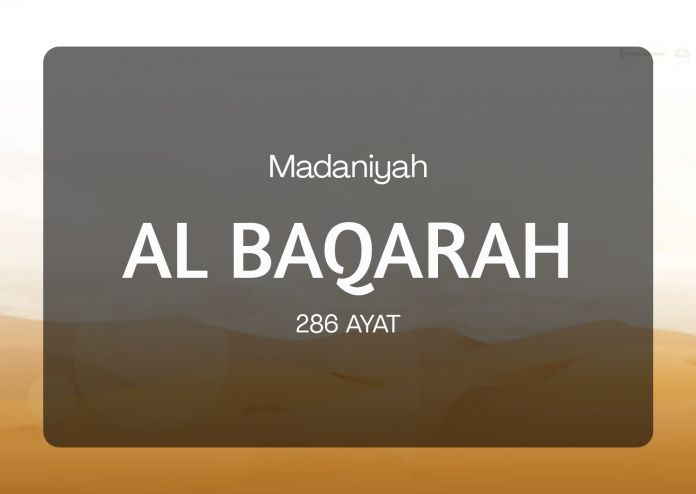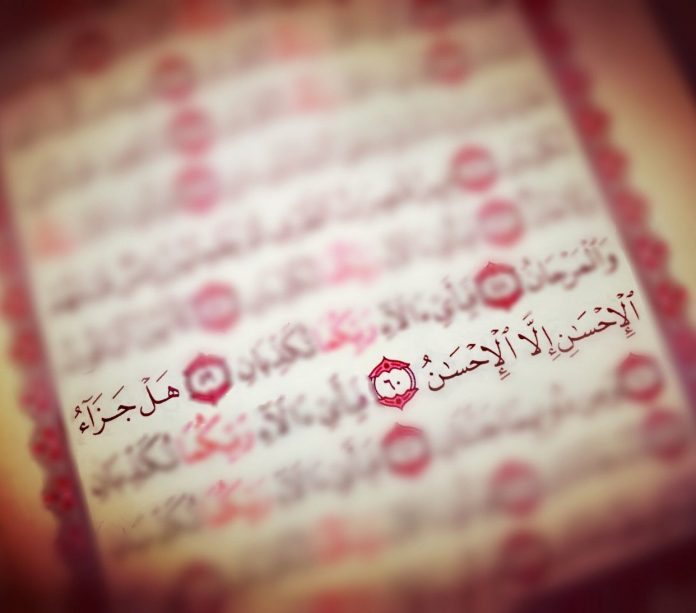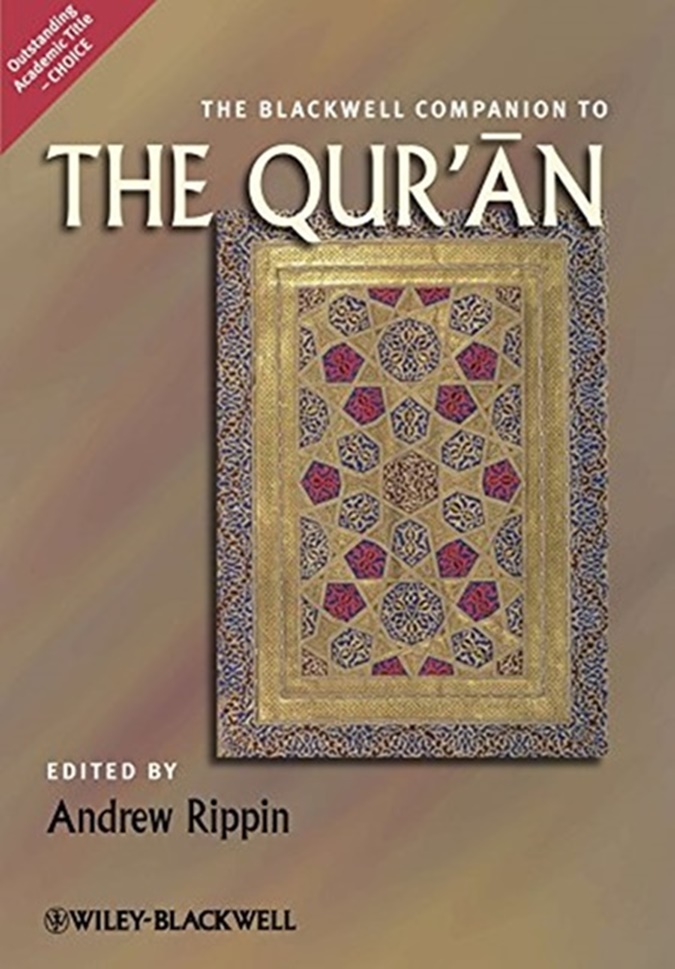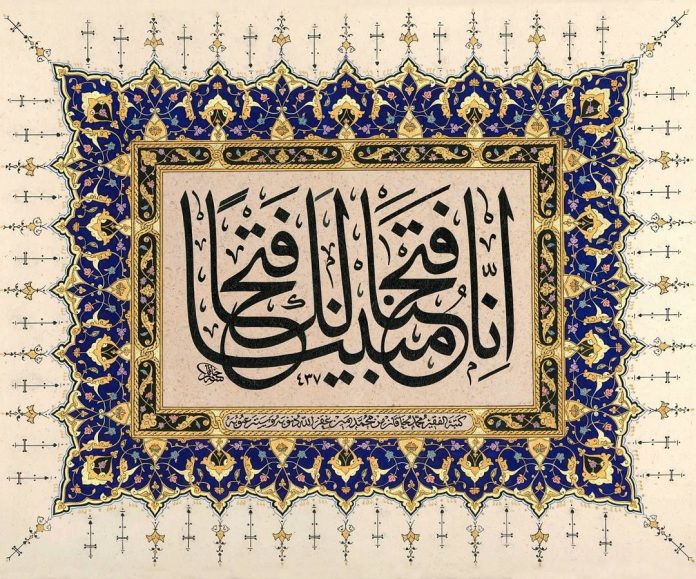Pada pembahasan yang lalu berbicara mengenai buah Tin dan Zaitun serta potensi yang dimiliki oleh manusia, selanjutnya Tafsir Surat Al ‘Alaq Ayat 1-7 berbicara mengenai proses pengetahuan dan penciptaan manusia.
Baca selanjutnya: Tafsir Surat Al Tin Ayat 4-8
Di awal pembahasan Tafsir Surat Al ‘Alaq Ayat 1-7 Allah swt memerintahkan kepada manusia untuk membaca. Membaca tersebut antara lain mempelajari, meneliti, mendalami, dan lain sebagainya. Objek pembacaannya meliputi segala ayat Allah, baik ayat-ayat Alquran maupun ayat-ayat alam semesta. Salah satu dari ayat Allah swt adalah proses penciptaan manusia.
Dalam Tafsir Surat Al ‘Alaq Ayat 1-7 anjuran untuk membaca disebut dua kali. Hal ini menandakan bahwa pembelajaran memang butuh proses. Tidak ujuk-ujuk langsung paham dan berhasil. Dari penyebutan sebanyak dua kali ini mengindikasikan untuk mengulang minimal dua kali. Namun sayangnya sebagian manusia terkadang mengingkari ayat-ayat Allah swt.
Ayat 1
Allah memerintahkan manusia membaca (mempelajari, meneliti, dan sebagainya.) apa saja yang telah Ia ciptakan, baik ayat-ayat-Nya yang tersurat (qauliyah), yaitu Alquran, dan ayat-ayat-Nya yang tersirat, maksudnya alam semesta (kauniyah).
Membaca itu harus dengan nama-Nya, artinya karena Dia dan mengharapkan pertolongan-Nya. Dengan demikian, tujuan membaca dan mendalami ayat-ayat Allah itu adalah diperolehnya hasil yang diridai-Nya, yaitu ilmu atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.
Ayat 2
Allah menyebutkan bahwa di antara yang telah Ia ciptakan adalah manusia, yang menunjukkan mulianya manusia itu dalam pandangan-Nya. Allah menciptakan manusia itu dari ‘alaqah (zigot), yakni telur yang sudah terbuahi sperma, yang sudah menempel di rahim ibu.
Karena sudah menempel itu, maka zigot dapat berkembang menjadi manusia. Dengan demikian, asal usul manusia itu adalah sesuatu yang tidak ada artinya, tetapi kemudian ia menjadi manusia yang perkasa. Allah berfirman:
وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ٢٠
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. (ar-Rµm/30: 20)
Asal usulnya itu juga labil, zigot itu bisa tidak menempel di rahim, atau bisa terlepas lagi dari rahim itu, sehingga pembentukan manusia terhenti prosesnya. Oleh karena itu, manusia seharusnya tidak sombong dan ingkar, tetapi bersyukur dan patuh kepada-Nya, karena dengan kemahakuasaan dan karunia Allah-lah, ia bisa tercipta.
Allah berfirman menyesali manusia yang ingkar dan sombong itu:
اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ٧٧
Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata! (Yasin/36: 77)
Menurut kajian ilmiah, ‘alaqah merupakan bentuk perkembangan pra-embrionik, yang terjadi setelah percampuran sel mani (sperma) dan sel telur. Moore dan Azzindani menjelaskan bahwa ‘alaqah dalam bahasa Arab berarti lintah (leech) atau suatu suspensi (suspended thing) atau segumpal darah (a clot of blood).
Lintah merupakan binatang tingkat rendah, berbentuk seperti buah per, dan hidup dengan cara menghisap darah. Jadi ‘alaqah merupakan tingkatan (stadium) embrionik, yang berbentuk seperti buah per, di mana sistem kardiovaskuler (sistem pembuluh-jantung) sudah mulai tampak, dan hidupnya tergantung dari darah ibunya, mirip dengan lintah.
‘Alaqah terbentuk sekitar 24-25 hari sejak pembuahan. Jika jaringan pra-embrionik ‘alaqah ini diambil keluar (digugurkan), memang tampak seperti segumpal darah (a blood clot like). Lihat pula telaah ilmiah pada penjelasan Surah Nµh/71 ayat 14.
Baca juga: Tafsir Surat Al-Mulk Ayat 5-7: Balasan Bagi yang Tak Patuh Perintah
Ayat 3
Allah meminta manusia membaca lagi, yang mengandung arti bahwa membaca yang akan membuahkan ilmu dan iman itu perlu dilakukan berkali-kali, minimal dua kali. Bila Alquran atau alam ini dibaca dan diselidiki berkali-kali, maka manusia akan menemukan bahwa Allah itu pemurah, yaitu bahwa Ia akan mencurahkan pengetahuan-Nya kepadanya dan akan memperkokoh imannya.
Ayat 4-5
Di antara bentuk kepemurahan Allah adalah Ia mengajari manusia mampu menggunakan alat tulis. Mengajari di sini maksudnya memberinya kemampuan menggunakannya. Dengan kemampuan menggunakan alat tulis itu, manusia bisa menuliskan temuannya sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan generasi berikutnya.
Dengan dibaca oleh orang lain, maka ilmu itu dapat dikembangkan. Dengan demikian, manusia dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahuinya, artinya ilmu itu akan terus berkembang. Demikianlah besarnya fungsi baca-tulis.
Ayat 6-7
Allah menyesali manusia karena banyak mereka yang cenderung lupa diri sehingga melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, yaitu kafir kepada Allah dan sewenang-wenang terhadap manusia.
Kecenderungan itu terjadi ketika mereka merasa sudah berkecukupan. Dengan demikian, ia merasa tidak perlu beriman, dan karena itu ia berani melanggar hukum-hukum Allah. Begitu juga karena sudah merasa berkecukupan, ia merasa tidak butuh orang lain dan merasa berkuasa, dan karena itu ia akan bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain itu.
Baca setelahnya: Tafsir Surat Al ‘Alaq Ayat 8-19
(Tafsir Kemenag)