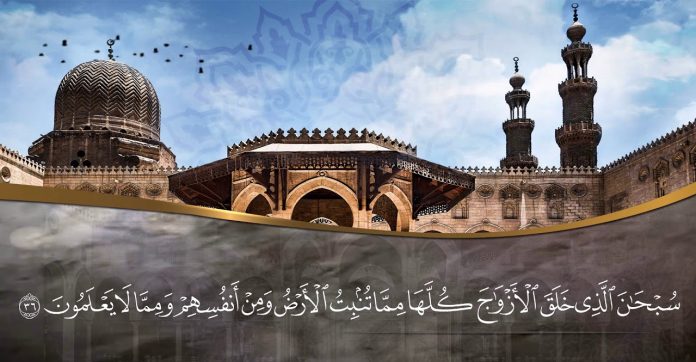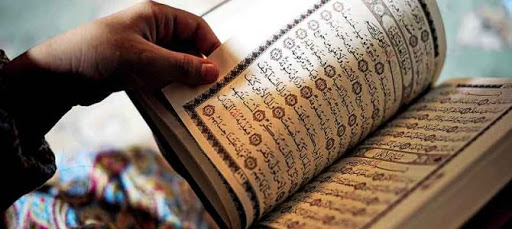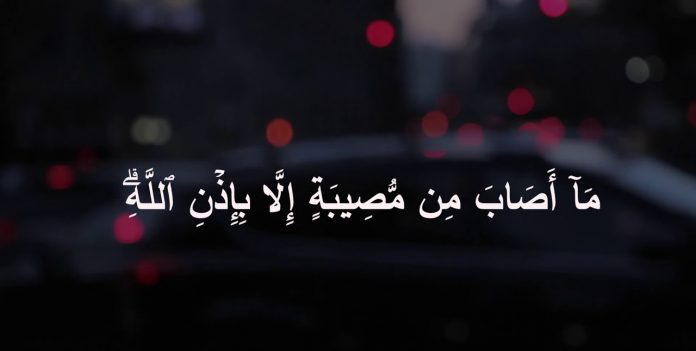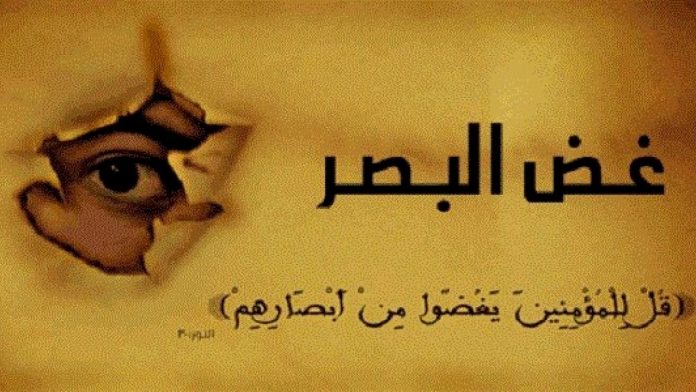Setelah memahami tentang definisi, klasifikasi, dan prasyarat yang dipenuhi dalam proses penafsiran corak sufistik. Maka, pada kesempatan kali ini penulis ingin melengkapi artikel sebelumnya dengan pembahasan terkait sejarah dan periodisasi perkembangan corak tafsir sufistik dalam beberapa masa yang telah disusun secara sistematis.
Awal Mula Kemunculan Corak Tafsir Sufistik
Penafsiran Al-Quran dengan menggunakan corak tafsir sufsitik bukanlah suatu hal yang baru. Telah dijelaskan pada artikel sebelumnya bahwa tafsir sufistik adalah proses penakwilan makna ayat dari makna lahir menuju makna batin. Pendekatan isyari dalam proses penafsiran Al-Quran sudah ditemukan sejak proses turunya Al-Quran pada masa Nabi. Isyarat tersebut telah dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa’ [4]: 78, Q.S. al-Nisa’ [4]: 82, dan Q.S. Muhammad [47]: 24.
Baca Juga: Mengenal Corak Tafsir Sufistik (1): Definisi, Klasifikasi dan Prasyarat yang Harus Dipenuhi
Semua ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Al-Quran terdapat makna lahir dan batin. Hal ini dikarenakan para kaum kafir Arab saat itu hanya memahami makna lahir saja, karena memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tetapi mereka tidak memahami maksud inti dari ayat Al-Quran tersebut, sehingga mereka lalai dan tidak mengakui eksistensi Allah.
Dalam kitab al-Ta’wilat al-Najmiyyah fi al-Tafsir al-Isyariy al-Shufiy karya Najmuddin al-Kubra. Dijelaskan bahwa terkait isyarat dari sabda Nabi, ditemukan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-Faryabi yang diriwayatkan oleh al-Hasan secara mursal kepada Nabi:
لِكُلِّ آيَةٍ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَلِكُلِّ حَرْفٍ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ
“setiap ayat (memiliki makna) lahir dan batin, dan disetiap huruf memiliki batasan, dan disetiap batasan tersebut terdapat pengantar/pembuka”
Selain itu, juga terdapat hadis Nabi yang dikeluarkan oleh al-Dailami dari riwayat yang disampaikan Abdurrahman ibn Auf secara marfu’ kepada Nabi:
القُرْآنُ تَحْتَ العَرْشِ لَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ يُحَاجُ العِبَادُ
“Al-Quran yang berada di bawah Arsy memiliki makna lahir dan batin yang dibutuhkan oleh para hamba”
Maksud dari kata dzahr adalah lafal ayat tersebut, sedangkan maksud dari kata Bathn adalah ta’wil dari ayat tersebut. Ibn al-Naqib menjelaskan bahwa yang dimaksud dari makna lahir adalah makna yang ditampakkan kepada para ahli ilmu. Sedangkan makna batin adalah makna yang mengandung rahasia-rahasia (al-asrar) yang hanya diberikan oleh Allah kepada ahli hakikat (ahl al-haqaiq).
Untuk lebih mudah memahami makna lahir dan batin, Abu Ubaid mengilustrasikan hal tersebut terhadap kisah-kisah dalam Al-Quran. Ia menjelaskan bahwa makna dzahir dari Qashash adalah pengetahuan tentang kisah umat-umat tedahulu dan kabar akan kehancuran mereka. Sedangkan makna bathin-nya adalah nasihat dan peringatan kepada umat saat ini agar tidak mengulangi apa yang dahulu mereka lakukan.
Implementasi dari adanya makna lahir dan batin dapat ditemukan dalam sebuah H.R. Bukhari no. 4970. Dijelaskan dalam riwayat tersebut, ketika Ibnu Abbas ditanya oleh Umar terkait makna dari Q.S. al-Nasr [110] ayat 1, ia tidak memaknai ayat tersebut sebagai suatu kegembiraan akan datangnya bantuan Allah bagi umat Islam. Tetapi ia justru menjawab bahwa ayat tersebut bermakna tentang pemberitahuan Allah terkait akan datangnya ajal Rasulullah Saw.
Baca Juga: Surat Al-Maidah Ayat 3: Isyarat Kewafatan Nabi Muhammad Saw
Sejarah Perekembangan Corak Tafsir Sufistik
Secara sistematis, dalam buku The Blackwell Companion to The Qur’an yang dieditori Andrew Rippin, Alan Godlas membagi periodisasi perkembangan corak tafsir sufistik menjadi lima fase:
- Fase Pertama (abad ke-2 H/8 M – 4 H/10 M)
Pada fase pertama ini merupakan fase dasar dari perkembangan interpretasi sufistik terhadap Al-Quran. Fase ini terbagi menjadi dua tahap, tahap pertama diawali oleh tiga tokoh sufi utama, yaitu: Hasan al-Bashri (w. 728 M), Ja’far al-Shadiq (w. 765 M), dan Sufyan al-Tsauri (w. 778 M).
Kemudian, pada tahap kedua dilanjutkan oleh Abu ‘Abdurrahman Muhammad al-Sulami (w. 937 M) penulis Haqaiq al-Tafsir. Tafsir tersebut memiliki rujukan utama terhadap pemikiran tujuh tokoh sufi ternama yaitu Dzu al-Nun al-Misri (w. 861 M), Sahl al-Tustari (w. 896 M), Abu Sa’id al-Kharraz (w. 899 M), al-Junaid (w. 910 M), Ibn ‘Ata’ al-Adami (w. 923 M), Abu Bakr al-Wasiti (w. 932 M), dan al-Syibli (w. 946 M).
- Fase kedua (abad ke-5 H/11 M – 7 H/13 M)
Memasuki era kedua ini, produk tafsir sufistik yang muncul terbagi menjadi tiga varian yang berbeda: pertama, Tafsir sufistik moderat, yaitu produk tafsir sufistik yang masih mencantumkan rujukan dari hadis Nabi, atsar Sahabat, dan mengutip beberapa pendapat dari para mufasir periode awal. Sehingga dalam tafsir tersebut masih terdapat kajian aspek kebahasaan, konteks historis, dan muatan ulumul Qur’an lainya. Contoh produk tafsir masuk kategori pertama ini adalah al-Kasyf wa al-Bayan ‘an Tafsir Al-Quran karya Abu Ishaq al-Tsa’labi (w. 1035 M), Lathaif al-Isyarat karya ‘Abdul Karim al-Qusyairi (w. 1074 M) dan Nughbat al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya Syihabuddin al-Suhrawardi (w. 1234 M).
Kemudian, varian kedua adalah produk tafsir yang dipengaruhi oleh hasil penafsiran dan pemikiran sufistik al-Sulami, seperti Futuh al-Rahman fi Isyarat Al-Quran karya Abu Tsabit al-Dailami (w. 1183 M), dan Ara’is al-Bayan fi Haqaiq Al-Quran karya Abu Muhammad Ruzbihan al-Shirazi (w. 1209 M). Terakhir, varian ketiga adalah produk tafsir sufistik yang ditulis dalam bahasa Persia, seperti Kasyf al-Asrar wa ‘Uddat al-Abrar karya al-Maybudi (w. 1135 M) dan karya tafsir dari al-Darwajiki (w. 1154 M).
- Fase Ketiga (abad ke-7 H/13 M – 8 H/14 M)
Pada fase ini, muncul dua tokoh sufi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan tafsir sufistik, yaitu Najmuddin al-Kubra (w. 1221 M) dengan karyanya yang berjudul al-Ta’wilat al-Najmiyyah fi al-Tafsir al-Isyariy al-Shufiy, dan Muhyiddin Ibn Arabi (w. 1240 M) dengan dua karya magnum opusnya, yaitu al-Futuhat al-Makkiyah dan Fushus al-Hikam. Dua tokoh sufi tersebut kemudian sama-sama membentuk madrasah tafsir sufistik masing-masing, yaitu madzhab Kubrawiyyun dan Madzhab Ibnu Arabi.
Beberapa tokoh sufi yang masuk dalam madzhab Kubrawiyyun adalah Nizamuddin Hasan al-Naisaburi (w. 1327 M) penulis Gharaib Al-Quran wa Raghaib al-Furqan. Sedangkan tokoh sufi yang mengikuti madzhab Ibnu Arabi adalah Ibn Barrajan al-Andalusi (w. 1141 M) pengarang al-Irsyad fi Tafsir Al-Quran.
- Fase Keempat (abad ke-9 H/15 M – 12 H/18 M)
Fase ini menjelaskan tentang produk tafsir sufistik yang dituli di India selama pemerintahan Turki Utsmani dan Dinasti Timurid. Beberapa karya tafsir sufistik tersebut adalah Tafsir Multaqat karya Khwajah Bandah Nawaz (w. 1422 M), dan Mawahib ‘Aliya karya Kamaluddin Husain al-Kasyifi (w. 1504 M).
Salah satu produk tafsir sufistik yang ditulis secara komprehensif pada era ini adalah Ruh al-Bayan karya tokoh sufi yang menghabiskan hidupnya di Istanbul dan Bursa yaitu Ismail Haqqi Bursevi (w. 1725 M). Tafsir tersebut menggabungkan antara dimensi makna eksoterik (dzahir) dan esoterik (bathin). Terkait sumbernya, Ismail mengutip beberapa karya tafsir aliran Kubrawiyyun dan puisi-puisi sufistik Persia karya Hafiz, Sa’di, Rumi, dan ‘Attar.
- Fase kelima (abad ke-13 H/19 M – sekarang)
Pada fase terakhir ini mulai terjadi proses penurunan produk tafsir yang menggunakan corak sufistik. Beberapa produk tafsir sufistik yang muncul pada masa ini adalah al-Bahr al-Madid fi Tafsir Al-Quran al-Majid karya tokoh sufi asal Maroko yang bernama Ahmad Ibn Ajiba (w. 1809 M), Ruh al-Ma’ani fi Tafsir Al-Quran al-’Adzim wa Sab’ al-Matsani karya Syihabuddin al-Alusi (w. 1854 M), Bayan al-Sa’adah fi Maqamat al-Ibadah karya Sultan Ali Shah (w. 1909 M) dan Bayan al-Ma’ani ‘ala Hasab Tartib al-Nuzul karya Abdul Qadir Mulla Huwaish (w. 1978 M).
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perkembangan corak tafsir sufistik dari masa ke masa terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Namun, sayangnya pada era akhir-akhir ini penafsiran Al-Quran dengan corak tafsir sufistik mulai mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan kesan negatif yang terlanjur melekat pada kata “sufi” yang dianggap sesat. Namun demikian, menurut Alan Godlas, kehadiran internet tidak dapat dipungkiri membuat banyak hasil-hasil penafsiran sufistik yang dimunculkan dalam berbagai portal online. Wallahu A’lam