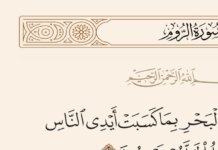Tatkala Raja Mesir tertarik dengan kemampuan Nabi Yusuf dan hendak menjadikannya salah satu pejabat Mesir, Nabi Yusuf tidak menolaknya malah justru meminta jabatan sebagai bendahara kerajaan. Sikap ini memunculkan diskusi tersendiri di antara para pakar tafsir. Di antara diskusi tersebut adalah, bagaimana pandangan Al-Quran terkait menjadi pejabat di bawah kepemimpinan non-muslim? Tidak banyak ahli tafsir menyinggung masalah ini di dalam tafsirnya. Tulisan ini akan mencoba mengemukakan pendapat Imam Al-Qurthubi terkait masalah ini.
Nabi Yusuf Menjadi Pejabat di Bawah Kepemimpinan Non-Muslim
Allah berfirman dalam Surat Yusuf Ayat 54-55
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ () قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
Dan raja berkata: “Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang dekatku”. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: “Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami”. Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. (QS. Yusuf [12]: 54-55).
Para ahli tafsir dalam beberapa kitab tafsir menerangkan, tindakan Nabi Yusuf meminta jabatan dalam ayat di atas bukanlah suatu kesalahan dan tidaklah bertentangan dengan keterangan hadis.
Hal ini disebabkan Nabi Yusuf melihat bahwa hanya dirinyalah yang dapat bertindak secara adil dan menerapkan hukum Allah pada jabatan tersebut. Maka bisa jadi Nabi Yusuf tidak memiliki pilihan selain meminta jabatan tersebut.
Baca Juga: Teladan Kisah Nabi Yusuf: Meminta Jabatan Boleh Asal Mampu Mendatangkan Kebaikan
Namun diskusi terkait tindakan Nabi Yusuf yang terkesan “tabu” itu tidak berhenti disitu. Diskusi berlanjut dengan persoalan bagaimana bisa Nabi Yusuf membiarkan dirinya bekerja di bawah kepemimpinan non-muslim? Bukankah berkerja di bawah kepemimpinan raja yang tidak mengerti hukum Islam, hanya akan berujung membantu terlaksananya kebijakan-kebijakan yang bisa jadi bertentangan dengan hukum Islam?
Komentar Imam Al-Qurthubi
Sebelum ke pendapat Imam Al-Qurthubi, Al-Qasimi mengutip pendapat Mujahid bahwa Raja yang berkuasa pada masa Nabi Yusuf itu sudah masuk Islam. Jika seperti ini maka tidak ada persoalan berikutnya. Namun jika belum masuk Islam, ini kemudian yang dikomentari lebih lanjut oleh Al-Qurthubi.
Imam Al-Qurthubi mengutip pendapat sebagian ulama’, bahwa di dalam ayat di atas ada petunjuk yang membolehkan seseorang yang mulia, menjadi pejabat di bawah kepemimpinan non-muslim, bahkan pemimpin yang zalim sekalipun.
Tindakan tersebut diperbolehkan selama ia tahu bahwa sang pemimpin tidak memintanya mengerjakan sesuatu yang bertentangan dirinya, sehingga ia bisa melakukan “perbaikan-perbaikan” pada hal-hal yang dikehendakinya. Berbeda bila kemudian sang pemimpin memintanya mengerjakan sesuatu berdasar kehendaknya yang melenceng dari kebenaran, maka tidak boleh (Tafsir Al-Qurthubi/9/181).
Baca Juga: Ibrah Kisah Nabi Yusuf, Penjara sebagai Sarana Mendekatkan Diri kepada Allah
Di dalam keterangan di atas, kutipan Imam Al-Qurthubi tidak membahasakan “sang pejabat” sebagai seorang muslim. Namun sebagai orang yang mulia “al-Fadhil”. Hal ini bisa jadi menunjukkan bahwa tindakan seorang yang soleh bekerja di sebuah lembaga yang dipimpin oleh orang muslim yang zalim atau non muslim, tidak lantas akan mencederai kesolehannya.
Juga, kutipan Imam Al-Qurthubi tidak bicara hanya terkait bekerja di lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh seorang muslim yang zalim, tapi juga non-muslim. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan akidah tidak menjadi penghalang seorang muslim bekerja di lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh seorang non-muslim.
Asal dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan, ia tidak di bawah kendali penuh sang pemimpin. Dalam arti harus melaksanakan kebijakan sang pimpinan meski itu bertentangan dengan syariat Islam yang dianutnya.
Imam Al-Qurthubi di dalam tafsirnya juga sempat menyinggung, bahwa ada beberapa ulama’ yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan Nabi Yusuf hanya diperbolehkan khusus pada Nabi Yusuf saja. Untuk zaman sekarang, hal itu tidak diperbolehkan.
Namun Imam Al-Qurthubi kemudian menyatakan bahwa pendapat yang pertama, yaitu yang menyatakan boleh dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh beliau dan tidak terkhusus pada diri Nabi Yusuf, itu lebih kuat.
Baca Juga: Kisah Kesabaran Nabi Yusuf Yang Membuat Kagum Nabi Muhammad
Pandangan-pandangan yang dikemukakan Imam Al-Qurthubi ini memberi tahu kita bahwa Islam tidak melarang kita menjadi pejabat di sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh orang Islam yang zalim dan bahkan non-muslim.
Hanya saja, hukum ini memiliki syarat, yaitu asal tindakan kita tidak kemudian justru ikut membantu terlaksananya kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat, serta dengan harapan jabatan dan amanah tersebut dapat mempermudah kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan tata aturan pemerintahan yang tidak sesuai dengan agama Islam.
Tidak terlalu berbeda dengan penjelasan Al-Qasimi dalam Mahasin At-Ta’wil, ia mengutip pendapat dari Qatadah bahwa keputusan Nabi Yusuf untuk menjadi pejabat di bawah kepemimpinan non-muslim itu menunjukkan bahwa hal yang serupa itu boleh, tentu dengan syarat seperti sebelumnya. Wallahu A’lam