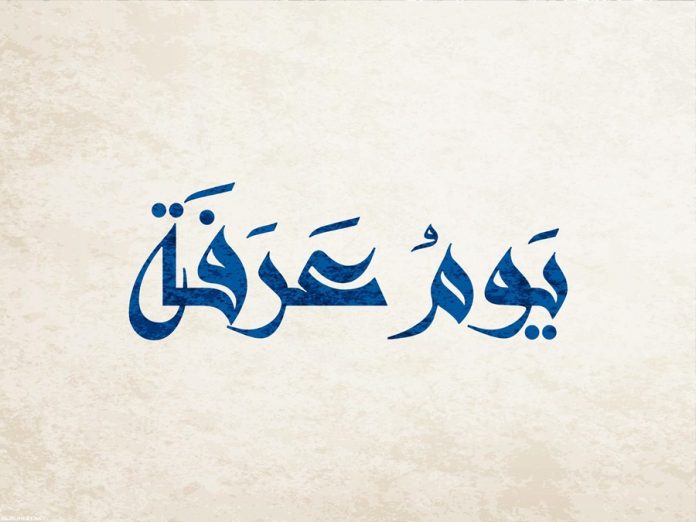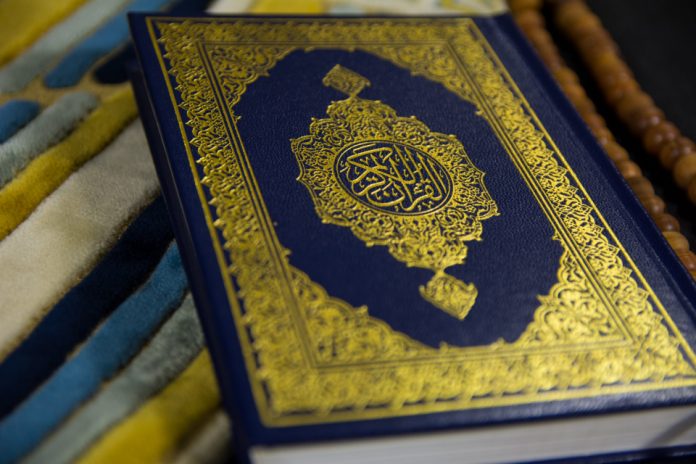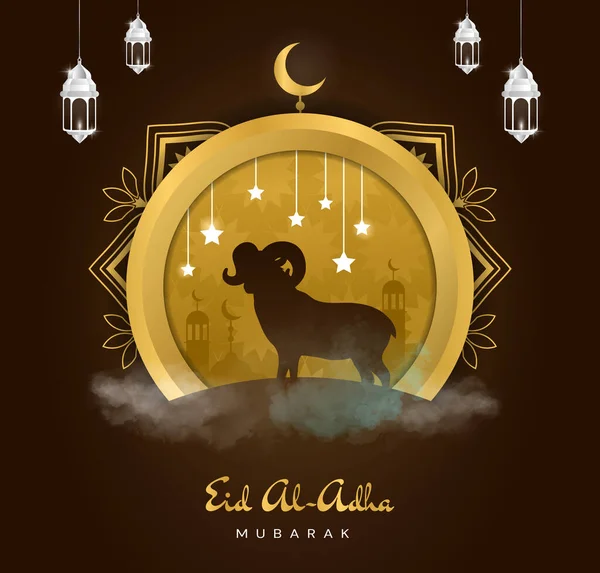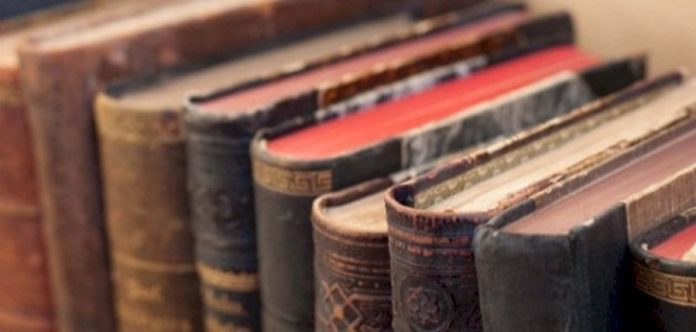Islam mengajarkan kita untuk memaknai suatu momentum dalam sejarah, menjadikannya semangat untuk perbaikan diri menjadi lebih bermanfaat dan progresif di jalan yang diperintahkan Allah. Hari ini, hari Arafah, adalah momentum di mana Nabi Ibrahim a.s. menyadari bahwa perintah untuk mengurbankan putera beliau adalah dari Allah.
Sebagai pengingat akan momentum Arafah, Nabi Muhammad saw. mengajarkan kepada kita untuk menandainya dengan berpuasa. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah, Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa puasa hari Arafah akan dihitung oleh Allah sebagai penebus dosa satu tahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Berikut redaksi hadis beliau.
صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ
Kiranya penting bagi umat Islam untuk kembali mengingat momen Arafah terjadi. Hal ini dilakukan sebagai gambaran bagi umat teologis Nabi Ibrahim a.s. ini untuk juga menemukan momentum kesadaran dalam diri bahwa tiada Tuhan selain Allah.
Baca Juga: Empat Artikel Pilihan terkait Kisah Awal Mula Ibadah Kurban
Sejarah Hari Arafah
Pada malam tarwiyah Nabi Ibrahim bermimpi seakan ada yang berkata, ‘sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk mengurbankan anakmu ini’. ketika beliau bangun dari tidur beliau memikirkan apakah mimpi tersebut benar dari Allah ataukah godaan dari setan. Oleh karenanya kemudian hari ini dinamakan tarwiyah yang diambil dari kata tarawwa yang bermakna mempertimbangkan, memikirkan, tidak menyegerakan.
Di malam selanjutnya beliau bermimpi kembali untuk kedua kalinya sehingga beliau mengerti bahwa mimpi itu dari Allah. Oleh karenanya hari ini disebut sebagai hari Arafah, saat ketika beliau mengerti datangnya perintah dari Allah. Pada malam yang ketiga beliau bermimpi kembali sehingga tekadnya bulat untuk melaksanakan kurban pada hari itu. Oleh karenanya hari tersebut dinamakan yaum al-nahr atau hari kurban.
Tanpa adanya kesadaran yang terjadi pada hari Arafah bisa jadi perintah kurban tidak akan pernah terlaksana. Momen munculnya kesadaran Nabi Ibrahim a.s. ini identik dengan gambaran ketika beliau menyadari akan hakikat ketuhanan.
Baca Juga: Kisah Nabi Ibrahim As dalam Q.S al-An’am Ayat 75-79 dan Ajaran Tauhid
Tahap Pertama Arafah: Kesadaran hingga Ilmu
Dikisahkan dalam surah al-An’am ayat 75-79, ketika Nabi Ibrahim a.s. diperlihatkan kuasa Allah, yaitu langit dan bumi sehingga beliau termasuk orang yang yakin akan-Nya. Saat malam menutupinya beliau melihat gumintang, berkata bahwa itu adalah tuhannya, ketika tenggelam bintang itu beliau katakan, ‘aku tidak mencintai hal-hal yang menghilang tenggelam.
Ketika cahaya rembulan bersinar beliau katakan, ‘inilah tuhanku’. Saat ia terbenam beliau katakan, ‘jika tuhanku tidak memberiku petunjuk pasti aku akan menjadi kaum yang tersesat.
Tatkala mentari terbit bersinar beliau katakan, ‘ini tuhanku, ini paling besar. Ketika ia terbenam beliau berkata, ‘kaumku sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Aku hadapkan wajahku pada Sang Pencipta langit dan bumi secara benar, dan aku bukanlah orang musyrik.’
Kesadaran akan hakikat ketuhanan ini meniscayakan beliau untuk menyeru kepada kaumnya tentang hal fundamental yang mereka tinggalkan terutama kepada ayahnya. Dalam surah Maryam ayat 43 disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim a.s. meyakinkan Azar ayahnya mengenai ilmu yang datang kepadanya.
يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا
“Ayah, sungguh telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak engkau dapatkan, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjuki engkau jalan yang benar.”
Terdapat proses pertimbangan hingga kemudian keyakinan akan ketuhanan hadir melalui kesadaran, pengenalan atau kearifan yang terserap dari kata arafa. Kesadaran tersebut mengkristal menjadi ilmu, pengetahuan akan esensi dari suatu hal. Arafa menurut al-Raghib al-Asfihani meniscayakan adanya suatu proses sehingga sifat ‘arif’ cocok bagi manusia dan mustahil bagi Allah. Arif meskipun positif bukanlah salah satu dari sifat Allah karena Dia tidak membutuhkan proses, Dialah al-‘Alim Yang Maha Mengetahui.
Baca Juga: Nabi Ishaq atau Nabi Ismail yang Dikurbankan? dari Kemuliaan Nasab hingga Toleransi
Pembuktian Nabi Ibrahim Pascaarafah
Kearifan Nabi Ibrahim a.s. tentang hakikat ketuhanan dapat dikatakan sebagai awalan dari momentum Arafah. Tahap pertama ini tidak menjadi hal yang berada pada level untuk ditandai sebagai momentum puncak Arafah. Hal ini karena kesadaran saja tidak cukup, butuh aksi nyata untuk membuktikan bahwa kesadaran akan keyakinan tersebut benar.
Adapun aksi nyata yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. untuk membuktikan kearifannya akan hakikat ketuhanan adalah pengurbanan putera yang beliau cintai. Bukan hanya diuji dengan kehilangan hal yang paling beliau cintai, dalam Tafsir al-Tsa’labi disebutkan bahwa beliau juga diuji dengan datangnya setan yang meyakinkan bahwa mimpi beliau adalah palsu.
Menjelma sebagai manusia, iblis menemui Ibrahim a.s. bertanya hendak ke mana dia menuju dan dan dijawab bahwa dia hendak menjalankan keperluan di gunung. Iblis pun mengatakan, ‘demi Allah, aku melihat setan datang dalam mimpimu dan memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu.’ Nabi Ibrahim a.s. pun mengusir iblis itu, namun iblis tetap saja menghalanginya.
Hingga sampai di jumrah al-aqabah lalu beliau melemparinya dengan tujuh kerikil sampai iblis pergi. Ketika sampai di jumrah al-wustha, si iblis datang lagi lalu beliau melemparinya dengan tujuh kerikil hingga dia pergi. Sampai pada jumrah al-kubra, iblis datang dan dilempari lagi oleh Nabi Ibrahim a.s. sampai pergi kemudian beliaupun melaksanakan perintah Allah. Godaan dan yang datang kepada Nabi Ibrahim a.s. saat itu sungguh berat, ditambah beliau juga akan kehilangan putera yang dicintai. Ujian berat ini dimaktubkan dalam surah al-Shaffat ayat 106.
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ
“Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata.”
Kearifan Nabi Ibrahim a.s. akan perintah Allah serta keteguhan beliau dalam menjalankannya menjadi satu gambaran peristiwa monumental. Godaan iblis dapat terasa begitu perih jika diakumulasikan dengan perasaan cinta akan puteranya. Kehilangan hal yang dicintai tentunya merupakan hal yang menyakitkan dan Nabi Ibrahim arif, tiada yang patut dicintai melebihi-Nya, dan terjadilah pengorbanan bersejarah.
Rumi berkata dalam Matsnawi bahwa segala sesuatu yang datang menyenangkanmu akan mengalihkanmu dari Allah. Hanya dari-Nya saja kau gembira, selain-Nya jangan. Dia adalah musim semi dan selain-Nya hanyalah musim dingin yang kelam. Dalam Muwattha’ Imam Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda.
أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ: أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ
“Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah, perkataan paling utama yang kuucapkan serta para nabi sebelumku adalah tiada Tuhan selain Allah yang Esa tiada sekutu bagi-Nya.”
Kearifan dapat menjadi pintu untuk teguh mencapai tujuan, dengan pertolongan Allah, semoga kita diselamatkan dari segenap ujian untuk mencapai ridha-Nya. Wallahu a’lam